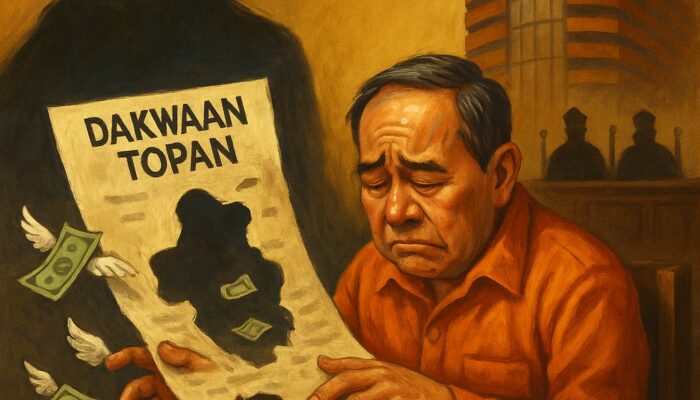Selain temuan Rp2,8M dan senjata api milik Topan, jaksa KPK tak ungkap pembayaran Rp1,3M di Bank Sumut berlabel “Sipiongot DP 7,5”.
Sidang korupsi menghadirkan terdakwa mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, digelar. Namun ketika Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno membacakan surat dakwaan Nomor 57/TUT.01.04/24/11/2025 atas nama Topan dan Kepala UPTD Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar—satu berkas setebal 25 halaman—publik justru disuguhi versi fakta yang kering, banyak detail “hilang” dibanding fakta-fakta lebih menggigit yang muncul di pemeriksaan awal dan sidang sebelumnya.
Dakwaan hanya mencatat Topan menerima Rp50 juta tunai dan “komitmen fee” 5% (4% untuk Topan, 1% untuk Rasuli), seolah itulah seluruh aliran uang ke sang kadis. Padahal saat OTT, pejabat KPK Asep Guntur terang menyebut kesepakatan fee 10–20% dari total proyek jalan Rp231,8 miliar, dengan proyeksi suap sekitar Rp46 miliar dan jatah Topan saja diperkirakan bisa mencapai Rp8 miliar. Ke mana raibnya selisih belasan miliar ini, dan mengapa dakwaan justru menyusutkan fakta?
Pada penggeledahan rumah Topan di Perumahan Royal Sumatera, penyidik menyita Rp2,8 miliar serta dua senjata api. Uang dan senjata itu mestinya menjadi barang bukti penting, apalagi bisa mengindikasikan korupsi lain yang belum terungkap. Anehnya, dakwaan sama sekali tak menyinggung temuan itu. Mengapa KPK mengabaikan barang bukti yang boleh jadi berasal dari proyek lain, dan bahkan lupa menyebutkan status rumah mewah di kawasan elit Royal Sumatera?
Sidang menghadirkan fakta adanya “uang klik” atau uang klik e katalog. Staf UPTD Gunung Tua Ryan Muhammad membeberkan bahwa Rasuli memintanya menyiapkan 0,5 % (sekitar Rp450 juta) sebagai “biaya klik e katalog” di luar 4 % dan 1 %. IDN Times menulis bahwa uang itu dialokasikan untuk memastikan paket proyek diunggah di e katalog. Praktik ini jelas menambah beban pengusaha, namun dakwaan tak menyebutnya. Juga tidak ada keterangan berapa jumlah total “uang klik” yang masuk ke kantong siapa. Lagi lagi, fakta yang sengaja hilang?
Lagi lagi dalam persidangan, terungkap adanya pembayaran Rp1,3 miliar di Bank Sumut bertuliskan “Sipiongot DP 7,5”. Komisaris PT Dalihan Natolu Group, Taufik Hidayat, mengaku menyerahkan uang itu kepada seseorang yang tak dikenal atas perintah Direktur Akhirun. Jaksa pun bingung, kode “Sipiongot DP 7,5” ini merujuk ke siapa. Seorang saksi menduga uang tersebut berkaitan dengan seseorang bernama Lulung (atau Lung Lung), namun identitasnya belum terungkap. Anehnya, dakwaan Topan tidak menyinggung aliran Rp1,3 miliar ini.
Topan Ginting dan Rasuli dijerat pasal sama, seolah setara. Padahal saksi menyebut Topan pengendali: memainkan paket sebelum dokumen lengkap, mengubah spesifikasi DS3 ke DS4 agar dua perusahaan menang, menayangkan paket di SIRUP dan e-katalog tanpa HPS atau KAK, serta menetapkan pemenang enam jam. Ryan: instruksi “uang klik” dari Topan. Namun dakwaan hanya menyorot penerimaan hadiah dan mengabaikan kejahatan: menyisipkan proyek lewat pergeseran anggaran di luar APBD yang diteken TAPD dan gubernur tanpa permintaan bupati, memulai pekerjaan sebelum tender selesai, mengatur pertemuan dengan penyedia, memanipulasi e-katalog, membuat kontrak tanpa menayangkan di LPSE, serta menggeser anggaran empat kali mendesak tanpa dokumen pendukung.
Dalam persidangan, hakim menyebut Topan punya “kekuatan super” karena bisa mengubah anggaran tanpa prosedur. Fakta-fakta yang hilang memunculkan pertanyaan: benarkah Topan aktor tunggal? Ada pihak lain yang pantas dimintai pertanggungjawaban: Tim TAPD Sumut—Sekda, Bappeda, BKAD—yang menyetujui pergeseran anggaran dan wajib menjelaskan dasar memasukkan proyek jalan ke Pergub; Gubernur Sumut yang menandatangani Pergub pergeseran anggaran (enam kali) tanpa perencanaan; Akhirun, Taufik Hidayat, dan Lung Lung, penerima Rp1,3 miliar, yang keterangannya soal “DP Sipiongot 7,5” harus diurai; Ketua PBJ/LPSE Sumut yang membiarkan e-katalog dimanipulasi hingga paket tayang tanpa dokumen.
Hilangnya fakta ini bukan kelalaian, melainkan sinyal keengganan jaksa KPK menyentuh aktor lebih besar. Apa arti Rp2,8 miliar, dua senjata, 0,5% “uang klik”, dan komitmen fee 10–20% bila hanya dijadikan pernak-pernik? Pengadilan korupsi seharusnya tidak berhenti pada “akad nikah” Rp50 juta, tetapi merunut alur uang, kebijakan anggaran, dan permainan e-katalog.
Dengan segala kelucuan dan kedunguan ini, rakyat Sumut pantas bertanya: apakah pemberantasan korupsi hanya memakai model diskon? Dari 20 % menjadi 5 %; dari Rp2,8 miliar menjadi hilang; dari 4 % plus 1 % ditambah 0,5 % menjadi cuma 5 %. Publik mengingatkan: jika pengusutan hanya sampai pinggir, mengesampingkan aktor-aktor penting di balik rencana kejahatan itu, maka sistem korupsi akan terus mulus seperti jalan tol–tanpa lubang– untuk pejabat berakal bulus sekelas gubernur dan antek-anteknya. Ada apa dengan KPK?