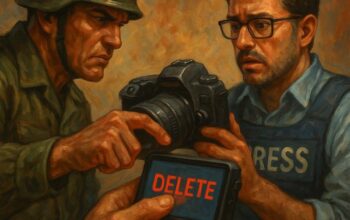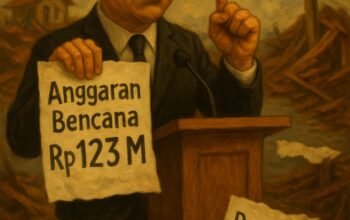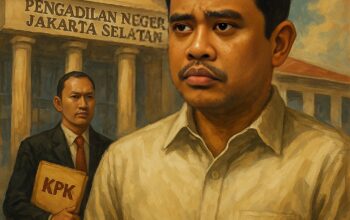Ripin adalah simbol bagi jutaan orang yang takut mati bukan karena ajal, tapi karena tak mendapatkan keadilan setelahnya.
Kematian bukanlah akhir. Dalam beberapa kasus, kematian justru membuka tabir kebusukan yang tersembunyi rapi di balik seragam dan institusi. Itulah yang terjadi pada Ripin alias Achien, pemuda 23 tahun yang ditemukan tewas di Emplasmen Kualanamu, Deliserdang. Tragedi ini seharusnya menjadi momen introspeksi dan koreksi dalam sistem penegakan hukum kita. Namun, yang muncul justru kebisuan, kebuntuan logika penyidikan, dan kekacauan moral yang sulit dijelaskan.
Sudah lebih dari 70 hari sejak jasad Ripin ditemukan. Namun hingga hari ini, tak satu pun tersangka ditetapkan. Pra-rekonstruksi telah dilakukan. Dua saksi kunci—Juwita dan Kelvin—telah dikenal sejak awal. Tapi mobil Fortuner yang mengantar Ripin ke takdirnya tetap dibiarkan bebas berkeliaran tanpa disita. SIM card para saksi malah dikembalikan sebelum dilacak secara digital. Fakta-fakta ini bukan hanya janggal, melainkan membunuh akal sehat.
Dalam era ketika hukum semestinya disinergikan dengan sains, penyelidikan kasus pembunuhan Ripin justru berjalan dengan pendekatan yang nyaris feodal. Padahal kita telah memiliki metode Scientific Crime Investigation (SCI)—pendekatan ilmiah yang mengandalkan jejak DNA, sidik jari, toksikologi, digital forensik, dan rekonstruksi canggih berbasis data. Pertanyaannya: mengapa pendekatan ini seakan absen dalam kasus Ripin?
Mari tengok kasus di Inggris. Pada tahun 1993, pembunuhan Stephen Lawrence nyaris tenggelam dalam kelambanan polisi. Namun bukti mikroskopik pada jaket korban—awalnya diabaikan—akhirnya membuka jalan menuju keadilan. Di Indonesia ada kasus Mirna Salihin—diungkap karena kemampuan polisi membaca jejak digital dan zat kimia di tubuh korban, bukan karena saksi. Di kedua kasus tersebut, hukum bekerja karena sains tidak disingkirkan.
Maka yang membebani publik hari ini bukan hanya soal lambatnya penyidikan, melainkan soal kegagalan fundamental penyidik dalam memahami zaman. Ini bukan era pengakuan. Ini era pembuktian. Dan ketika penyidik gagal merakit bukti, menafsirkan data, atau bahkan menyita alat vital kejahatan, kita tak sedang menghadapi keterbatasan, melainkan kehampaan kompetensi.
Lebih gawat lagi, aroma intervensi pun mulai tercium samar. Asuransi jiwa. Uang besar. Hubungan kekuasaan. Semua ini memperkeruh lanskap penyidikan yang sudah buram sejak awal. Dan ketika publik mulai lebih percaya pada opini netizen daripada rilis resmi kepolisian, maka yang runtuh bukan hanya reputasi institusi, melainkan legitimasi hukum itu sendiri.
Kini, nama Ripin tak lagi cuma identitas korban. Ia telah menjelma menjadi cermin retak dari sistem keadilan kita: rapuh, keruh, dan terancam kehilangan arah. Ia adalah simbol bagi jutaan orang yang takut mati bukan karena ajal, tapi karena kemungkinan tak akan pernah mendapatkan keadilan setelahnya.
Maka kita wajib bertanya lantang: apakah Polresta Deliserdang masih mampu berdiri di atas pilar ilmu dan etika? Ataukah ia telah rebah, bersimpuh pada tekanan, kekuasaan, dan kompromi tak bermoral?
Jika keadilan untuk Ripin yang jejak kematiannya bersisian dengan klaim asuransi jiwa gagal ditegakkan, maka hukum bukan lagi instrumen kebenaran. Ia hanya akan menjadi panggung absurditas yang dimainkan oleh mereka yang kuat, untuk memperdaya keluarga Ripin yang lemah.
Dan dalam teater absurd ini, kita telah tahu siapa yang jadi sutradara, siapa yang jadi aktor, siapa yang jadi penonton—dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya.
Sebab jika keadilan tak ditegakkan hari ini di kasus Ripin, maka ia akan mati dua kali: sekali di tangan pembunuh—dan sekali lagi di tangan polisi yang diam, yang sejatinya menjaga hukum itu sendiri!