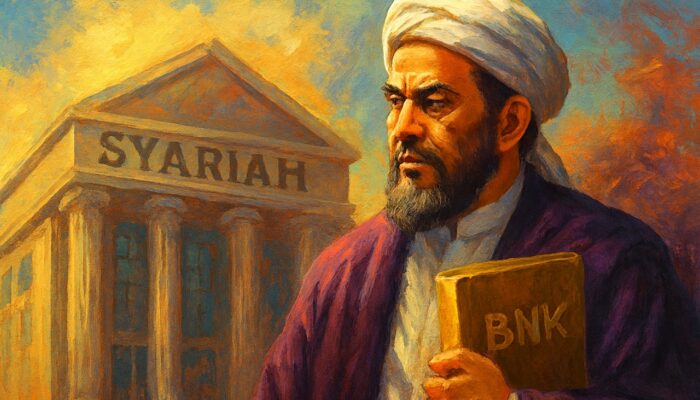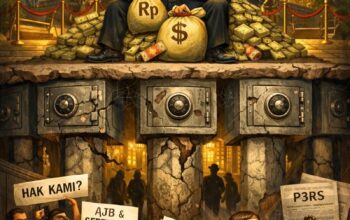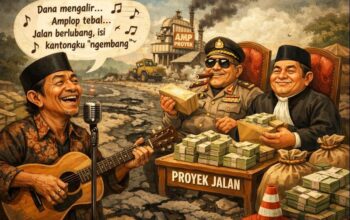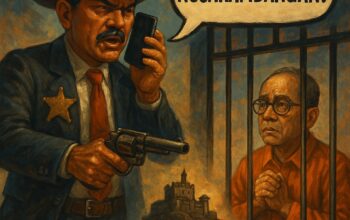Mana bedanya akad ijarah, murabahah, atau musyarakah, jika kasir di bank syariah saja mengartikan “ijarah” sebagai kain basahan?
Tawa ringan mengiringi pernyataan Tengku H. Faisal Ali, ketua MPU Aceh, di Lhoksukon—Bank Aceh dan BSI disebut “muallaf” yang masih belajar Islam. Namun tawa itu meredup ketika realitas menyentak: dua institusi keuangan kebanggaan Aceh, yang mengusung label syariah, justru dikritik keliru memainkan skema pembiayaan. Retorika ulama tersohor menampar kesadaran, bahwa berjubah syariah tidak lantas menghentikan praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur’an.
Muamalah pada dasarnya bukan aib, melainkan kekurangan mendasar dalam penerapan syariah. Sebab, syariah banking sejatinya harus bebas unsur bunga, ketidakpastian, dan spekulasi. Namun persoalan muncul ketika masyarakat Aceh Utara bertanya: mana bedanya akad ijarah, murabahah, atau musyarakah, jika kasir di bank syariah saja mengartikan “ijarah” (bahasa Aceh) sebagai kain basahan?
Sebuah bank syariah idealnya menegakkan prinsip akhlak ekonomi Islam: uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tidak diperdagangkan layaknya komoditas yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (spekulasi). Implementasi akad murabahah (jual beli dengan margin) dan mudharabah (bagi hasil) haruslah transparan serta adil untuk semua pihak.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Larangan riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 semakin menggarisbawahi bahwa bunga, bukan profit-sharing, adalah akar dari ketidakadilan finansial yang dikecam Al-Qur’an.
Data OJK menunjukkan bahwa industri perbankan syariah nasional tumbuh pesat, dengan peningkatan aset sekitar 15 persen per tahun. Namun di Aceh, percepatan belajar syariah itu terhambat budaya muallaf internal: pegawai lama yang terbiasa dengan sistem konvensional belum teredukasi penuh akan kaidah ushul fiqh muamalah.
Ketika citra dan realitas saling berseberangan, nasabahlah yang menanggung akibatnya. Kebingungan publik tentang skema pembiayaan memicu desas-desus: akad syariah hanyalah bungkus manis, sementara bunga konvensional diam-diam ditransfer ke margin bank. Celah inilah yang memunculkan label “riba tersembunyi”.
Reformasi struktural mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh dan BSI sejatinya berperan sebagai penjamin kehalalan produk dan mutu pendidikan syariah internal. Namun fungsi pengawasan hanya efektif jika diiringi komitmen pelatihan menyeluruh—dari direksi sampai petugas lapangan—tentang mekanisme murabahah, musyarakah, ijarah, dan istisna yang sesuai madhab Syafi’i maupun kaidah ushul fiqh muamalah.
Keterlambatan memetakan fatwa otoritatif di tingkat MPU Aceh tak hanya melemahkan posisi bank syariah lokal, tetapi juga menggoyahkan keyakinan masyarakat. Tanpa kejelasan legal opinion, konsensus Aceh menjalankan syariat Islam di setiap sektor akan menjadi jargon politis belaka. Hal ini berpotensi menggeser kepercayaan umat ke alternatif non-syariah, bahkan ke lembaga informal yang rawan eksploitasi.
Kritik ini bukan sentilan. Akhirnya, pertanyaan moral pun muncul: jika berjubah syariah tetapi menjual riba dalam bungkus akad, apa bedanya dengan konvensional? Mari berhenti tertawa ringan. Syariah bukan status mualaf yang membolehkan salah langkah selamanya. Syariah adalah panggilan etika, tuntutan keadilan, dan janji kesejahteraan bersama.
Sudahkah kita mendidik calon karyawan perbankan syariah dengan khazanah fiqh muamalah yang otoritatif? Sudahkah fatwa syariah lokal menghadirkan kepastian hukum atau hanya menjadi pajangan seremonial? Jangan biarkan Bank Aceh dan BSI berjubah syariah tapi dalam praktiknya berubah menjadi sandiwara riba. Refleksikanlah: keadilan finansial memerlukan lebih dari gelar “syariah”—ia memerlukan kesungguhan penghijrahan nilai dalam setiap transaksi. Agar kita semua (bank dan nasabah) selamat di dunia, selamat pula di akhirat.