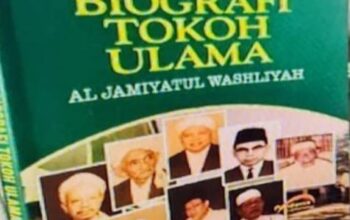Oleh: Farid Wajdi
Ada ironi sunyi yang kini menjelma pemandangan sosial: warga melapor kehilangan, orang pingsan, kucing terjebak, hingga pertikaian rumah tangga bukan ke polisi, melainkan ke pemadam kebakaran.
Damkar, lembaga yang semestinya hadir saat api menyala, justru menjadi alamat pertama saat negara seharusnya hadir melalui kepolisian.
Fenomena ini bukan sekadar lelucon media sosial. Ia penanda retak serius dalam relasi kepercayaan antara rakyat dan institusi penegak hukum.
Ketika Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo mengakui di hadapan DPR publik lebih memilih damkar lantaran responsnya cepat, pernyataan itu bukan sekadar klarifikasi administratif.
Ia diagnosis terbuka atas krisis legitimasi operasional. Standar respons di bawah 10 menit yang direkomendasikan PBB belum tercapai, sementara Damkar tampil sebagai simbol kehadiran negara yang sigap, tangkas, tidak bertele-tele.
Di tengah kelelahan sosial akibat birokrasi berlapis, publik memilih siapa yang hadir, bukan siapa yang memiliki kewenangan formal.
Hukum sosial bekerja secara lugas: kepercayaan lahir bukan dari seragam atau senjata, melainkan dari pengalaman konkret.
Tom Tyler (2006) menegaskan publik mematuhi institusi bukan karena rasa takut, melainkan karena merasa diperlakukan adil. Polisi yang lamban, responsif setengah hati, atau terasa jauh memicu jarak emosional. Damkar mengisi ruang kosong itu bukan lewat kewenangan hukum, melainkan lewat kehadiran nyata.
Fenomena ini menyingkap paradoks mendasar. Polisi memikul mandat penegakan hukum, namun damkar memenangi simpati publik. Kekuasaan legal tidak otomatis melahirkan legitimasi moral.
Max Weber (1922) mengingatkan otoritas rasional-legal sah sejauh dijalankan secara konsisten dan efektif. Saat efektivitas runtuh, otoritas menjelma formalitas kosong.
Ironisnya, survei Litbang Kompas masih mencatat angka kepercayaan publik terhadap Polri di atas 70 persen. Angka itu bukan indikator kemenangan, melainkan sinyal ambigu: publik menyimpan harapan sekaligus kekecewaan laten. Kepercayaan bersifat rapuh, seperti jembatan yang berdiri di atas fondasi mulai lapuk.
Studi Azis Saputra, dkk (2024) menunjukkan kualitas pelayanan menjadi faktor dominan pembentuk persepsi publik. Kepercayaan bukan konsep abstrak, tetapi hasil akumulasi pengalaman mikro: cepat atau lambat, ramah atau dingin, hadir atau absen. Damkar unggul bukan karena strategi komunikasi, melainkan karena performa nyata.
Problem utama terletak pada watak institusional. Polisi masih terjebak paradigma lama: masyarakat diperlakukan sebagai objek yang dikendalikan, bukan subjek yang dilayani.
Satjipto Rahardjo (2009) mengingatkan hukum ideal bertugas memanusiakan manusia. Ketika prosedur lebih diagungkan ketimbang rasa keadilan, relasi publik runtuh pelan namun pasti. Transparansi juga menjadi titik lemah akut.
Penelitian dalam Jurnal CAUSA (2024) menyoroti minimnya keterbukaan proses penyidikan memicu persepsi gelap, tertutup, dan jauh dari akuntabilitas. Publik kehilangan orientasi karena tidak tahu nasib laporan. Saat laporan terasa menguap, kepercayaan ikut terkubur.
Damkar menjadi pilihan bukan sekadar soal kecepatan tanggap. Fenomena ini refleksi kegagalan negara menghadirkan rasa aman berbasis empati. Damkar hadir tanpa menggurui, tanpa intimidasi simbolik, tanpa kesan menghakimi. Sebaliknya, banyak warga merasa berhadapan dengan suasana inquisitorial saat melapor ke polisi.
Michel Foucault (1977) menyoroti bagaimana institusi kekuasaan menciptakan jarak melalui bahasa, struktur, dan gestur dominan. Polisi, sering tanpa sadar, mereproduksi jarak itu. Damkar meniadakannya.
Lebih mengkhawatirkan, kepercayaan yang beralih ke damkar bukan sekadar soal preferensi, tetapi sinyal delegitimasi fungsi mendasar kepolisian. Saat persoalan sosial dialihkan ke petugas pemadam, terjadi pergeseran definisi otoritas. Negara kehilangan monopoli moral atas perangkat keamanan.
Meski demikian, ruang koreksi belum sepenuhnya tertutup. Kepercayaan yang tersisa masih menyimpan potensi rekonstruksi.
Jurnal BADATI (2024) menekankan responsivitas, kapasitas petugas, dan etika pelayanan sebagai kunci pemulihan legitimasi. Bukan sekadar teknis, tetapi menyentuh dimensi empati dan kepekaan sosial.
Reformasi kepolisian tidak cukup bertumpu pada slogan. Ia harus terasa sejak detik pertama saat warga menghubungi nomor darurat. Intonasi suara, sikap menyambut, kecepatan hadir — seluruhnya menjadi bahasa baru negara. Negara berbicara melalui tindakan, bukan narasi promosi.
Era digital membentuk ekspektasi baru. Publik terbiasa dengan layanan real-time, pelacakan presisi, dan kepastian waktu. Saat laporan ke polisi tidak memiliki sistem pelacakan transparan, jurang ketertinggalan terbuka lebar. Warga ingin diyakinkan laporannya hidup, tidak sekadar berakhir di tumpukan arsip.
Fenomena ini menggugat paradigma lama: polisi sebagai simbol kekuasaan harus berubah menjadi polisi sebagai simbol kehadiran. Bukan sosok yang ditakuti, melainkan figur yang dipercaya. Bukan menjaga jarak, melainkan menghadirkan kedekatan.
Jika transformasi gagal, fenomena damkar berubah dari anomali menjadi norma. Polisi tetap eksis secara struktural, namun kehilangan wibawa simbolik. Legitimasi berpindah kepada institusi mana pun yang sanggup hadir lebih cepat dan lebih manusiawi.
Dalam kerangka filsafat politik, Jean-Jacques Rousseau (1762) menegaskan kontrak sosial runtuh saat negara gagal melindungi rakyat. Ketika rasa aman dialihkan ke institusi non-penegak hukum, kontrak itu mengalami erosi diam-diam. Damkar bukan pemenang sejati. Mereka sekadar menutup lubang yang ditinggalkan kepolisian. Pemenang sejati hanya lahir dari negara yang mampu memulihkan kepercayaan melalui keberanian berbenah dan kerja konkret.
Pertanyaan utama bukan lagi mengapa warga melapor ke Damkar, tetapi apakah polisi siap belajar dari Damkar? Siap menanggalkan superioritas simbolik, menggantinya dengan kecepatan pelayanan.
Siap meninggalkan mentalitas penguasa, memasuki etos pelayan publik. Siap menerima realitas pahit: kepercayaan tidak diwariskan oleh institusi, melainkan direbut kembali setiap hari.
Jika tidak, sirene Damkar yang semakin sering terdengar bukan hanya penanda kebakaran, melainkan alarm keras atas kegagalan moral sebuah sistem. Negara yang gagal mendengar alarm itu tengah berjalan perlahan menuju senyap legitimasi.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU.