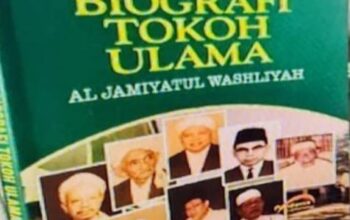Oleh Farid Wajdi
Pelaporan ke polisi, idealnya menjadi mekanisme perlindungan publik, kini sering berubah menjadi instrumen kekuasaan.
Fenomena “lapor polisi” di Indonesia memperlihatkan perubahan peran dari pelindung menjadi alat intimidasi.
Publik semakin aktif melaporkan dugaan tindak pidana atau pelanggaran yang mereka alami, tetapi pejabat publik juga menggunakan laporan sebagai senjata untuk menekan jurnalis, aktivis, dan individu yang mengkritik kebijakan atau tindakan mereka.
Saluran hukum yang semestinya menjamin keamanan publik berubah menjadi alat sosial-politik yang menakutkan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pejabat publik yang melaporkan kritik memunculkan self-censorship. Kekhawatiran publik untuk menyuarakan pendapat meningkat karena laporan pidana dapat menjadi ancaman serius.
Mekanisme yang seharusnya melindungi hak publik justru menimbulkan ketakutan dan menekan kebebasan ekspresi. Reformasi kepolisian perlu menembus aspek etika, keadaban hukum, dan legitimasi moral institusi, bukan hanya fokus pada perbaikan struktur dan prosedur.
Cermin Kekuasaan dan Krisis Keadilan
Peningkatan jumlah laporan polisi menjadi indikasi penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Banyak kasus yang bermula dari kritik di media sosial berakhir di ruang penyidikan.
Barda Nawawi Arief (2023) menyebut fenomena ini sebagai over-criminalization. Hukum kehilangan fungsi edukatif dan korektif, bergeser menjadi mekanisme pembalasan.
Kasus pelaporan terhadap jurnalis Tempo pada 2021 dan aktivis Greenpeace yang menyoroti kebijakan energi menunjukkan praktik kekuasaan yang menutupi diri dari kritik.
Pejabat publik menggunakan delik pidana untuk menekan publik dan media yang menyoroti penyalahgunaan kekuasaan.
Refly Harun (2023) menekankan kritik publik tidak boleh dibalas laporan pidana, karena hukum akan kehilangan peran sebagai instrumen keadilan.
Efek jangka panjang dari pola ini tampak pada ruang publik yang membeku.
Suko Widodo, Universitas Airlangga, menjelaskan fenomena chilling effect yang muncul ketika ancaman laporan pidana membatasi kebebasan berbicara (Widodo, 2022).
Jurnalis memilih diam, aktivis menahan kritik, dan publik membatasi ekspresi di media sosial. Ketika diam menjadi strategi rasional, demokrasi kehilangan ritme vitalnya.
Ketimpangan penanganan laporan juga terlihat jelas. Publik biasa menghadapi birokrasi panjang, sedangkan figur berpengaruh dapat memproses laporan secara cepat.
Hukumonline (2017) mencatat adanya risiko penyalahgunaan selektivitas ini. Laporan yang menguntungkan elite diproses kilat, sementara kasus publik biasa dapat tertunda tanpa alasan jelas.
Adrianus Meliala (2024) menegaskan reformasi kepolisian tidak akan berhasil tanpa perubahan mentalitas penyidik. Paradigma kekuasaan harus diganti paradigma pelayanan.
Perubahan prosedur dan struktur tidak cukup jika etika profesi tidak diperbarui. Aparat penyidik perlu menempatkan tugas sebagai pelayanan publik, bukan mempertahankan status quo politik.
Kasus jurnalis Tempo, Nurhadi, menjadi ilustrasi nyata kerentanan kebebasan pers. Pada Maret 2021, Nurhadi dilaporkan setelah mengalami penganiayaan saat meliput dugaan korupsi pajak di Jawa Timur.
Proses hukum berlangsung lambat, dan meskipun ada penerapan delik pers berdasarkan UU Pers, pelaku hanya divonis ringan.
AJI meminta perlindungan kepada LPSK, menandakan risiko yang dihadapi jurnalis saat melaporkan pelanggaran. Komnas HAM menekankan perlunya penanganan tegas agar kebebasan pers tidak terus terancam.
UU ITE dan Pasal Karet
UU ITE menjadi instrumen yang sering dipakai untuk menuntut pengkritik. Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik digunakan pejabat atau lembaga untuk menekan kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2025 membatasi ketentuan penghinaan UU ITE hanya berlaku untuk individu perseorangan, bukan pejabat publik atau lembaga negara.
Keputusan ini membuka ruang bagi kebebasan berekspresi dan mencegah kriminalisasi kritik yang tidak berdasar.
Meskipun putusan MK memberikan harapan, revisi KUHP dan UU ITE tetap diperlukan agar pasal karet dihapus. Tanpa langkah legislatif dan komitmen aparat penegak hukum, putusan MK berisiko hanya menjadi dokumen formal tanpa perubahan nyata di lapangan.
Reformasi pelaporan polisi perlu menyasar perubahan paradigma, bukan sekadar prosedur. Depenalisasi kasus yang lebih tepat diselesaikan melalui mediasi, jalur administratif, atau restorative justice menjadi strategi utama. Tidak setiap perbedaan pendapat harus berakhir di ranah pidana.
Pedoman internal Polri wajib menetapkan prioritas laporan berdasarkan urgensi dan dampak publik. Kritik atau ekspresi digital yang tidak mengandung kebencian diarahkan ke mediasi, bukan kriminalisasi.
Selektivitas semacam ini harus dibarengi transparansi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Perlindungan bagi pelapor dan pengkritik harus dijamin. Sistem whistleblower protection perlu dikembangkan agar publik yang melaporkan pelanggaran tidak menjadi korban balik hukum.
Transparansi menjadi syarat utama. Setiap laporan pidana harus memiliki nomor registrasi yang bisa dipantau publik, dan hasil penanganannya dilaporkan secara berkala. Langkah ini dapat memulihkan kepercayaan publik yang terkikis.
Publik perlu meningkatkan literasi hukum dan digital agar memahami batas antara kritik, fitnah, dan ujaran kebencian. Aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan etika komunikasi publik agar tidak bereaksi represif terhadap kritik.
Jimly Asshiddiqie (2023) menekankan hukum harus menjamin kebebasan dan ketertiban secara bersamaan, bukan menjadi alat membungkam perbedaan.
Fenomena “Lapor Polisi” mencerminkan kedewasaan hukum suatu bangsa. Laporan yang digunakan untuk melindungi hak publik dapat menjadi mekanisme partisipatif dalam penegakan hukum.
Sebaliknya, laporan yang disalahgunakan menjadi senjata kekuasaan, merusak demokrasi.
Kasus jurnalis Tempo, pelaporan aktivis Greenpeace, dan kritik terhadap pejabat publik menegaskan ruang perbedaan di Indonesia masih sempit.
Hukum kehilangan makna ketika publik takut melapor karena risiko kriminalisasi, atau aparat menggunakan laporan sebagai alat menekan. Keberanian moral jauh lebih penting daripada kepatuhan prosedural semata.
Polri memiliki kesempatan memulihkan legitimasi publik melalui selektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan bagi pelapor yang beritikad baik.
Konsistensi langkah-langkah ini memungkinkan polisi kembali menjadi penjaga keadilan, bukan alat politik. Kanal pelaporan harus menjadi kanal keadilan, bukan kanal ketakutan. Demokrasi akan menemukan kembali nadinya ketika hukum berpihak pada publik, bukan kekuasaan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU