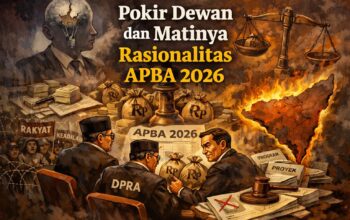Oleh: Farid Wajdi
Hukum tidak pernah bekerja sendiri. Ia bergerak melalui manusia, terutama hakim. Dari ruang sidang, melalui putusan, hukum menjelma keadilan atau justru kehilangan maknanya.
Karena itu, kualitas keadilan sebuah negara sering kali dapat dibaca dari cara hakim menjalankan perannya.
Relasi antara hukum dan hakim bukan hubungan mekanis. Hakim tidak sekadar membaca pasal lalu menjatuhkan vonis. Ia menilai fakta, menimbang bukti, dan menghubungkan norma dengan realitas sosial yang kompleks.
Setiap putusan membawa konsekuensi lebih luas dari sekadar menang atau kalah. Putusan membentuk persepsi publik tentang adil atau tidaknya hukum bekerja.
Tradisi hukum Islam sejak awal menempatkan hakim pada posisi sentral. Dalam kajian ushul fiqih, dikenal konsep hukmul hakim, yakni ketetapan hukum atas perkara konkret melalui proses penalaran dan penilaian.
Hukum dipahami sebagai relasi antara aturan (hukm), subjek yang dibebani (mahkum ‘alaih), dan perbuatan yang dinilai (mahkum fih). Wahbah al-Zuhaili (1986), menegaskan peran hakim sebagai penghubung norma dan kenyataan sosial agar tujuan hukum tercapai.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran hukum modern. Hakim bukan corong undang-undang, melainkan penafsir aktif yang memberi jiwa pada hukum.
Putusan hakim membawa dimensi moral dan sosial karena ia memengaruhi cara masyarakat memaknai keadilan dan negara hukum.
Masalah muncul ketika hukum dipraktikkan secara kaku. Kritik publik terhadap peradilan sering berangkat dari kesan formalisme berlebihan.
Pasal diterapkan secara tepat, tetapi keadilan substantif terasa menjauh. Di titik ini, hukum sah secara prosedural, namun miskin legitimasi moral.
Tom R. Tyler menjelaskan fenomena tersebut melalui Why People Obey the Law (1990). Menurutnya, kepatuhan publik lebih dipengaruhi pengalaman keadilan prosedural dibanding ancaman sanksi.
Orang menerima putusan yang merugikan ketika proses dirasakan adil dan transparan. Sebaliknya, putusan yang menguntungkan pun dapat memicu penolakan moral ketika prosesnya mencurigakan. Cara hukum dijalankan menjadi faktor penentu kepercayaan.
Keadilan prosedural sangat bergantung pada independensi hakim. Independensi memberi ruang bagi hakim untuk memutus tanpa tekanan politik, ekonomi, atau kekuasaan lain. Prinsip ini menjadi fondasi negara hukum modern.
Montesquieu, dalam De l’Esprit des Lois (1748), menegaskan pemisahan kekuasaan sebagai syarat kebebasan dan keadilan.
Namun independensi bukan kebebasan tanpa batas. Hakim tetap terikat pada etika dan akuntabilitas. Independensi tanpa integritas melahirkan kesewenang-wenangan.
Sebaliknya, pengawasan berlebihan tanpa menghormati independensi justru mereduksi martabat peradilan. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi kunci.
Hukum Sebagai Institusi Yang Hidup
Satjipto Rahardjo secara konsisten mengingatkan dimensi moral ini. Dalam Hukum Progresif (2009), ia menempatkan hukum sebagai institusi yang hidup melalui manusia.
Hakim dipandang perlu berani keluar dari formalisme demi mencapai keadilan substantif. Hukum hadir untuk melayani manusia, bukan mengekangnya.
Pemikiran tersebut menemukan relevansi dalam pergeseran paradigma pemidanaan modern. Hukum pidana tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan.
Pendekatan kontemporer menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Antony Duff, melalui Punishment, Communication, and Community (2001), memandang pemidanaan sebagai sarana komunikasi moral antara negara, pelaku, dan masyarakat.
Pendekatan ini memberi ruang bagi hakim untuk menilai konteks sosial, latar belakang pelaku, serta dampak perbuatan secara lebih utuh.
Paradigma baru ini menuntut kapasitas etik dan intelektual hakim yang tinggi. Hakim tidak cukup hanya menguasai hukum positif. Ia perlu memahami nilai kemanusiaan dan dinamika sosial.
Gustav Radbruch, melalui refleksinya pasca-Perang Dunia II (1946), merumuskan gagasan terkenal tentang konflik antara kepastian hukum dan keadilan.
Dalam situasi ekstrem, keadilan patut didahulukan. Rumus ini lahir dari pengalaman hukum yang sah secara formal, namun gagal secara moral.
Di Indonesia, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara idealitas tersebut dan praktik peradilan. Publik kerap menyaksikan perbedaan perlakuan antara perkara kecil dan perkara besar.
Ketimpangan ini belum tentu melanggar hukum positif, tetapi melukai rasa keadilan sosial. Lon L. Fuller (1964), menekankan konsistensi dan penerapan umum sebagai syarat moral hukum. Tanpa konsistensi, legitimasi hukum terkikis perlahan.
Keadilan juga berkaitan erat dengan partisipasi publik. Jeremy Waldron (1999), menegaskan pentingnya hukum sebagai hasil proses deliberatif.
Aturan yang lahir tanpa ruang dialog mudah terasa asing dan kehilangan daya ikat. Dalam konteks peradilan, keterbukaan informasi dan akses publik terhadap putusan menjadi jembatan penting antara hakim dan masyarakat.
Pendidikan hukum ikut menentukan kualitas peradilan. Pendidikan yang menekankan hafalan pasal berisiko melahirkan aparat yang cakap secara teknis, tetapi tumpul secara etik.
Barda Nawawi Arief, melalui karya-karyanya tentang kebijakan hukum pidana sejak 1994 hingga Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (2010), menekankan orientasi nilai dan keadilan sosial sebagai fondasi pendidikan hukum.
Relasi antara hukum, hakim, dan keadilan akhirnya membentuk segitiga yang saling menentukan. Hukum menyediakan kerangka normatif, hakim memberi makna melalui putusan, dan keadilan menjadi tujuan yang dikejar. Ketika satu unsur melemah, bangunan negara hukum ikut terguncang.
Keadilan tidak lahir dari teks semata. Ia tumbuh dari integritas, keberanian moral, dan kepekaan sosial para penegaknya. Hakim memegang posisi kunci dalam menjaga keseimbangan itu.
Di tangan hakim yang berintegritas, hukum menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan. Tanpa integritas dan nurani, hukum berisiko berubah menjadi mekanisme kekuasaan yang kehilangan jiwa keadilan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU