Oleh Shohibul Anshor Siregar
Di satu sisi, ini bisa menjadi momentum untuk merombak sistem kepartaian yang mandek—di mana partai besar lebih berfungsi sebagai mesin pencari rente daripada wadah aspirasi. Di sisi lain, risiko oligarkisasi dan sentralisasi kekuasaan tetap mengancam
Scroll Untuk Lanjut MembacaIKLAN
Pasca-Pemilu 2024, Indonesia memasuki fase politik yang sarat dengan spekulasi dan ketegangan. Di tengah euforia kemenangan koalisi pemerintah, muncul wacana mengejutkan: Joko Widodo (Jokowi), presiden dua periode dengan tingkat kepuasan publik tertinggi dalam sejarah demokrasi Indonesia, dikabarkan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Partai yang didirikan pada 2014 ini, meski gagal menembus ambang batas parlemen dalam dua pemilu terakhir, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Langkah ini bukan sekadar pergantian ketua partai, melainkan gerakan politik yang berpotensi mengubah peta kekuasaan nasional. Dalam narasi yang lebih luas, ini adalah ujian bagi demokrasi Indonesia: apakah sistem politik mampu bertahan dari tarikan oligarki yang menguat, atau justru menemukan jalan baru melalui transformasi partai yang inklusif?
Jokowi bukanlah politisi biasa. Karirnya dimulai dari Solo, kota kecil di Jawa Tengah, yang di sana ia membangun reputasi sebagai “manajer kota” yang efisien. Gaya blusukan menjadi ciri khas yang membedakannya dari politisi generasi sebelumnya. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, janjinya untuk membersihkan sistem birokrasi yang korup dan membangun infrastruktur dasar menarik simpati warga ibukota. Dua tahun kemudian, ia terpilih sebagai presiden, mengalahkan rivalnya yang berasal dari keluarga politik mapan. Sepanjang dekade kepemimpinannya, Jokowi berhasil membangun citra sebagai “presiden rakyat”, meski kebijakannya kerap menuai kontroversi, dari pembangunan bendungan dan jalan tol masif hingga relokasi ibu kota ke Kalimantan.
Namun, di balik klaim kesuksesan itu, Jokowi juga membangun jaringan kekuasaan yang rumit. Selama dua periode, ia menempatkan loyalis di pos-pos kritis: dari kementerian strategis seperti PUPR dan BUMN hingga institusi militer. Data menunjukkan, 60% kepala daerah yang terpilih sejak 2015 memiliki hubungan politik langsung atau tidak langsung dengan Jokowi. Di sektor BUMN, 85% direktur utama perusahaan pelat merah diangkat melalui proses yang diwarnai pertimbangan politik. Jaringan ini tidak hanya menjadi alat untuk memperlancar program pembangunan, tetapi juga benteng pertahanan bagi kelangsungan pengaruhnya pascakepresidenan.
Namun, kekuatan ini rapuh. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2024 mengungkap 12 kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan lingkaran dalam Jokowi, mulai dari alokasi proyek infrastruktur hingga intervensi proses hukum. Dalam situasi ini, PSI muncul sebagai kendaraan potensial untuk melindungi warisan politiknya—dan mungkin, diri sendiri.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sendiri adalah entitas yang menarik untuk dikaji. Didirikan sebagai partai kaum muda dengan jargon antikorupsi dan kesetaraan gender, PSI berhasil merebut perhatian publik melalui kampanye digital yang kritis dan segar. Dengan 2,3 juta pengikut di Instagram (angka tertinggi di antara partai politik) PSI menjadi contoh bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk politik. Namun, di lapangan, partai ini gagal menjangkau pemilih di pedesaan dan wilayah tradisional. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan, PSI hanya meraih 5% suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, basis pemilih utama partai-partai besar seperti PDIP dan PKB. Kegagalan ini mencerminkan dilema klasik partai baru: bagaimana membangun akar di tengah dominasi partai mapan yang telah menguasai mesin politik di tingkat grassroot.
Di sinilah Jokowi bisa menjadi game changer. Popularitasnya yang tetap tinggi (73% publik menilainya sebagai pemimpin yang “dekat dengan rakyat” menurut survei Indikator Politik 2024) memberikan PSI akses ke basis pemilih yang selama ini tidak terjamah. Jika Jokowi resmi memimpin, PSI tidak hanya akan mendapatkan simbol politik yang kuat, tetapi juga jaringan kekuasaan yang telah dibangun selama sepuluh tahun. Contoh dari Filipina bisa menjadi analogi: Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, berhasil membawa partai Lakas-CMD dari perolehan 2% suara pada 2019 menjadi 28% pada 2022 melalui kombinasi personal branding dan mobilisasi sumber daya. Dengan skenario serupa, PSI berpotensi meraih 15–20% suara dalam pemilu berikutnya, menjadikannya kekuatan penyeimbang di parlemen.
Namun, mobilisasi elektoral semacam ini membutuhkan logistik politik yang masif. Di Indonesia, biaya politik tidak murah. Jokowi adalah orang kaya besar. Ia tidak akan sudi menjadi Ketua PSI jika partai ini hanya sekadar partai papan bawah. Maka jka di bawah kepemimpinannya PSI mengalokasikan Rp1 triliun per daerah pemilihan (total Rp82 triliun untuk 82 dapil) uang ini bisa digunakan untuk membangun jaringan patronase melalui proyek infrastruktur kecil, bantuan sosial, atau insentif bagi elit lokal untuk memenangi pemilu dengan target menjadi fraksi terbesar di setiap kota, kabupaten dan provinsi. Strategi ini efektif secara elektoral, meski berisiko mengubur idealisme awal PSI sebagai partai antikorupsi. Akan terjadi paradoks: ingin menjadi kekuatan pembaru, tetapi terpaksa berkompromi dengan sistem yang dikritiknya.
Meski Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum, kepemimpinan Jokowi bisa memicu ketegangan antara kader muda idealis yang bergabung karena janji reformasi dengan pendatang baru yang bermotif pragmatis. Lebih dari itu, hubungan dengan PDIP, partai yang mengusung Jokowi dalam dua pilpres. akan memasuki fase kompetitif. Berapa persen kader PDIP yang secara diam-diam mendukung Jokowi? Eksodus ke PSI bukanlah hal mustahil.
Implikasi demokratis dari skenario ini sangat kompleks. Di satu sisi, kehadiran PSI di bawah Jokowi bisa menjadi penyeimbang bagi oligarki lama yang menguasai partai-partai mapan. Di sisi lain, sentralisasi kekuasaan di sekitar figur Jokowi berisiko menciptakan oligarki baru yang lebih tersistematis. Indeks Demokrasi Indonesia menurun dengan indikator utama melemahnya kebebasan sipil dan menguatnya intervensi negara dalam proses demokrasi. Jika Jokowi menggunakan PSI untuk mengontrol parlemen dan menetralisir oposisi, seperti yang dilakukan Recep Tayyip Erdogan di Turki melalui Partai AKP, maka demokrasi Indonesia bisa terjebak dalam spiral otoritarianisme elektoral.
Erdogan, sebagai contoh, mengubah AKP dari partai Islamis moderat menjadi alat sentralisasi kekuasaan. Melalui amendemen konstitusi, kontrol atas yudikatif, dan kooptasi media, ia menciptakan sistem “hyper-presidentialism” yang memusatkan hampir semua kekuasaan di tangannya. Di Indonesia, skenario serupa mungkin terjadi jika PSI menjadi kendaraan untuk meloloskan kebijakan kontroversial, seperti pembatasan kebebasan pers atau revisi UU KPK, dengan dalih stabilitas nasional.
Alternatif lain adalah transformasi PSI menjadi partai berbasis program ala New Labour di Inggris era Tony Blair. Blair mentransformasi Partai Labour dari partai buruh tradisional menjadi kekuatan sentris melalui modernisasi ekonomi dan pencitraan pragmatis. Dengan jargon “Third Way”, ia merebut dukungan kelas menengah perkotaan yang lelah dengan polarisasi politik lama. Jokowi bisa meniru model ini dengan mengubah PSI menjadi wadah bagi kaum muda urban yang peduli pada ekonomi digital, energi terbarukan, dan pemerintahan inklusif. Namun, risiko terbesarnya adalah kehilangan identitas: PSI bisa terjebak sebagai partai “catch-all” yang tak punya ciri khas, seperti yang terjadi pada Partai Demokrat di AS.
Habermas menekankan pentingnya partai politik sebagai ruang deliberasi rasional, tempat kebijakan dirumuskan melalui dialog inklusif, bukan transaksi elit. PSI, dengan 65% kader berusia di bawah 40 tahun, berpotensi mengadopsi model ini. Misalnya, dengan membuka platform digital untuk diskusi kebijakan terbuka atau menggelar pemilihan kader berbasis merit. Namun, realitasnya rumit.
Kontradiksi lain terlihat dari pendanaan PSI. Meski mengusung citra “partai bersih”, diduga dana kampanyenya pada 2024 berasal dari beberapa donatur utama yang sebagian besar adalah pengusaha proyek infrastruktur. Di sini, PSI dapat mirip dengan Partai Kongres India era pasca-kemerdekaan: lahir sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi akhirnya terjebak dalam jerat dinasti dan korupsi.
Di tingkat global, fenomena post-populisme yang dijelaskan Benjamin Moffitt memberikan lensa untuk memahami langkah Jokowi. Moffitt berargumen bahwa pemimpin populis sering beralih dari retorika revolusioner (“melawan elite”) ke narasi stabilitas setelah berkuasa. Apakah PSI akan menjadi alat untuk mempertahankan status quo (dengan segala kebijakan kontroversialnya) atau justru menjadi katalis perubahan sistemik?
Jawabannya terletak pada respons publik. Tentu saja polarisasi akan terjadi atas rencana kepemimpinan Jokowi di PSI. Dukungan tertinggi mungkin datang dari pemilih muda perkotaan yang melihat Jokowi sebagai simbol pembangunan, sedangkan penolakan dominan di kalangan aktivis dan akademisi yang khawatir pada demokratisasi. Jika polarisasi ini tidak dikelola melalui dialog substansial, bukan sekadar kampanye pencitraan, maka stabilitas politik Indonesia ke depan akan rentan goncangan.
Dalam konteks ini, pembelajaran dari Partai Podemos Spanyol layak dijadikan cermin. Podemos, partai kiri progresif yang lahir dari gerakan akar rumput, awalnya menjanjikan demokratisasi internal dan transparansi. Namun, ambisi elektoral yang terlalu cepat dan konflik internal antara kubu idealis-pragmatis membuat partai ini kehilangan momentum. PSI, jika tidak hati-hati, bisa mengulangi kesalahan yang sama: terlalu fokus pada pencapaian elektoral jangka pendek, lalu mengabaikan pembangunan institusi partai yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, transformasi PSI di bawah Jokowi adalah cermin dari pertaruhan besar demokrasi Indonesia. Di satu sisi, ini bisa menjadi momentum untuk merombak sistem kepartaian yang mandek—di mana partai besar lebih berfungsi sebagai mesin pencari rente daripada wadah aspirasi. Di sisi lain, risiko oligarkisasi dan sentralisasi kekuasaan tetap mengancam. Pilihan ada di tangan Jokowi: apakah ia akan menggunakan pengaruhnya untuk membangun partai yang deliberatif dan berintegritas, atau sekadar menambahkan episode baru dalam sejarah panjang politik transaksional Indonesia?
Demokrasi bukanlah garis lurus yang bergerak maju, melainkan proses dialektika yang penuh tikungan. Langkah Jokowi ke PSI adalah salah satu tikungan itu—sebuah ujian apakah Indonesia mampu belajar dari kesalahan masa lalu, atau justru mengulanginya dalam kemasan modern.
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).







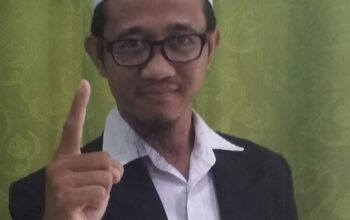





Jangan ulangi kesalahan selama 10 tahun ini yg penuh dengan kepalsuan dan kebohongan.