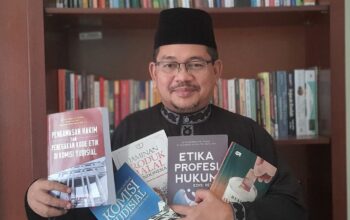Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., SpN., M.Kn
Pancasila bukan sekadar simbol seremonial atau dokumen normatif, melainkan sebuah sistem nilai yang tumbuh dan berakar kuat dalam realitas budaya, sejarah, dan spiritual bangsa Indonesia.
Pengantar
Di tengah krisis moral, polarisasi politik, dan derasnya arus globalisasi, Pancasila tetap menjadi jangkar filosofis dan arah etik bangsa Indonesia. Namun tantangan utama kini bukan pada pengakuan formal terhadap Pancasila, melainkan pada internalisasi dan praksis nilai-nilainya secara otentik.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga filosofis—yakni melalui kerangka ontologis (hakikat bangsa), epistemologis (cara memahami nilai), dan aksiologis (nilai guna dan praksis sosial)—dalam bingkai Ius Integrum Nusantara.
Pancasila bukan doktrin impor, melainkan realitas historis yang tumbuh dari konsensus dan kearifan lokal bangsa. Ia mencerminkan pluralitas, spiritualitas, dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi ontologis Indonesia. Namun dalam praktik, pendidikan Pancasila masih bersifat seremonial dan tekstual, bukan reflektif dan dialogis. Hal ini memicu jauhnya nilai dari realitas sosial, terutama di kalangan muda.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar mantra, tetapi harus dihidupi dalam tindakan, kebijakan, dan kepemimpinan. Maka pendekatan ius integrum menjadi solusi integratif, menjadikan Pancasila sebagai sistem hukum, moral, dan budaya yang menyatu dengan kehidupan bangsa. Dalam kerangka aksiologis, Pancasila harus menjelma dalam keadilan sosial, etika publik, dan sistem pendidikan yang membebaskan. Revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara struktural dan kultural, melalui partisipasi aktif media, lembaga pendidikan, dan institusi negara. Generasi muda tidak cukup dijadikan pewaris, melainkan agen nilai baru. Seperti dikatakan Soedjatmoko, ideologi hanya hidup jika mewujud dalam tindakan moral kolektif.
Sebagai ius integrum Nusantara, Pancasila adalah sistem nilai yang mempersatukan jati diri, cara berpikir, dan tindakan bangsa. Di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045, Pancasila harus menjadi kekuatan pemersatu dan pemandu arah, bukan hanya simbol seremonial. Ia adalah jalan hidup bangsa—yang harus terus dijaga, dibela, dan dihidupi demi Indonesia yang adil, bermartabat, dan berdaulat. Sejak kemerdekaan, Pancasila telah menjadi fondasi utama yang menyatukan keberagaman budaya, agama, dan etnis bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis.
Namun, di era modern ini, bangsa kita menghadapi krisis kebangsaan yang ditandai oleh erosi nilai-nilai dasar Pancasila, polarisasi sosial yang memecah, serta pragmatisme politik yang mengikis semangat persatuan. Krisis ini bukan sekadar persoalan formal atau tekstual, melainkan menuntut refleksi filosofis mendalam yang menghidupkan kembali Pancasila melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan demikian, Pancasila dapat berfungsi sebagai Ius Integrum Nusantara — hukum integral yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh.
Pancasila bukan sekadar simbol seremonial atau dokumen normatif, melainkan sebuah sistem nilai yang tumbuh dan berakar kuat dalam realitas budaya, sejarah, dan spiritual bangsa Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap hakikat (ontologi), cara mengetahui (epistemologi), dan nilai guna (aksiologi) Pancasila, kita mampu mengembalikan makna asli Pancasila sebagai sumber moral dan etika yang mendasari kehidupan sosial-politik serta menghadapi berbagai tantangan zaman dengan keberanian dan kebijaksanaan. Karya ini bertujuan menggerakkan revitalisasi nilai-nilai Pancasila agar benar-benar hidup dan berdaya guna dalam praktik keseharian masyarakat serta kebijakan negara.
Menghadapi dinamika sosial-politik yang semakin kompleks dan tantangan global yang terus berubah, menjaga relevansi Pancasila sebagai Ius Integrum Nusantara menjadi keharusan yang mendesak. Krisis kebangsaan yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya berupa ancaman ideologis dari luar, tetapi lebih pada krisis internalisasi nilai yang memerlukan pendekatan filosofis holistik dan terintegrasi. Penguatan kesadaran ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila menjadi fondasi utama agar bangsa ini mampu mewujudkan keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan secara nyata, bukan sekadar retorika politik.
Selain itu, Pancasila harus dihidupkan kembali sebagai jiwa dan roh bangsa, bukan hanya simbol upacara atau jargon politik yang mudah dilupakan. Konsep Ius Integrum Nusantara menegaskan perlunya sebuah kerangka hukum dan moral integral yang menyatukan seluruh aspek kehidupan berbangsa dalam keselarasan nilai dan tindakan. Dengan fondasi ini, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, serta menjadi tonggak kebangkitan nasional yang autentik di era modern yang penuh tantangan. Tulisan ini diharapkan menjadi kontribusi intelektual dan praktis dalam diskursus akademik, kebijakan publik, dan pendidikan kewarganegaraan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Dengan semangat ini, Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga kuat dan sakti secara moral dan filosofis, siap menghadapi masa depan yang penuh harapan dan tantangan.
Pancasila di Tengah Krisis Kebangsaan
Setiap 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara di berbagai institusi. Namun, di balik seremonial itu, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kita benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi fondasi konstitusional selama lebih dari tujuh dekade. Namun, kenyataan menunjukkan paradoks antara nilai luhur yang diwariskan dan praktik sosial-politik yang kerap menyimpang. Pragmatisme politik menggeser semangat musyawarah, dan polarisasi identitas melemahkan nilai persatuan.
Kondisi ini menggambarkan krisis nilai kebangsaan yang tidak sekadar soal lemahnya implementasi atau edukasi, melainkan krisis filosofis: apakah Pancasila masih dipahami dan diyakini sebagai dasar hidup berbangsa? Pancasila harus dipahami sebagai sistem nilai yang utuh—berlapis ontologi (hakikat), epistemologi (cara mengetahui), dan aksiologi (nilai guna). Kerangka ini memungkinkan kita menempatkan Pancasila sebagai Ius Integrum Nusantara, yakni hukum integral yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa secara menyeluruh.
Secara ontologis, Pancasila merepresentasikan hakikat bangsa Indonesia. Ia bukan produk elit atau dokumen legalistik semata, melainkan realitas yang melekat dalam identitas kolektif: lahir dari sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Notonagoro dengan tajam menyatakan bahwa Pancasila adalah “sistem filsafat negara yang berdiri di atas landasan budaya dan sejarah bangsa sendiri”¹. Artinya, Pancasila tidak dicangkokkan dari luar, melainkan tumbuh dari tanah Indonesia sendiri, mencerminkan pluralitas, religiusitas, dan gotong-royong sebagai substansi kebangsaan.
Pendekatan epistemologis mengajak kita meninjau ulang cara memahami Pancasila. Bukan hanya sekadar teks atau hafalan di ruang kelas, tetapi hasil refleksi dari pengalaman historis, sosial, dan kultural bangsa. Pengetahuan tentang Pancasila tidak boleh berhenti pada level deklaratif, melainkan harus menjadi kesadaran reflektif dan kritis.
Sayangnya, di tengah derasnya arus informasi dan politik pragmatis, Pancasila sering direduksi menjadi jargon atau alat legitimasi kekuasaan. Survei Litbang Kompas tahun 2023 mengungkap hanya 27 persen generasi muda memahami makna mendalam tiap sila Pancasila. Sebagian besar hanya menghafalnya tanpa memahami konteks sosialnya—dari masalah korupsi, intoleransi, hingga ketimpangan sosial.
Hal ini menguatkan pernyataan Yudi Latif, yang menilai krisis Pancasila saat ini bukan soal eksistensial, melainkan soal internalisasi nilai. “Pancasila berhenti di lisan, belum turun ke tindakan,” tulisnya dalam Mata Air Keteladanan². Pancasila belum menjadi kesadaran kolektif, melainkan hanya kewajiban administratif.
Ancaman terhadap Pancasila hari ini memang tidak lagi berbentuk senjata atau ideologi asing, tetapi lebih subtil: ketidakpedulian terhadap ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan erosi etika publik. Dalam situasi ini, Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi momentum reflektif: apakah Pancasila masih sakti karena dijaga senjata, atau karena hidup dalam nurani dan tindakan rakyatnya?
Selain itu, Soedjatmoko pernah mengingatkan bahwa “sebuah ideologi hanya sakti sejauh ia bisa hidup dalam tindakan moral dan politik masyarakatnya, bukan semata dalam simbol dan dokumen”³. Ini adalah tantangan kita hari ini—menghidupkan kembali Pancasila sebagai ideologi yang menuntun, bukan sekadar dihormati.
Di sinilah urgensi pendekatan Ius Integrum Nusantara menemukan relevansinya. Konsep ini bukan hanya menegaskan Pancasila sebagai dasar normatif, tetapi sebagai kerangka filosofis, hukum, dan moral yang integral. Ius integrum Nusantara mengintegrasikan seluruh dimensi kehidupan—politik, hukum, pendidikan, sosial—dalam satu sistem nilai yang hidup dan membumi. Bukan hanya di ruang elite, tetapi juga dalam perilaku keseharian masyarakat. Menjadi bangsa yang ontologis berarti menjadikan Pancasila sebagai representasi diri yang otentik. Menjadi bangsa yang epistemologis berarti terus mengasah cara berpikir kritis terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dan menjadi bangsa yang aksiologis berarti menghadirkan Pancasila dalam kebijakan yang adil, etika publik yang luhur, dan relasi sosial yang menjunjung kemanusiaan.
Pancasila tidak cukup diajarkan sebagai dogma. Ia harus dihidupkan dalam praktik, dikawal oleh pendidikan yang membebaskan, dan dibumikan oleh kebijakan yang berkeadilan. Dengan pendekatan Ius Integrum Nusantara, Pancasila bukan hanya fondasi filosofis, tetapi juga menjadi instrumen aplikatif dalam menjawab tantangan krisis kebangsaan—sekaligus jembatan menuju masa depan Indonesia yang adil, inklusif, dan beradab.
Pancasila bukan sekadar dokumen dasar negara, tetapi dasar filosofis kebangsaan yang lahir dari realitas kultural dan historis Nusantara. Secara ontologis, ia mencerminkan identitas Indonesia yang majemuk dan spiritual; secara epistemologis, ia menuntut pemahaman reflektif yang melampaui hafalan tekstual; dan secara aksiologis, ia mesti menjelma dalam tindakan politik, hukum, dan sosial yang berkeadilan. Krisis kebangsaan saat ini adalah krisis nilai—saat Pancasila direduksi menjadi simbol formal tanpa daya transformasi praksis. Pendekatan Ius Integrum Nusantara menghadirkan kerangka utuh yang menyatukan nilai, norma, dan tindakan berbasis kearifan lokal serta prinsip universal. Pancasila, dalam kerangka ini, bukan sekadar sumber hukum, tapi pedoman hidup kolektif yang harus menyatu dalam nadi publik, bukan sekadar milik negara.
Menghidupkan kembali Pancasila berarti menanamkan kembali jati diri bangsa dalam sistem pendidikan, narasi media, praktik demokrasi, dan kepemimpinan publik. Kesaktiannya tidak terletak pada seremoni tahunan, tetapi pada kemampuannya menjadi ruh etika, hukum, dan kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila harus terus dihidupi—bukan diwariskan sebagai slogan, melainkan diteruskan sebagai tindakan moral generasi ke generasi.
Epistemologi Pancasila – Menyelamatkan Cara Bangsa Memahami Dirinya
Setelah menggali hakikat Pancasila secara ontologis, pertanyaan krusial berikutnya adalah: bagaimana bangsa Indonesia memahami dan menafsirkan Pancasila? Inilah wilayah epistemologi—cara membangun pengetahuan yang sahih, kontekstual, dan membumi atas dasar negara kita. Epistemologi Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan tekstual. Ia menuntut penelaahan atas bagaimana pengetahuan tentang Pancasila dibentuk—secara historis, kultural, dan politis. Sejarah menunjukkan bahwa cara kita memahami Pancasila tidak selalu netral. Ia kerap dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, orientasi ideologis penguasa, hingga kebutuhan politik rezim tertentu.
Salah satu tonggak penting dalam sejarah epistemologi Pancasila adalah lahirnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di masa Orde Baru. Diluncurkan tahun 1978, P4 menjadi upaya negara untuk membumikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Lewat penataran massal—dari pejabat hingga pelajar—Pancasila diposisikan sebagai landasan moral dan ideologi negara yang tak boleh dipertanyakan.
Tujuan idealnya: membentuk warga negara yang sadar nilai dan berdisiplin nasional. Namun, dalam praktiknya, P4 justru mengkristalkan epistemologi yang dogmatis dan searah. Pemahaman terhadap Pancasila tidak lahir dari proses dialog dan refleksi kritis, tetapi dari penanaman nilai secara vertikal dan top-down. Tafsir tunggal negara menjadi sumber utama kebenaran, dan kritik terhadapnya dianggap sebagai bentuk penyimpangan ideologis. Hal ini selaras dengan kritik Paulo Freire terhadap pendidikan yang represif, di mana pengetahuan ditanamkan tanpa partisipasi aktif peserta. Model semacam ini menciptakan warga yang “paham” Pancasila secara formal, tapi tak mampu mengaktualisasikannya secara kontekstual (Freire, 1970). Akibatnya, Pancasila menjadi simbol administratif yang sakral tapi jauh dari kehidupan nyata rakyat.
Melalui pendekatan Ius Integrum Nusantara, epistemologi semacam itu tidak cukup. Ius integrum menekankan pentingnya kesatuan antara nilai, hukum, dan praksis hidup masyarakat. Maka, epistemologi Pancasila harus dibangun secara partisipatif dan kontekstual. Ia harus tumbuh dari pengalaman rakyat—dari pasar, sawah, dan ruang kelas—bukan hanya dari podium-podium negara.
Pendidikan menjadi arena utama untuk merekonstruksi cara kita memahami Pancasila. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Franz Magnis-Suseno, Pancasila kerap diajarkan sebagai dogma yang beku, bukan sebagai sistem nilai yang hidup (Magnis-Suseno, 1991). Di sinilah reformulasi epistemologis perlu dilakukan: pembelajaran Pancasila harus ditautkan dengan isu-isu nyata seperti kemiskinan, ketimpangan, perundungan, atau keberagaman digital. Siswa tidak hanya belajar “apa isi sila keempat”, tetapi juga bagaimana musyawarah bisa menjadi metode penyelesaian konflik di sekolah atau komunitas.
Tak kalah penting adalah pelibatan masyarakat sipil dan komunitas budaya dalam memperkaya diskursus Pancasila. Kita membutuhkan demokratisasi tafsir, bukan monopoli makna. Dengan itu, Pancasila tidak lagi sekadar milik negara, melainkan ruang nilai bersama—common ground—yang tumbuh, berkembang, dan selalu bisa diuji ulang oleh masyarakat sendiri.
Membangun epistemologi Pancasila yang emansipatoris adalah jalan untuk menghindari kekakuan model P4 yang pernah dominan. Bukan berarti menafikan jasa P4, tetapi menghindari jebakan formalisme dan membuka ruang baru bagi keberlanjutan nilai Pancasila dalam konteks abad ke-21. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dihafal, melainkan etika kolektif yang dipahami, diperdebatkan, dan dihidupi dalam tindakan sosial. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, epistemologi Pancasila yang kontekstual, reflektif, dan terbuka adalah fondasi penting dalam membentuk bangsa yang adil, demokratis, dan berkeadaban.
Aksiologi Pancasila – Membumikan Nilai Lewat Sejarah dan Praksis
Epistemologi Pancasila sudah menguak bagaimana bangsa kita mengetahui dan memahami nilai-nilainya; sekarang tiba giliran aksiologi—nilai guna Pancasila dalam tindakan nyata, terutama lewat pembumian historis seperti P4.
Pada masa Orde Baru, P4 dijadikan instrumen aksiologi yang sangat nyata: Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai pedoman perilaku warga negara, aparatur negara, dan lembaga kenegaraan. P4 memuat 36 butir pengamalan yang merinci tindakan konkret dari setiap sila Pancasila agar warga bukan hanya mengerti secara teoritis, tetapi menghidupi Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah membentuk Badan Pembina Penataran P4 (BP7) untuk menyebarluaskan pengamalan tersebut hingga ke sekolah, instansi pemerintahan, hingga masyarakat umum⁹.
Selain itu, dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, P4 menjadi contoh aplikatif bagaimana nilai-nilai ontologis dan epistemologis dapat dirangkum ke dalam norma publik yang mengatur perilaku dan kebijakan. Namun, terdapat sisi paradoks: meskipun P4 dirancang untuk membumikan Pancasila, implementasinya cenderung bersifat top-down, seragam, dan terkadang represif. Kritik muncul karena P4 menekan keragaman tafsir dan ruang kebebasan berpikir—nilai-nilai lokal atau kultural yang berbeda sering dianggap menyimpang jika tidak sejalan dengan pedoman pusat⁹.
Secara praktis, P4 memengaruhi kehidupan publik: dalam kurikulum PMP dan PPKn, pelajar diperkenalkan pada nilai-nilai moral Pancasila yang dijabarkan dari butir-butir pengamalan, yang kemudian diharapkan menjadi etika warga sehari-hari. Namun, dampak sosialnya menjadi terbatas ketika pengamalan itu lebih bersifat ritualistik, formalitas, atau kewajiban administratif—tanpa refleksi kritis atau adaptasi kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Nilai guna Pancasila lewat P4 di masa Orde Baru menawarkan pelajaran penting: bahwa aksiologi Pancasila efektif bila melibatkan dua elemen kunci: kejelasan norma praktis (butir-butir pengamalan) dan partisipasi aktif masyarakat dalam penafsiran serta praktiknya. Bila hanya norma jelas tanpa dialog, Pancasila dapat terdistorsi menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan fondasi moral rakyat.
Selanjutnya, dalam situasi kontemporer, membumikan Pancasila berarti merujuk pada model P4 sebagai benchmark—tetapi diperbaharui lewat pendekatan Ius Integrum Nusantara yang menghargai pluralitas pengalaman dan membuka ruang bagi adaptasi nilai dalam konteks lokal. Misalnya, lembaga pendidikan harus mengintegrasikan butir-butir pengamalan dengan isu-isu lokal—keadilan lingkungan, hak-hak komunitas adat, ekonomi mikro berbasis musyawarah—sehingga Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi hidup dan relevan.
Kebijakan publik pun harus diuji berdasarkan aksiologi Pancasila: apakah tata ruang, distribusi anggaran, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan politik telah mencerminkan keadilan sosial, empati kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab moral? Jika tidak, P4 masa lalu menjadi hanya kenangan, bukan teladan aplikatif.
Dari Aksiologi ke Aksi Nyata
Jika aksiologi Pancasila menekankan nilai guna dan praksis, maka langkah berikutnya adalah merancang strategi aplikatif yang kontekstual, partisipatif, dan transformatif. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai jembatan antara nilai filosofis Pancasila dan kehidupan sosial-politik bangsa hari ini. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, rekomendasi ini menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai sistem ide, tetapi sebagai sistem tindakan yang menyatu dengan karakter dan kebutuhan bangsa.
1. Desentralisasi Penafsiran Nilai Pancasila
Salah satu pelajaran dari era P4 adalah bahaya sentralisasi tafsir ideologi. Untuk menghindari Pancasila menjadi dogma, maka dibutuhkan ruang dialog yang luas di tingkat lokal. Pemerintah pusat harus mendorong pembentukan Forum Tafsir Pancasila Partisipatif di tingkat daerah—melibatkan tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan akademisi lokal—untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks wilayahnya.
Langkah ini akan memulihkan kesakralan nilai melalui pengalaman hidup masyarakat, sekaligus mencegah eksklusivisme ideologi oleh elite negara.
2. Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan
Alih-alih mengulang pendekatan normatif, kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus direformulasi menjadi laboratorium kebangsaan. Pendekatan pedagogis berbasis studi kasus, proyek sosial, dan refleksi nilai harus diperluas. Misalnya:
Siswa diajak merancang kampanye anti-intoleransi berbasis sila kedua.
Mahasiswa membuat peta kemiskinan lokal sebagai bentuk penghayatan sila kelima.
Pengajar memfasilitasi forum debat nilai antar-pelajar sebagai bentuk musyawarah.
Nilai tidak dihafalkan, melainkan dihidupi melalui pengalaman belajar yang membumi.
3. Audit Kebijakan Publik Berbasis Pancasila
Setiap kebijakan strategis di tingkat nasional maupun daerah perlu melewati “uji nilai” Pancasila. Pemerintah dapat membentuk instrumen Audit Kebijakan Pancasila—tim independen lintas-disiplin yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mencerminkan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, musyawarah, dan keberagaman.
Audit ini juga bisa menjadi bagian dari reformasi birokrasi berbasis etika, mencegah kebijakan yang diskriminatif, eksploitatif, atau manipulatif yang mengatasnamakan pembangunan.
4. Penguatan Ekosistem Etika Publik Berbasis Komunitas
Pancasila harus mengakar dalam gerakan komunitas, bukan hanya institusi negara. Pemerintah dan sektor sipil dapat mengembangkan program “Pancasila Berbasis Komunitas”, seperti:
Pembentukan rumah nilai Pancasila di kelurahan sebagai pusat dialog, kegiatan lintas iman, dan resolusi konflik.
Festival budaya Pancasila tahunan untuk merayakan keberagaman dan solidaritas sosial.
Inisiatif lokal seperti bank gotong royong, koperasi pangan, atau sekolah adat sebagai penerjemahan konkret sila ke-3 dan ke-5.
Program ini akan menciptakan ekosistem nilai yang mandiri, berakar, dan berkelanjutan.
5. Literasi Digital Pancasila sebagai Tanggapan Era Post-Truth
Di tengah banjir disinformasi dan ujaran kebencian, perlu dibentuk Gerakan Literasi Digital Berbasis Nilai Pancasila. Tujuannya adalah memperkuat daya tahan masyarakat, khususnya anak muda, terhadap manipulasi ideologis di media sosial. Gerakan ini harus bersifat kolaboratif—antara platform digital, pemerintah, sekolah, dan tokoh masyarakat.
Sebagai contoh, sila pertama bisa menjadi dasar penguatan narasi toleransi lintas iman, sila keempat memperkuat budaya diskusi sehat, dan sila kelima menolak konten yang diskriminatif.
Dari Ide ke Etika, dari Nilai ke Tindakan
Rekomendasi-rekomendasi di atas bukan sekadar pelengkap normatif, melainkan tangga praksis yang menghubungkan fondasi filosofis Pancasila dengan ruang hidup rakyat. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Soedjatmoko, ideologi tidak akan bermakna jika tidak hidup dalam tindakan moral masyarakat⁴.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai Ius Integrum Nusantara, kita diajak melampaui simbol, memasuki substansi, dan mewujudkannya dalam sistem sosial-politik yang etis, adil, dan inklusif. Kini, tantangannya bukan lagi mempertanyakan apakah Pancasila sakti, melainkan apakah kita cukup berani untuk menghidupkannya.
Epistemologi Pancasila – Menyelamatkan Cara Bangsa Memahami Dirinya
Di tengah kompleksitas krisis kebangsaan—korupsi sistemik, arus disinformasi digital, melemahnya etika publik—kita harus menggeser fokus bukan lagi pada definisi Pancasila, tapi pada bagaimana bangsa ini mengetahui dan menafsirkan Pancasila secara benar dan berkelanjutan. Epistemologi Pancasila bukan hanya tentang apa yang kita hafal, melainkan bagaimana nilai-nilainya meninggalkan jejak pada cara kita berpikir, bertindak, dan berdialog.
Selain itu, dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, epistemologi Pancasila menjadi alat analisis yang mengakar pada realitas lokal: sejarah, budaya, spiritualitas masyarakat. Penafsiran bukan monopoli elite negara atau institusi formal saja, melainkan hasil pertukaran dialogis antara warga, komunitas, pemimpin lokal, dan struktur hukum publik. Ini memungkinkan Pancasila tumbuh sebagai sistem pengetahuan bangsa yang dinamis dan responsif.
Model pendidikan yang dominan saat ini, seperti yang dikritisi oleh Paulo Freire, memperlakukan peserta didik sebagai objek pengisian nilai, bukan subjek yang membangun pemahaman kritis (Freire, 1970). Model semacam ini memang menciptakan kepatuhan simbolik, tapi tidak menyemai kedalaman reflektif. Padahal, Pancasila hanya akan menjadi nyata bila nilai-nileyang diajarkan tersambung dengan kenyataan sosial: keadilan ekonomi, tanggung jawab budaya, harmonisasi keberagaman.
Kemudian, dalam pemikiran Notonagoro, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat hidup bangsa yang integral dan universal, tetapi berpijak pada realitas budaya Indonesia sendiri (Notonagoro, 1974). Dari situ tampak bahwa epistemologi Pancasila yang sehat tak bersandar pada cetak biru ideologi impor, tetapi pada tradisi lokal, pengalaman rakyat, serta problem nyata yang dihadapi masyarakat.
Pengetahuan akan Pancasila harus inklusif, membuka ruang kritik dan adaptasi. Franz Magnis-Suseno pernah menegaskan bahwa Pancasila bukan sistem hukum mati, melainkan sistem moral hidup yang terus ditafsirkan dalam konteks etika dan budaya kita sehari-hari (Magnis-Suseno, 2001). Ia menolak pemisahan tegas antara norma hukum dan norma moral dalam praktik kenegaraan; dalam pandangannya, moralitas dan nilai-nilai etis harus menjadi bahan uji bagi setiap kebijakan, setiap kebijakan publik harus mampu dijawab bukan hanya oleh undang-undang, tetapi oleh nurani kolektif dan pengalaman rakyat.
Untuk merevitalisasi epistemologi Pancasila melalui Ius Integrum Nusantara, beberapa langkah aplikatif perlu diambil:
Membuka ruang dialog di tingkat komunitas untuk menafsirkan butir-butir Pancasila setempat, yang memungkinkan adaptasi nilai sesuai konteks lokal dan sekaligus menjaga kesatuan nilai nasional.
Memperbarui kurikulum Pancasila/Kewarganegaraan dengan materi studi kasus lokal dan proyek refleksi sosial agar siswa bukan hanya hafal sila, tetapi mengalami sila dalam tindakan nyata.
Mendorong literasi digital berbasis nilai Pancasila; media massa dan platform digital harus menyediakan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong empati, keadilan, dan partisipasi aktif.
Dengan demikian, epistemologi Pancasila tidak lagi menjadi soal simbol, melainkan panggilan moral dan praksis budaya yang menyatu dengan prinsip Ius Integrum Nusantara. Bila generasi mampu mengetahui dan memahami Pancasila secara kritis dan hidup, maka kekuatan moral bangsa akan kembali menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan.
Aksiologi Historis P4 dan Rekomendasi Aplikatif
Bagian sebelumnya telah menelaah anatomi filosofis Pancasila dari sudut ontologi dan epistemologi. Kini saatnya menyentuh dimensi nilai guna (aksiologi) melalui refleksi historis terhadap Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru, serta merumuskan rekomendasi aplikatif agar Pancasila kembali membumi dan hidup di tengah masyarakat.
P4 sebagai Eksperimen Aksiologis Orde Baru
P4 lahir lewat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 sebagai upaya sistematis Orde Baru untuk menjabarkan kelima sila Pancasila menjadi 36 butir pengamalan praktis yang wajib diterapkan oleh aparatur negara, organisasi massa, hingga warga biasa. Tujuannya: menjadikan Pancasila bukan hanya konsep, tetapi pedoman hidup sehari-hari. Pemerintah membentuk BP7 (Badan Pembina Penataran P4) dan P7 (Penasihat Presiden) untuk menyebarkan pendidikan nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat—dengan metode penataran massal, modul, dan penyuluhan lewat institusi negara. Praktik ini dianggap sebagai bentuk pembumian nilai negara lewat perangkat negara resmi.
Namun aspek aplikatif P4 menyimpan paradoks: di satu sisi, ia memperkuat kesadaran ideologis dan membentuk norma etika publik; di sisi lain, ia sering dipakai sebagai instrumen kontrol ideologi. Kritik muncul karena ruang interpretasi lokal dan kritik sosial dibatasi—P4 cenderung mematikan pluralisme tafsir dan membelenggu kreativitas nilai lokal (etika Pancasila masa Orde Baru)¹¹. Dengan demikian, P4 adalah contoh konkret bagaimana nilai-nilai abstrak bisa diturunkan ke tindakan lewat norma publik. Ia juga memperlihatkan bahwa nilai guna Pancasila hanya efektif bila disertai ruang dialog dan adaptasi lokal—sesuatu yang harus menjadi pelajaran dalam merancang aksiologi Pancasila masa kini.
Rekomendasi Aplikatif Berdasarkan Aksiologi P4 dan Ius Integrum Nusantara
Berangkat dari refleksi P4 dan analisis nilai guna, berikut rekomendasi aplikatif agar Pancasila kembali menjadi landasan praksis—bukan sekadar simbol politik:
1. Penataran Pancasila Kontekstual dan Partisipatif
Program penataran nilai Pancasila tidak boleh kembali ke format dogmatis Orde Baru. Penataran sekarang harus berbasis lokal—mengadaptasi butir-butir nilai sesuai kebutuhan budaya daerah, tanpa mengorbankan kesatuan nilai nasional. Institusi seperti BPIP harus mensinergikan materi nasional dengan dialog komunitas lokal.
2. Integrasi Nilai P4 ke Kurikulum Pendidikan Moderat
Butir-butir P4 sebaiknya dijadikan referensi dalam kurikulum Pancasila/Kewarganegaraan (PPKn) dengan versi adaptif—sebagai modul nilai kontekstual, bukan butir kaku. Dalam Kurikulum Merdeka, misalnya, pendekatan P5 bisa menjadi wahana untuk menerjemahkan nilai Pancasila dalam proyek-proyek lokal. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi penataran P4 dalam sistem P5 dapat menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan pendidikan kontemporer (penelitian Transformasi Penataran P4 ke Kurikulum Merdeka).
3. Auditing Nilai dalam Kebijakan Publik
Pancasila sebagai aksiologi harus diuji dalam kebijakan nyata. Perlu dibentuk unit audit nilai Pancasila di pemerintah daerah dan nasional, untuk menilai sejauh mana regulasi, anggaran, dan program publik mencerminkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Kebijakan yang gagal standar nilai harus dievaluasi ulang.
4. Penguatan Komunitas Nilai Lokal
Nilai Pancasila harus dikelola tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat sipil dan komunitas lokal. Program Pancasila Berbasis Komunitas bisa mencakup rumah nilai, forum dialog lintas iman, festival kebersamaan, dan proyek gotong-royong nyata. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari, bukan dokumen kantoran.
5. Literasi Nilai di Era Digital
P4 zaman Orde Baru belum mengenal dunia digital. Saat ini, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam ruang maya: media sosial, platform digital, dan aplikasi edukasi. Program literasi digital berbasis Pancasila menjadi urgensi, melatih warga mengenali hoaks, membangun empati daring, dan menggunakan teknologi untuk memperkuat nilai keadaban.
Dengan menyatukan refleksi historis terhadap P4 dan rekomendasi aplikatif kontemporer, aksiologi Pancasila tidak lagi menjadi wacana kosong. Alih-alih menjadi simbol formal semata, Pancasila dalam kerangka Ius Integrum Nusantara bisa kembali menjadi fondasi moral dan etika yang membumi, relevan, dan transformasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Aksiologi Pancasila – Nilai Guna dalam Kehidupan Sosial dan Politik
Jika ontologi menanyakan apa Pancasila itu, dan epistemologi menelisik bagaimana kita memahami Pancasila, maka aksiologi menegaskan: untuk apa Pancasila hadir? Sebab membahas nilai tanpa penerapan adalah membiarkan idealisme membeku. Aksiologi Pancasila menuntut agar nilai-nilainya dijadikan pemandu nyata dalam sosial-politik Indonesia. Dalam konteks publik, Pancasila harus tampil sebagai etika publik — arah normatif yang menjembatani nilai dan kebijakan, warga dan negara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan sekadar sila yang dihafal, tapi prinsip yang menggerakkan tindakan kolektif dan kebijakan negara. Namun dalam praktik, sering terjadi kompromi nilai: pasar mengalahkan keadilan sosial, identitas mayoritas meredam persatuan, dan kekuasaan mendominasi hukum dan kebijakan.
Menurut Franz Magnis-Suseno, inti nilai guna Pancasila terletak pada kemampuannya menjaga martabat manusia dalam tatanan hidup bersama yang adil dan manusiawi. Pancasila bukan volatil slogan politik, tetapi landasan moral yang wajib disematkan dalam setiap keputusan kolektif. Nilai-nilai itu harus teruji — di gedung legislatif, ruang kebijakan publik, bahkan dalam ruang diskursus media.
Mewujudkan Pancasila sebagai aksiologi berarti menurunkan norma ke dalam tindakan kolektif. Setiap kebijakan negara, mulai dari anggaran daerah hingga program sosial, harus dapat diuji terhadap tolok nilai Pancasila: apakah memperkuat keadilan? Apakah mengikutsertakan warga? Apakah menghargai keragaman dan martabat manusia? Di sinilah relevansi Ius Integrum Nusantara muncul: pendekatan ini menolak dikotomi antara norma hukum dan etika lokal — hukum tidak boleh abai nilai, dan etika tidak boleh tumpas oleh kekuasaan formal. Dalam kerangka Ius Integrum, Pancasila bukan hanya sumber dari segala sumber hukum, melainkan juga sumber dari segala tindakan kolektif. Artinya, kebijakan dan budaya publik harus secara organik mencerminkan nilai-nilai Pancasila — bukan sebagai retorika, tetapi sebagai pijakan nyata yang hidup di lanskap sosial. Partisipasi warga, demokrasi substantif, dan kebijakan berpihak adalah ekspresi aksiologis Pancasila.
Aksiologi Pancasila juga memandu demokrasi agar tidak stagnan pada prosedur. Demokrasi bukan sekadar angka partisipasi, tetapi kearifan kolektif. Yudi Latif mengingatkan bahwa demokrasi Pancasila bukan sistem kekuasaan melulu, melainkan jalur kearifan sosial yang berakar pada nilai gotong-royong dan belas kasih. Dengan demikian, politik tak cukup menang-kalah; ia menjadi arena kolaborasi untuk menyejahterakan bersama — di mana suara minoritas dihormati dan keputusan bersama dijunjung. Dalam jangka panjang, Pancasila sebagai aksiologi tidak mungkin hidup hanya lewat negara. Masyarakat sipil, media independen, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan memegang peran vital dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Dalam semangat Ius Integrum Nusantara, budaya hukum bukan monopoli aparatus, melainkan kesadaran kolektif warga. Nilai Pancasila harus muncul dalam praktik sehari-hari: musyawarah kampung, solidaritas di saat krisis, hingga keberanian publik menuntut keadilan.
Seperti ditegaskan oleh Soedjatmoko, “ideologi tidak akan berarti apa-apa jika tidak menjelma menjadi tindakan moral kolektif.” Kesaktian Pancasila hari ini bukan ditentukan oleh narasi sejarah, melainkan oleh kapasitas rakyat untuk menjadikannya cahaya nilai dalam tindakan nyata di tengah kehidupan sehari-hari.
Menghidupi Pancasila sebagai Dasar Filosofis Bangsa dalam Perspektif Ius Integrum Nusantara
Di tengah arus perubahan global, kegaduhan politik, serta menguatnya fragmentasi sosial dan moral, Pancasila tetap menjadi jangkar historis sekaligus kompas filosofis bangsa Indonesia. Namun, pertanyaan mendasarnya hari ini bukan semata tentang pengakuan terhadap Pancasila, melainkan: bagaimana bangsa ini benar-benar memahami dan menghidupi Pancasila secara otentik dan kontekstual? Pada titik inilah, pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap Pancasila menemukan relevansinya, terutama jika ditopang oleh kerangka ius integrum Nusantara—sebuah paradigma hukum dan nilai yang menyatu dengan tradisi, etika publik, dan realitas sosial Indonesia.
Meneguhkan Fondasi Identitas Bangsa
Pancasila bukanlah produk ideologis dari luar, melainkan realitas historis dan kultural yang tumbuh dari bumi Nusantara. Ia lahir dari konsensus besar bangsa pada 1 Juni 1945, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto: “Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai prestasi cemerlang bangsa Indonesia.”
Pancasila tidak sekadar lima sila normatif yang dirumuskan para elite, melainkan hasil sublimasi nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia: ketuhanan yang inklusif, kemanusiaan yang adil, persatuan yang mengatasi sekat primordial, kerakyatan yang demokratis, dan keadilan sosial yang membumi.
Dalam perspektif ius integrum Nusantara, Pancasila bukan hanya fondasi konstitusional, tetapi juga mencerminkan jiwa bangsa (geist des volks). Notonagoro menekankan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat hidup yang menyatu dengan kebudayaan Indonesia, dan karenanya bersifat organis, dinamis, dan kontekstual.
Menyelamatkan Cara Bangsa Memahami Dirinya
Sayangnya, pendidikan Pancasila selama ini masih banyak terjebak dalam pendekatan tekstual, normatif, dan seremonial, alih-alih menumbuhkan kesadaran kritis. Dalam istilah Paulo Freire, ini adalah bentuk dari banking concept of education, di mana peserta didik diposisikan sebagai wadah pasif penerima informasi tanpa partisipasi dalam pemaknaan.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh survei Alvara Research Center (2022) yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% mahasiswa tidak mampu mengaitkan nilai Pancasila dengan isu-isu aktual seperti korupsi, radikalisme, atau kemiskinan digital.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menggarisbawahi bahwa: “Saya sebagai Presiden melihat masih terlalu banyak penyelewengan, korupsi, dan manipulasi justru di tubuh kekuasaan. Karena itu, kita semua harus kembali ke nilai-nilai Pancasila. Pancasila hidup dan bukan sekadar mantra. Kita harus jadi penjaga dan pembela nilai-nilai itu.”
Melalui pendekatan ius integrum, pemahaman terhadap Pancasila harus dikontekstualisasikan dalam realitas sosial bangsa. Ia harus dipelajari melalui metode dialogis, reflektif, dan partisipatif, bukan sekadar hafalan normatif.
Dari Norma ke Tindakan Etis dan Sosial
Secara aksiologis, Pancasila bukan hanya sistem nilai, melainkan pedoman etika publik dan praksis sosial. Nilai-nilai Pancasila seharusnya hadir dalam kebijakan, birokrasi, dan kepemimpinan. Namun realitas memperlihatkan sebaliknya: keadilan sosial kerap dikalahkan oleh kapitalisme predator, dan persatuan dikoyak oleh politik identitas. Franz Magnis-Suseno mengingatkan bahwa Pancasila hanya berguna jika dijadikan dasar moral konkret dalam kehidupan politik dan pemerintahan5. Dalam konteks ini, pendekatan ius integrum Nusantara menawarkan koreksi mendasar: bahwa hukum dan kebijakan tidak pernah netral—ia membawa nilai dan ideologi, dan karena itu harus memihak pada keadilan substantif.
Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya generasi muda sebagai aktor utama: “Anak generasi emas adalah garda terdepan dalam menjaga Pancasila tetap hidup, bukan hanya dalam hafalan, tetapi dalam sikap, karya, dan karakter.” Pernyataan ini menjadi seruan aksiologis: Pancasila harus dijalani sebagai praktik hidup, bukan hanya doktrin simbolik.
Revitalisasi Pancasila sebagai Agenda Publik
Revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi agenda kolektif seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo menyebut: “Pancasila memperkenankan kita untuk bersatu di tengah dinamika dunia yang penuh ketidakpastian. Tema peringatan ini, ‘Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya’ bukan hanya ajakan, tapi komitmen.”
Media, institusi pendidikan, komunitas adat, hingga birokrasi publik harus memperbarui cara menyampaikan nilai-nilai Pancasila, dengan bahasa dan format yang bisa menyentuh nurani generasi digital. Generasi muda tidak cukup diposisikan sebagai objek pewarisan, melainkan sebagai subjek pencipta nilai baru. Seperti diungkap Soedjatmoko, ideologi hanya akan hidup jika menjelma dalam tindakan moral kolektif. Maka Hari Lahir Pancasila bukan sekadar ritual, melainkan momentum transformasi struktural dan kultural bangsa.
Jalan Menuju Indonesia Emas
Pancasila adalah ius integrum Nusantara—nilai hidup bangsa yang mempersatukan ontologi kebangsaan, epistemologi sosial, dan aksiologi tindakan. Jika bangsa ini ingin bangkit dari krisis moral, politik, dan ekonomi, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Pancasila yang dipahami secara utuh, kritis, dan kontekstual.
Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto: “Mari kita terus kokohkan ideologi Pancasila untuk wujudkan Indonesia Emas yang kuat dan bersatu.”
Pancasila bukan mitos, bukan pula slogan. Ia adalah jalan hidup bangsa, yang harus terus dijaga, dibela, dan dihidupi—oleh setiap warga negara, terutama generasi penerus—demi Indonesia yang adil, bermartabat, dan berdaulat.
Refleksi Penutup dalam Narasi Publik dan Generasional
Mengakhiri perjalanan pemikiran ini, kita kembali kepada pertanyaan fundamental: apa arti Pancasila hari ini, dalam dunia yang berubah begitu cepat? Globalisasi, disrupsi digital, dan pluralitas sosial menuntut agar Pancasila tak hanya dikenang sebagai teks sejarah, melainkan dihidupkan sebagai denyut nadi bangsa yang terus bergerak.
Ontologi–Epistemologi–Aksiologi bukan hanya kerangka teoritis belaka, melainkan peta pemahaman dan transformasi: memahami apa itu Pancasila; meninjau kembali cara kita mengetahuinya; lalu memerankan nilai-nilainya dalam tindakan nyata. Refleksi publik dan generasional menjadi jembatan antara akar historis bangsa dan visi masa depan yang lebih manusiawi.
Memperkuat Persatuan
Dalam ruang publik, Pancasila harus tampil sebagai narasi bersama — bukan alat kampanye, bukan doktrin tertutup — melainkan bahasa nilai yang mengajak warga berpijak pada kesamaan, bukan sekat. Media massa, lembaga budaya, dan komunitas harus mengambil peran strategis dalam mendialogkan Pancasila sebagai landasan moral kolektif, menolak retorika sektarian yang memecah. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tak cukup menjadi ritual tahunan; ia harus menjadi momen reflektif dan aksi — momen ketika publik menanyakan kembali: adakah kebijakan kita selaras dengan nilai keadilan dan kemanusiaan?
Warisan Nilai yang Hidup
Generasi muda adalah ujung tombak keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan. Namun kenyataannya, banyak yang hanya mengenal Pancasila sebagai hafalan, tanpa peta nilai yang hidup. Pendidikan Pancasila harus dilebur menjadi pendidikan nilai—pendekatan partisipatif yang menyentuh pemikiran (epistemologi) dan praktik (aksiologi), agar nilai-nilai Pancasila dapat meresap dan menjadi landasan moral dalam menghadapi tantangan kontemporer.
Selain itu, generasi muda perlu ditempatkan sebagai agen perubahan: bukan konsumen wacana semata, tetapi penggerak politik sosial yang merujuk Pancasila sebagai dasar bertindak. Melalui inovasi sosial, diskursus publik, dan aktivitas budaya, mereka bisa menjadikan nilai-nilai Pancasila nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila sebagai Jiwa Kolektif
Pancasila tidak boleh tinggal sebagai teks kenangan, melainkan sebagai jiwa kolektif yang memandu langkah bersama. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, Pancasila adalah hukum moral integral yang menyatukan aspek kenegaraan dan pengalaman rakyat. Krisis kebangsaan hari ini bukan akhir, melainkan panggilan agar kita kembali menumbuhkan akar nilai dalam tindakan publik nyata. Jika Pancasila menjadi kompas moral dalam kebijakan dan kehidupan publik, maka Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tetapi tumbuh menjadi bangsa bermartabat, inklusif, dan berkeadilan. Kesaktian Pancasila terletak bukan pada simbol upacara, melainkan pada keberanian kita menjadikannya etika hidup—bersama, dalam tindakan dan keputusan kolektif.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus dijadikan panggilan reflektif sekaligus aksi kolektif. Pancasila harus hidup dalam nurani, pikiran, dan tindakan setiap warga. Sebagai warisan luhur yang terus berkembang, ia harus menyatu dengan denyut kehidupan generasi mendatang, menjadi fondasi moral dan spiritual Indonesia masa depan.
Indonesia saat ini menghadapi krisis nilai yang kompleks, di mana Pancasila sebagai landasan filosofis kebangsaan kian terpinggirkan dan direduksi menjadi sekadar jargon politik atau ritual simbolik. Krisis ini bukan hanya persoalan institusional atau hukum, melainkan krisis mendalam pada pemahaman dan pengamalan Pancasila yang harus dilihat melalui lensa ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Secara ontologis, Pancasila adalah esensi identitas bangsa yang lahir dari realitas historis, kultural, dan spiritual Nusantara. Ia merepresentasikan jiwa kolektif bangsa yang plural dan religius, menjadikan kebhinekaan sebagai sumber kekuatan moral dan spiritual. Epistemologisnya menuntut cara memahami Pancasila secara kritis dan reflektif, jauh melampaui hafalan tekstual, agar nilai-nilainya dapat diaplikasikan dalam konteks sosial yang dinamis dan kompleks, termasuk tantangan teknologi dan perubahan global. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ius integrum Nusantara yang memandang hukum dan nilai tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan kearifan lokal. Dari sisi aksiologi, Pancasila harus diinternalisasi sebagai pedoman moral yang nyata dalam kehidupan publik, di mana nilai-nilainya menuntun tindakan berkeadilan, inklusif, dan demokratis. Krisis kebangsaan saat ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai tersebut, yang kemudian melemahkan fondasi sosial-politik dan memperlebar jurang ketidakadilan. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi landasan etika dalam sistem hukum dan kebijakan negara, bukan hanya dokumen normatif, melainkan spirit yang menghidupkan demokrasi substansial dan kesejahteraan bersama.
Penting pula untuk menghidupkan kembali narasi publik dan generasional tentang Pancasila. Narasi ini harus bersifat inklusif dan menyatukan seluruh elemen bangsa, sekaligus memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan yang menginternalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Pendidikan Pancasila perlu direformasi agar berorientasi pada pemahaman nilai-nilai secara kontekstual dan partisipatif, sehingga generasi mendatang mampu menerjemahkan filosofi Pancasila ke dalam tindakan nyata. Sebagai langkah prospektif, reformasi pendidikan, penguatan narasi publik melalui media dan budaya, pembentukan kepemimpinan etis, reformasi sistem hukum berlandaskan ius integrum Nusantara, serta pemberdayaan generasi muda menjadi kunci strategis untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga harus dikemas ulang menjadi momen refleksi dan aksi nyata, bukan ritual formalitas semata.
Dengan pendekatan sistemik yang menyatukan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Pancasila dapat berfungsi sebagai kompas moral dan landasan etika yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju masa depan yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan. Kesaktian sejati Pancasila terletak pada kemampuannya untuk menjelma menjadi perilaku dan kebijakan yang menyatukan, membebaskan, dan mensejahterakan seluruh rakyat. Sebagai ius integrum Nusantara, Pancasila adalah warisan luhur sekaligus tugas kolektif untuk terus dihidupkan dalam denyut kehidupan bangsa, menyatukan masa lalu dengan harapan generasi masa depan.
Referensi
Alvara Research Center. Survei Persepsi Generasi Muda terhadap Pancasila. Jakarta, 2022.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Salinan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4): Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979. Diakses dari: https://jdih.bpip.go.id
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 1970.
Kompas. “Mengenang Penataran P4, Ketika Orde Baru Melakukan Indoktrinasi Pancasila.” Kompas.com, 31 Mei 2022.
Latif, Yudi. Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan. Bandung: Mizan, 2018.
Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia, 2011.
Litbang Kompas. Survei Nasional: Pemahaman Generasi Muda terhadap Nilai Pancasila. Jakarta: Kompas Research & Development, 2023.
Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 1999.
Notonagoro. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1974.
Pidato Presiden Prabowo Subianto. Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.
Soedjatmoko. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Jakarta: LP3ES, 1984.
Tim Penulis. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Jakarta: BP7, 1978.
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Makalah: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila: Membangun Kenegarawanan. Lumbung Pustaka UNY.
Penulis adalah Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia