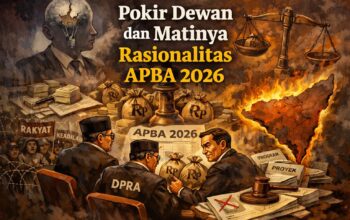Oleh: Farid Wajdi
Bencana sering datang dengan cara paling menghancurkan: tiba-tiba, membabi buta, dan tidak peduli siapa yang berdiri di hadapannya.
Di Sumatera, banjir dan longsor kembali menenggelamkan desa-desa, menyapu jembatan, memutus jalan, dan mengusir ribuan warga dari rumah yang mereka bangun selama puluhan tahun.
Situasi ini menyajikan fakta paling telanjang tentang negeri ini: manusia selalu berada di garis paling rapuh, sementara urusan birokrasi sering bersembunyi di balik alasan teknis.
Narasi lapangan menunjukkan penderitaan konkret. Kompas (2025) melaporkan evakuasi yang terhambat cuaca buruk dan logistik yang tak kunjung tiba di titik terdampak.
Dompet Dhuafa bergerak lebih cepat daripada sebagian institusi formal, menurunkan perahu karet dan dapur umum sebelum rapat koordinasi rampung.
Pola semacam ini menjadi pengingat pahit: publik bergerak lebih sigap daripada sejumlah lembaga yang memegang mandat resmi penanganan bencana.
Di tengah kepungan air, publik membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar pernyataan normatif. Publik memerlukan negara yang hadir sebagai penyelamat, bukan pengamat.
Gerak lambat pemerintah tidak hanya memperlambat bantuan; gerak lambat berpotensi menjadi bumerang moral yang meruntuhkan kewibawaan.
Bencana selalu menjadi momen ketika legitimasi diuji. Bukan melalui slogan, tetapi melalui tindakan cepat yang menyentuh nyawa manusia.
Komunikasi krisis seharusnya menjadi sumbu utama penanganan bencana. Ilmu komunikasi darurat mengajarkan prinsip dasar: pesan harus cepat, akurat, lugas, dan empatik.
LSPR (2019) menegaskan komunikasi bukan sekadar transmisi informasi; komunikasi memengaruhi persepsi risiko, menentukan arah evakuasi, dan membentuk kepercayaan publik.
Namun, sejumlah pejabat justru tampil dengan pernyataan yang menyakiti warga yang sedang berjuang menyelamatkan hidup.
Kepala BNPB menjadi contoh paling mencolok ketika menyebut kesan mencekam banjir “lebih terlihat di media sosial” (Detik, 2025). Kalimat itu menyulut kemarahan publik yang sedang berebut tempat aman, menunggu bantuan, atau mencari anggota keluarga yang hilang.
Pernyataan nir-empati semacam ini bukan sekadar salah tekanan; pernyataan tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan dasar terhadap tragedi manusia. Ketika pejabat publik gagal menggunakan bahasa yang tepat, kerusakan sosial meluas lebih cepat dari kerusakan fisik.
BNPB kemudian meminta maaf, tetapi dampaknya sudah telanjur menyebar. Ketidakpekaan pejabat memperbesar jurang antara institusi negara dan warga terdampak.
Kritik mengalir dari berbagai kelompok masyarakat sipil. LSM Aceh menilai komentar tersebut “kurang empati dan tidak memahami rasa takut warga” (Tribun Aceh, 2025).
Ketika pejabat menganggap pengalaman korban sebagai isu persepsi, publik kehilangan pegangan pada institusi yang seharusnya menjadi jangkar keselamatan.
Kegagalan komunikasi semacam ini menambah berat beban psikologis warga. Negara kehilangan momentum penting untuk memimpin narasi secara moral. Padahal, komunikasi krisis yang baik mampu menenangkan publik dan mencegah kepanikan.
Komunikasi yang buruk justru memicu turbulensi emosional. BRIN (2023) menunjukkan temuan kuat: ketidakjujuran atau ketidakterampilan komunikasi memperparah kekacauan sosial pada masa pandemi. Pola tersebut tampak berulang dalam penanganan bencana alam.
Bencana selalu memberi ruang bagi seseorang untuk menyalakan rasa kemanusiaan. Di berbagai wilayah Sumatera, relawan lokal mengangkut warga lanjut usia dengan gerobak, menjemput anak-anak dari rumah terendam, hingga menyalakan dapur umum sederhana.
Kompas (2025) mendokumentasikan bagaimana kelompok pemuda di Sumatera Barat menjahit sendiri perahu karet darurat dari ban dalam truk. Semua dilakukan bukan karena mereka memiliki mandat, tetapi karena naluri kemanusiaan bergerak lebih cepat daripada prosedur.
Gerakan solidaritas ini selaras dengan gagasan Hans Küng (1998) tentang etika global: “Kemanusiaan bertahan bukan melalui kekuatan negara, melainkan melalui tindakan moral individu yang memilih untuk tidak membiarkan sesamanya mati.”
Pandangan itu menemukan relevansinya pada momen seperti ini, ketika negara masih berkutat dengan penilaian kerusakan, sementara publik sudah mengevakuasi jenazah.
Namun solidaritas publik tidak dapat menggantikan mandat negara. Relawan tidak memiliki data lengkap, akses logistik skala besar, atau kewenangan untuk membuka jalur darurat.
Negara tetap memegang tanggung jawab tertinggi untuk melindungi nyawa. Bencana bukan ruang untuk administrasi yang ragu-ragu.
Irfan Noor (2021) menjelaskan dalam kajian kebencanaan negara perlu memiliki “keberanian administratif” untuk mempercepat keputusan, termasuk pemangkasan prosedur dan pemberlakuan diskresi kebencanaan.
Tanpa keberanian semacam ini, keselamatan warga sering kalah oleh kekhawatiran pejabat terhadap audit dan pemeriksaan.
Ketidaktegasan administrasi menjadi kendala laten. Bantuan logistik sering tertahan karena menunggu otorisasi, sementara korban menunggu pertolongan dengan tubuh menggigil. Bencana tidak memberi ruang untuk menunggu tanda tangan.
Logistik seharusnya bergerak mendahului urusan kertas. Pemerintah kerap mencoba menjelaskan proses panjang itu sebagai “prosedur”, padahal masyarakat sedang menunggu air surut, bukan menunggu kelengkapan dokumen.
Nilai kemanusiaan bukan sekadar jargon. Nilai itu adalah prinsip operasional yang menentukan hidup dan mati seseorang.
Dalam maqasid al-syariah, hifz al-nafs menempati kedudukan paling tinggi: menjaga nyawa sebagai prioritas absolut. Prinsip serupa hidup dalam Piagam Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana (2011) yang menegaskan hak warga untuk menerima bantuan tepat waktu dan mendapatkan informasi akurat. Setiap jam keterlambatan berpotensi menghilangkan satu kehidupan.
Pandangan humanisme modern menempatkan martabat manusia sebagai titik pusat kebijakan publik. Dalam kerangka ini, negara tidak boleh memposisikan warga sebagai angka statistik. Setiap korban memiliki nama, sejarah, dan masa depan.
Program kerja kebencanaan seharusnya dimulai dari pertanyaan sederhana: “Siapa yang harus diselamatkan sekarang?” Ketika kebijakan berangkat dari pertanyaan moral semacam ini, seluruh mesin negara bergerak menuju prioritas yang benar.
Tantangan terbesar pemerintah sering bukan pada kekurangan sumber daya, tetapi pada cara melihat bencana. Negara cenderung memulai dari pendekatan teknokratis: peta, data curah hujan, tabel kerusakan, laporan administratif.
Semua penting, tetapi semua itu hanya bekerja efektif jika empati memimpin langkah pertama. Empati menghadirkan keberanian untuk memutus rantai birokrasi. Empati menciptakan urgensi untuk menyelamatkan nyawa lebih dulu, menghitung kerugian belakangan.
Menyalakan kemanusiaan berarti menyalakan kewarasan moral di tengah kekacauan. Banyak negara berhasil mengurangi korban bukan karena kecanggihan alat, tetapi karena kualitas kepemimpinan.
Kepemimpinan semacam itu tidak lahir dari retorika. Kepemimpinan lahir dari keberanian untuk mengatakan situasi sebenarnya, dari kecepatan mengambil keputusan, dan dari kesediaan turun langsung bertemu korban tanpa kamera.
Indonesia memerlukan model kepemimpinan semacam ini. Bencana akan terus datang. Curah hujan tetap tinggi. Deforestasi terus memicu longsor. Sungai semakin dangkal.
Namun bangsa ini tidak boleh menyerah pada fatalisme. Selama nilai kemanusiaan ditempatkan di pusat kebijakan, publik masih memiliki harapan.
Menyalakan kemanusiaan berarti menolak tunduk pada kelumpuhan birokrasi. Menyalakan kemanusiaan berarti menegur pejabat yang berbicara tanpa empati. Menyalakan kemanusiaan berarti menempatkan manusia sebagai prioritas kebijakan di titik paling gelap dalam hidup mereka.
Selama nyala itu terus dijaga, bangsa ini tetap memiliki alasan untuk percaya: bencana bisa menghancurkan banyak hal, tetapi tidak pernah mampu memadamkan rasa kemanusiaan yang memilih untuk berdiri bersama yang paling rapuh. (Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU).