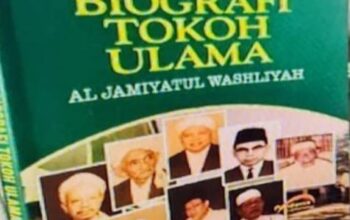Oleh Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.
Pengantar
Indonesia kini berdiri di persimpangan kritis: di satu sisi ialah cita-cita reforma agraria, mengakui hak ulayat dan kedaulatan pangan; di sisi lain, realitas administrasi pertanahan menunjukkan betapa hukum positif kerap gagal menjawab tuntutan keadilan historis dan sosial. Konflik agraria yang berulang dari lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di Deli hingga sengketa wilayah adat di Papua membuka celah besar bahwa hukum pertanahan selama ini lebih dipahami sebagai perangkat lex administratif, bukan sebagai sistem nilai ius yang menghormati akar kultural dan ekologis masyarakat adat. Paradigma Ius Integrum Nusantara muncul sebagai protes konseptual sekaligus solusi praktis: ia menuntut agar hak ulayat dan kedaulatan pangan menjadi pilar utama dalam sistem hukum agraria nasional.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, arah idealnya adalah membangun keadilan agraria yang menghargai pluralitas hukum adat dan fungsi sosial tanah. Namun, dominasi orientasi modal dan fragmentasi kelembagaan justru memperkokoh ketimpangan. Konsesi besar, perpanjangan HGU, dan izin pertambangan sering dikeluarkan tanpa mempertimbangkan legitimasi historis masyarakat adat atas tanah mereka: prosedur administratif dijunjung tinggi, tetapi verifikasi sosial-historis diabaikan. Inilah yang dalam retorika modern disebut lawful dispossession — perampasan yang terlihat “sah” di atas kertas, tetapi meniadakan hak komunal yang hidup secara konkret dalam komunitas.
Paradigma Ius Integrum Nusantara mengejawantahkan gagasan bahwa hukum pertanahan bukan sekadar instrumen legalitas, tetapi medium keadilan substantif. Di dalamnya, negara diposisikan sebagai public trustee, bukan pemilik absolut. Hukum nasional (ius positivum) tetap menjadi landasan, namun harus dipadu dengan agenda pembaruan (ius constituendum), norma internasional (ius gentium), dan legitimasi hukum adat (ius communitatis Nusantara). Dengan demikian, setiap kebijakan agraria dinilai bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga historis, ekologis, dan kultural.
Pilar pertama, paradigma ini adalah penetapan hak (recognition of rights). Hak ulayat bukanlah hak residu yang muncul setelah wilayah dikuasai negara, melainkan hak kolektif yang melekat pada komunitas adat sepanjang struktur sosial dan identitas budaya mereka masih hidup. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, misalnya, menegaskan bahwa hutan adat tidak menjadi hutan negara secara otomatis, dan pengakuan masyarakat adat dapat didasarkan pada fakta historis dan sosial tanpa perlu persetujuan administratif negara. Namun di lapangan, klaim formal terhadap tanah sering mengalahkan klaim historis-komunal: sertifikat, SK, dan dokumen BPN diprioritaskan atas bukti tradisional seperti peta adat, cerita leluhur, atau kesaksian tetua. Akibatnya, sepanjang proyek-proyek strategis dicanangkan, hak ulayat kerap dikompromikan demi kepentingan investasi.
Pilar kedua, distribusi dan akses (access and equity), menyoroti bahwa reforma agraria sejati tidak bisa hanya membagi lahan kosong. Distribusi tanah harus menyasar pemulihan hak historis masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. Tanah adat adalah bukti kedaulatan komunitas lokal (historical sovereignty) dan sekaligus basis akses ekologis dan sosial. Prinsip access justice menghendaki bahwa keadilan agraria bukan hanya soal siapa yang memiliki sertifikat, tetapi siapa yang benar-benar bisa mengelola lahan tersebut demi keberlanjutan pangan dan kesejahteraan komunitas. Realitas kekinian menunjukkan bahwa sebagian kecil pemilik modal menguasai lahan sangat besar, sedangkan petani kecil dan masyarakat adat kehilangan akses kritis. Model seperti ejido di Meksiko atau sertifikat kolektif quilombola di Brasil bisa menjadi inspirasi: negara memberi pengakuan langsung kepada komunitas adat atas hak kolektif mereka, bukan melalui fragmentasi kepemilikan individu.
Pilar ketiga, pemanfaatan sosial-ekologis (sustainable land use), mengajak kita melihat tanah sebagai entitas hidup yang menyatukan nilai sosial, ekologis, dan spiritual. Dalam paradigma ini, alih fungsi lahan harus diukur bukan hanya dari sudut ekonomi, tetapi dari kontribusi terhadap ekosistem dan kesejahteraan komunitas. Praktik adat seperti leuweung larangan (Jawa Barat), sasi (Maluku), dan rotasi ladang tradisional di Kalimantan menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah lama menjalankan prinsip ecological stewardship jauh sebelum terminologi modern muncul. Di samping itu, norma internasional seperti prinsip intergenerational equity dan precautionary principle mewajibkan negara untuk mempertimbangkan hak generasi mendatang sebelum membuat keputusan konversi lahan besar-besaran.
Pilar keempat, perlindungan dan penyelesaian konflik (protection and conflict resolution), menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak cukup melalui litigasi tradisional. Alih-alih hanya membatalkan SK atau menerbitkan putusan administrasi, dibutuhkan mekanisme restoratif yang mengembalikan tanah, memulihkan ekosistem, dan merestorasi identitas budaya. Model hibrida adjudikatif — yang melibatkan hakim, pemimpin adat, ahli agraria, dan perwakilan komunitas — memungkinkan pengakuan bukti historis, peta adat, dan kesaksian tradisional (testimonium orale) sebagai bagian dari proses penyelesaian. Prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) menjadi keharusan agar masyarakat setuju secara substansial sebelum keputusan diambil. Dalam konteks ini, kerangka hukum bergerak dari rule-based menuju justice-based, dimana legitimasi moral dan struktural menjadi landasan kekuatan hukum.
Refleksi Historis Memperkuat Urgensi Paradigma Ius Integrum Nusantara
Sejak era kolonial, sistem konsesi Belanda (melalui contractus concessionarium) mengatur tanah adat tanpa menghapus hak asal-usul komunitas. Setelah nasionalisasi pada tahun 1950-an, tanah bekas konsesi tetap memiliki akar ulayat, tetapi sering diberi cap “tanah negara” begitu HGU berakhir. Bahkan era UUPA pun tidak sepenuhnya membebaskan diri dari warisan kolonial: di satu sisi pengakuan adat diatur, tetapi praktik administratif dan sertifikasi formal justru mengakibatkan peminggiran komunitas. Modernisasi seperti PTSL semakin memperkuat rezim sertifikasi individual yang tidak sesuai dengan struktur komunal adat.
Lagipula, konstitusi memberikan pijakan kuat untuk paradigma integratif ini. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Pasal 28I ayat (3) menjadikan hak tradisional bagian dari hak asasi manusia, sementara Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa tanah “dikuasai oleh negara” bukanlah milik absolut, melainkan dikelola sebagai amanah bagi kemakmuran bersama. Konsep trusteeship ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan dan penghormatan atas hak komunal.
Dalam konteks komparatif, banyak negara telah menjajaki reformasi semacam ini. Di Kanada, misalnya, Mahkamah Agung dalam putusan Delgamuukw v. British Columbia mengakui aboriginal title sebagai hak komunal yang tidak bisa dihapus selain melalui pelepasan sah, dan menegaskan doktrin honour of the Crown yang menuntut negara untuk bertindak adil dan jujur terhadap masyarakat adat. Di Amerika Tengah, pengadilan internasional dalam kasus Awas Tingni v. Nicaragua memerintahkan negara membatalkan penetapan tanah tanpa persetujuan masyarakat dan menegakkan hak mereka atas lahan tradisional. Di Brasil, sertifikat kolektif quilombola mengakui wilayah historis komunitas Afro-Brasil sebagai milik bersama. Di Selandia Baru, Treaty of Waitangi Tribunal menjadi forum rekonsiliasi jangka panjang antara suku Māori dan negara, menyelidiki klaim masa lalu dan memberi rekomendasi pemulihan hak.
Semua pengalaman ini memberi cermin substansial bagi Indonesia: pengakuan hukum adat bukan semata simbolik, tetapi instrumen redistribusi dan restitusi; kedaulatan komunitas tidak dapat diabaikan; dan mekanisme konflik harus bersifat restoratif dan demokratis. Kritik terhadap kerangka hukum positif agraria Indonesia bukan berarti menolak legislasi nasional, melainkan memperkaya dan memperbaikinya. Ius Integrum Nusantara adalah panggilan untuk transformasi: pemulihan hak historis, pembaruan kelembagaan, dan pembentukan budaya agraria yang menghormati identitas serta keberlanjutan. Tanah ulayat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi masa depan: ruang hidup masyarakat, basis kedaulatan pangan, dan penjaga identitas budaya.
Jika Indonesia berani mengadopsi paradigma ini, maka sistem agraria dapat berubah dari mesin administrasi menjadi instrumen keadilan, dari alat kapital menjadi sarana rekonsiliasi, dan dari proyek pembangunan sepihak menjadi ekosistem partisipatif bersama masyarakat adat. Paradigma Ius Integrum Nusantara menawarkan harapan dan peta jalan menuju agraria yang adil, inklusif, dan berkelanjutan — tempat di mana hukum bukan hanya membagi tanah, tetapi menegakkan martabat dan kesejahteraan manusia Nusantara.
Tanah Adat sebagai Fondasi Masa Depan Hukum Agraria Indonesia
Di ujung perjalanan analisis ini, jelas bahwa tanah adat bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi masa depan hukum pertanahan Indonesia. Paradigma Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa pengelolaan agraria harus berpihak pada rakyat, menghormati legitimasi historis-komunal, dan menjaga keberlanjutan ekologis. Empat pilar—penetapan hak, distribusi dan akses, pemanfaatan sosial-ekologis, serta perlindungan dan penyelesaian konflik—menjadi instrumen integratif yang menutup jurang antara norma administratif dan nilai keadilan substantif.
Pengakuan hak ulayat, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, bukan sekadar simbol hukum; ia menandai penghormatan terhadap identitas budaya dan hak kedaulatan pangan masyarakat adat. Redistribusi tanah yang adil, pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, dan mekanisme restoratif dalam penyelesaian sengketa bukan hanya prosedur legal, tetapi sarana untuk menegakkan justice-based approach. Dalam perspektif historis, komparatif, dan konstitusional, paradigma ini menunjukkan bahwa tanah adalah hak rakyat yang tak terpisahkan dari pembangunan sosial, politik, dan ekonomi bangsa.
Tanah bukan lagi objek administratif atau aset ekonomi semata; ia adalah penopang kehidupan, identitas, dan kedaulatan komunitas. Dengan Ius Integrum Nusantara, hukum agraria bergerak dari formalitas menuju substansi keadilan: menghormati hak ulayat, memastikan akses dan distribusi yang adil, menjaga fungsi sosial-ekologis, dan membuka jalan bagi resolusi konflik yang partisipatif dan restoratif. Paradigma ini membuktikan bahwa masa depan hukum pertanahan Indonesia dapat berpihak pada rakyat Nusantara, melindungi warisan budaya, dan menjaga sumber daya sebagai milik kolektif yang sejati—menjadi pondasi bagi kedaulatan pangan dan keadilan agraria yang berkelanjutan.
Secara ringkas, epilog ini menegaskan bahwa penguatan paradigma Ius Integrum Nusantara adalah panggilan untuk memastikan bahwa hukum pertanahan Indonesia bukan hanya legalitas di atas kertas, tetapi legitimasi moral, sosial, dan ekologis yang nyata, mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Nusantara.
Krisis Hukum Positif dan Kebangkitan Hak Ulayat
Di banyak pelosok Nusantara, konflik tanah bukan sekadar persoalan batas sertifikat atau sengketa administratif — ia adalah benturan cara pandang tentang siapa sebetulnya pemilik tanah, siapa yang berhak menafsirkan relasi manusia dengan alam, dan atas dasar nilai apa hak-hak komunitas dihormati. Di tengah berkecamuknya ekspansi perkebunan, industrialisasi lahan, serta penetapan tanah negara secara sepihak setelah masa Hak Guna Usaha (HGU) berakhir, muncul kritik tajam bahwa kerangka hukum positif agraria Indonesia telah menjadi penyebab, bukan solusi, konflik struktural. Paradigma Ius Integrum Nusantara hadir sebagai jawaban konseptual dan operasional atas kegagalan sistem yang terlalu fokus pada legalitas formal tanpa legitimasi historis dan sosial.
Salah satu akar fundamental problem agraria terletak pada pemisahan artifisial antara tanah negara, tanah adat, dan hak atas tanah. Ketika suatu area HGU habis masa izinnya, aparat pertanahan sering menetapkan lahan tersebut sebagai “tanah negara” tanpa melakukan verifikasi memadai terhadap hak ulayat yang masih berjalan. Padahal, Pasal 3 UUPA 1960 dengan tegas menyatakan bahwa hak ulayat tetap diakui selama kenyataannya masih ada, sebagai bagian dari struktur agraria nasional. Dalam praktiknya, aparat lebih mementingkan kepastian administratif—survei peta, dokumen HGU, dan SK—daripada mempertanyakan legitimasi historis komunitas adat yang telah menggarap lahan selama puluhan generasi. Paradigma legalistik ini menciptakan kesan bahwa negara menganggap tanah sebagai aset birokrasi, bukan amanah sosial, dan memicu konflik horizontal yang terus berulang.
Kasus di Deli, Sumatra Utara, adalah contoh khas. Setelah perusahaan kolonial atau perkebunan meninggalkan wilayahnya, pemerintah menerbitkan SK Penetapan Tanah Negara atas lahan bekas HGU tanpa dialog mendalam dengan masyarakat Melayu yang mengklaim hak ulayat. Sementara itu, di Kalimantan Barat, masyarakat Dayak menghadapi tekanan dari operator sawit yang memperoleh izin konsesi berdekatan dengan wilayah tradisional mereka. Di Papua, konflik atas tanah adat semakin pelik ketika perusahaan pertambangan memasuki kawasan yang secara adat adalah wilayah komunal suku Mamberamo. Dalam konteks ini, negara tidak sekadar berhadapan dengan tuntutan legal, tetapi juga identitas budaya, kedaulatan pangan lokal, dan keberlanjutan ekosistem.
Kerangka hukum yang hanya berlandaskan legal formal pun tidak pernah benar-benar netral. Tafsiran sempit terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 — bahwa “tanah dikuasai oleh negara” — telah memperkuat narasi dominasi negara atas tanah, alih-alih tugas negara sebagai public trustee. Padahal, secara konstitusional, negara tidak diamanahkan untuk menjadi pemilik absolut, melainkan pengatur dan pengawas agar pemanfaatan tanah berorientasi pada kemakmuran rakyat dan penghormatan terhadap hak adat. Dalam banyak kasus, interpretasi teknokratis justru menjadikan negara sebagai pemilik efektif, yang kemudian memberikan ruang bagi konsesi, HGU, dan konversi kawasan, sementara komunitas adat tidak mendapat pengakuan riil atas hak asal-usulnya.
Modernisasi agraria melalui sertifikasi tanah, seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seharusnya menjadi jalan memperkuat kepastian hak, tetapi untuk masyarakat adat, model sertifikasi individual itu tidak selalu relevan. Struktur agraria komunal seperti customary tenure tidak sesuai dengan sistem pendaftaran berbasis kepemilikan pribadi. Banyak masyarakat adat mengelola tanah secara kolektif; batas wilayah bisa bersifat cair, berdasarkan aliran sungai, pohon keramat, atau warisan leluhur. Sistem sertifikasi yang mendorong pembatasan peta fisik, pengukuran individual, dan kepemilikan pribadi berpotensi menghancurkan struktur adat tersebut, karena tidak menghargai dimensi historis, sosial, dan spiritual tanah komunal.
Dalam konteks kritik ini, Ius Integrum Nusantara menawarkan paradigma yang jauh lebih integratif. Dimensi ius positivum — yaitu hukum nasional — tetap menjadi pondasi: UUPA 1960, peraturan pertanahan, undang-undang kehutanan, serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen operasional. Namun paradigma ini tidak berhenti di sana. Melalui ius constitutum–ius constituendum, ia menegaskan bahwa hukum yang ada (constitutum) memang memiliki kekurangan implementatif, dan menuntut reformasi (constituendum) yang menempatkan hak ulayat sebagai dasar kebijakan agraria. Agenda pembaruan ini mencakup mekanisme pendaftaran komunal, verifikasi historis-legal, konsultasi adat, dan larangan penetapan tanah negara tanpa persetujuan masyarakat.
Dimensi ius gentium menambahkan bobot moral dan legal internasional. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang diakui dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), serta doktrin non-regression, menegaskan bahwa negara tidak boleh mundur dalam pengakuan hak-hak adat. Putusan pengadilan internasional seperti Awas Tingni v. Nicaragua (Inter-American Court of Human Rights) menunjukkan bahwa penetapan kawasan tanpa persetujuan komunitas adat dapat menjadi pelanggaran hak asasi. Dalam kerangka ini, norma internasional tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi menjadi tolok ukur bagi legitimasi tindakan negara terhadap tanah adat.
Tak kalah penting adalah dimensi ius communitatis Nusantara, yaitu hukum adat sebagai living law yang melekat dalam komunitas. Tanah ulayat, tanah marga, petuanan, leuweung larangan, sasi — semua ini mencerminkan aturan tradisional lokal yang menyatukan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Di komunitas adat, keputusan tentang pemanfaatan tanah tidak diambil semata lewat registrasi formal tetapi melalui musyawarah adat, persetujuan kolektif, dan peran pemimpin adat. Ini adalah logika komunal yang berbeda jauh dari rezim individualistis: tanah bukan komoditas yang dipindahtangankan secara permanen, melainkan ruang keberlanjutan eksistensi kolektif dan spiritual.
Sejarah agraria Indonesia menunjukkan betapa mendesaknya pergeseran paradigma ini. Pada masa kolonial, sistem konsesi Belanda memberikan hak guna perusahaan besar, tetapi tidak mencabut hak adat. Setelah kemerdekaan, nasionalisasi aset kolonial terjadi, tetapi pengembalian hak atas tanah lokal sering diabaikan. UUPA 1960 mencoba menyatukan warisan hukum adat dengan hukum nasional, tetapi praktik administratif justru menciptakan dualisme baru: legalitas formal yang mengabaikan legitimasi komunal. Program modernisasi pertanahan seperti PTSL mempercepat sertifikasi, namun hasilnya banyak menyepelekan struktur adat dan realitas sosial lokal.
Konstitusi sesungguhnya memberikan pijakan kuat untuk harmonisasi agraria. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, selama keberadaannya masih nyata dalam masyarakat. Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa hak tradisional adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam kerangka public trusteeship, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa negara harus mengelola tanah untuk kemakmuran rakyat, bukan menyerapnya sebagai milik sepenuhnya. Dengan paradigma Ius Integrum Nusantara, tugas negara adalah memastikan bahwa hak komunal diakui, dilindungi, dan dipulihkan bila pernah terabaikan.
Contoh konkret menunjukkan konsekuensi kegagalan sistem hukum positif. Di Kalimantan Timur, konflik panjang antara masyarakat Dayak Kenyah dan perusahaan kayu menyoroti bagaimana dokumen perizinan sering diprioritaskan atas tradisi adat yang telah berlangsung ratusan tahun. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar menuntut pengakuan ulayat atas pulau-pulau kecil yang kini diklaim sebagai kawasan pariwisata. Kasus-kasus ini bukan hanya persoalan kompensasi ekonomi, tetapi konflik budaya dan identitas: ketika negara mengabaikan pengakuan atas hak kolektif, ia merenggut lebih dari lahan — ia merenggut rasa aman, kedaulatan lokal, dan keberlanjutan warisan leluhur.
Secara internasional, banyak negara telah menapaki reformasi agraria semacam ini. Di Brasil, pengakuan komunal atas wilayah quilombola telah memunculkan sertifikat kolektif yang menghormati masa lalu komunitas keturunan budak dan pemukim tradisional. Pengakuan ini bukan sekadar simbol, tetapi instrumen redistribusi dan restitusi historis. Di Kanada, aboriginal title diakui sebagai hak komunal yang tidak hilang kecuali komunitas secara sah melepaskannya. Doktrin honour of the Crown menuntut pemerintah Canada untuk bertindak dengan integritas dan itikad baik dalam menghormati hak-hak penduduk adat. Di Selandia Baru, Waitangi Tribunal bertindak sebagai lembaga quasi-yudisial yang menyelidiki pelanggaran masa lalu atas tanah Māori dan merekomendasikan pemulihan hak. Semua model ini memperlihatkan bahwa rekonsiliasi agraria mendalam adalah mungkin apabila hukum nasional membuka ruang bagi identitas adat dan norma internasional.
Paradigma Ius Integrum Nusantara bukan sekadar wacana akademik. Ia adalah kerangka transformasional untuk reformasi nyata: reformasi kebijakan, reformasi kelembagaan, dan reformasi cara berpikir. Dengan mengintegrasikan ius positivum, agenda ius constituendum, norma internasional (ius gentium), dan hukum adat lokal (ius communitatis), paradigma ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa agraria harus dilakukan dengan mekanisme restoratif dan partisipatif, bukan sekadar litigasi atau pembatalan administratif. Negara perlu menata ulang birokrasi pertanahan agar menjadi lembaga trustee yang memahami nilai sosial tanah, bukan hanya mesin sertifikasi dan konsesi.
Pada akhirnya, kritik terhadap kerangka hukum positif agraria bukan berarti menolak hukum nasional. Sebaliknya, ini adalah seruan untuk memperkaya hukum nasional dengan legitimasi lokal dan nilai universal. Jika negara benar-benar ingin menghormati konstitusi dan hak asasi masyarakat adat, ia harus mengakui bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi bagian dari jaring sosial-ekologis yang menyatukan manusia, alam, dan sejarah. Ius Integrum Nusantara menerima tantangan itu: mengatasi fragmentasi hukum dan menyulam kembali identitas agraria Indonesia dengan keadilan substantif, keberlanjutan, dan pengakuan atas warisan komunal.
Di ujung perjalanan ini, negara dihadapkan pada pilihan penting. Apakah ia akan terus mempertahankan paradigma yang menyederhanakan tanah menjadi komoditas, atau berani menegakkan paradigma hukum yang mempertahankan akar budaya, sejarah, dan kehormatan komunitas? Ius Integrum Nusantara menawarkan satu jalan: jalan integratif yang memulihkan hak ulayat, melindungi identitas masyarakat adat, dan menjadikan tanah sebagai medium keadilan sosial, bukan sekadar objek administratif. Jika pilihan ini diambil, maka agraria Indonesia bisa memasuki babak baru — di mana hukum menjadi alat pemulihan dan bukan instrumen dominasi. Itu adalah harapan besar bukan hanya bagi masyarakat adat, tetapi bagi seluruh bangsa yang merindukan keadilan nyata di atas tanah leluhurnya.
Mengakhiri Dualisme, Menegakkan Keadilan Substantif Agraria
Perjalanan panjang hukum pertanahan Indonesia menegaskan satu hal yang tak terbantahkan: konflik agraria bukan sekadar persoalan administratif, tetapi cerminan ketegangan antara legitimasi sosial, identitas budaya, dan kekuasaan negara. Era modernisasi pertanahan, meski menegaskan kepastian formal melalui sertifikasi massal, justru menyingkap kelemahan sistem hukum positif yang sering mengabaikan hak ulayat—hak asal-usul masyarakat adat yang telah hidup berabad-abad dalam relasi komunal dengan tanah.
Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, kita menemukan pijakan normatif dan praktis untuk mengatasi dualisme ini. Paradigma ini menegaskan bahwa hukum nasional (ius positivum) tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi reformasi (ius constituendum), norma internasional (ius gentium), dan pengetahuan lokal (ius communitatis). Keempat dimensi ini bersinergi membentuk sistem agraria yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga berkeadilan secara substantif, menghormati sejarah, budaya, dan keberlanjutan ekologi.
Kasus-kasus dari Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi menunjukkan bahwa ketidaksinkronan hukum formal dan realitas sosial menimbulkan sengketa berkepanjangan. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan keberlakuan hak ulayat, memberikan preseden penting: hak adat tidak bisa dikesampingkan oleh dokumen administratif atau kepemilikan negara semata. Di tingkat internasional, pelajaran dari pengakuan aboriginal title di Kanada atau sistem quilombola di Brasil menegaskan bahwa negara wajib menghormati hak kolektif dan melibatkan masyarakat adat secara partisipatif.
Lebih dari sekadar perangkat hukum, tanah ulayat adalah medium kehidupan—meliputi sistem pangan lokal, praktik konservasi ekologi seperti leuweung larangan, sasi, dan tana’ ulen, serta identitas budaya yang melekat pada komunitas. Mengabaikannya berarti merusak fondasi sosial-ekologis bangsa. Paradigma integratif menuntut negara bergerak dari legalisme formal menuju keadilan substantif, dari administrasi semata menuju legitimasi sosial, dari kepemilikan absolut menuju trusteeship yang bertanggung jawab.
Di penghujung refleksi ini, pesan yang muncul jelas: transformasi agraria Indonesia bukan sekadar soal penataan batas atau sertifikasi dokumen, tetapi tentang menyatukan hukum, budaya, dan sejarah dalam satu visi keadilan. Ius Integrum Nusantara bukan teori belaka; ia adalah panggilan aksi bagi negara, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama menegakkan hak ulayat, memulihkan keadilan historis, dan membangun tata kelola pertanahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat menutup bab lama dualisme agraria dan membuka lembaran baru, di mana hukum menjadi alat pemulihan, bukan instrumen dominasi, dan tanah kembali menjadi warisan yang menghormati manusia, alam, dan leluhur.
Menyatukan Sejarah, Hak Adat, dan Keadilan Agraria Masa Depan
Di hamparan alam Nusantara, tanah bukan sekadar ruang fisik. Ia adalah tisu sejarah dan akar identitas: ladang tempat leluhur bertani, hutan keramat yang dijaga generasi, dan kampung adat yang menyulam memori bersama. Namun dalam banyak kasus modern, keintiman itu terabaikan, digantikan oleh batas peta administratif dan keputusan birokrasi. Ketika Hak Guna Usaha (HGU) berakhir, negara kerap menancapkan cap “tanah negara” tanpa pernah merunut akar sejarahnya — akar yang tumbuh dari komunitas adat yang telah lama menetap. Inilah paradoks besar agraria Indonesia: di satu sisi ada legalitas formal, di sisi lain ada legitimasi sosial yang masih hidup. Paradigma hukum konvensional belum cukup untuk menjembatani jurang itu.
Selama beberapa dekade, hukum agraria Indonesia mengandalkan logika rule-based governance. Artinya, perhatian utama hukum adalah prosedur: pendaftaran tanah, pemberian hak atas tanah, penetapan batas, dan sertifikasi kepemilikan. Proses ini memberikan kepastian formal, tetapi sering menutup mata terhadap struktur sosial masyarakat adat, nilai kosmologis yang melekat pada tanah, dan warisan sejarah yang telah mengakar. Dalam sistem agraria adat, tanah bukan objek ekonomi murni, melainkan medium kehidupan kolektif dan relasi spiritual. Paradigma semata administratif gagal menghargai dimensi tersebut.
Melawan kegagalan itu, muncul gagasan Ius Integrum Nusantara, sebuah kerangka konseptual yang mencoba merumuskan ulang peran hukum agraria melalui empat dimensi hukum: Ius Positivum, Ius Constitutum–Ius Constituendum, Ius Gentium, dan Ius Communitatis Nusantara. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa tanah dan komunitas adat bukanlah entitas yang bisa disederhanakan menjadi catatan registrasi atau SK instansi pertanahan, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas kultural, kedaulatan pangan, dan keberlanjutan ekologis. Dengan paradigma ini, negara tidak lagi berfungsi sebagai pemilik tunggal (dominium), melainkan sebagai public trustee: pengelola amanah yang menjamin hak komunal, kesejahteraan kolektif, dan kelestarian alam.
Dari Konsesi Kolonial Hingga Konflik Modern
Sejarah agraria Indonesia tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonial. Di era Belanda, perusahaan-perusahaan kolonial memperoleh lahan melalui kontrak jangka panjang (contractus concessionarium) dengan penguasa lokal — sultan, kepala marga, atau komunitas adat. Namun, meski digunakan secara besar-besaran, konsesi itu tidak selalu menghapus hak asal-usul masyarakat adat. Banyak dokumen kolonial kemudian menyebutkan bahwa tanah tersebut hanya diberikan hak guna, bukan dialihkan kepemilikannya secara mutlak. Ketika masa konsesi habis, secara historis tanah semestinya kembali kepada komunitas asal, bukan langsung menjadi milik negara.
Saat kemerdekaan, nasionalisasi besar-besaran atas perkebunan kolonial memberi harapan pemulihan keadilan agraria. Namun kenyataan tak semudah harapan: nasionalisasi sering kali hanya menyasar aset fisik — modal dan infrastruktur — tanpa mengembalikan pengakuan penuh atas hak ulayat masyarakat adat. Lebih parah, ketika HGU diselesaikan atau tidak diperpanjang, tanah sering langsung ditetapkan sebagai tanah negara melalui SK Kepala BPN atau instansi pertanahan lokal, tanpa dialog mendalam dengan komunitas. Proses ini menghasilkan apa yang dalam literatur hukum disebut lawful dispossession — perampasan yang sah secara prosedur tetapi tidak adil secara historis.
Kasus di Sumatra Timur (eks-Deli) menjadi ilustrasi nyata. Ladang-ladang tembakau masa kolonial, dulunya bagian dari wilayah adat Melayu, dijadikan HGU oleh perusahaan Belanda. Ketika masa HGU berakhir, sebagian besar tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah negara tanpa proses verifikasi yang memadai terhadap hak ulayat masyarakat lokal. Praktik serupa juga terjadi di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Ketika komunitas adat berjuang menuntut pengembalian hak atas tanah leluhur mereka, perlawanan itu sering kali dibalas dengan kriminalisasi atau penolakan administratif. Konflik ini menggambarkan betapa negara masih melihat tanah sebagai inventaris pembangunan, bukan ruang kehidupan yang bernilai kultural dan ekologis.
Paradigma Ius Integrum Nusantara: Justice-based Governance
Revolusi pemikiran diperlukan: hukum agraria harus bergeser dari sekadar aturan prosedural menjadi instrumen keadilan sosial. Ius Integrum Nusantara mengusulkan paradigma justice-based governance, di mana keadilan substantif menjadi inti, bukan sekadar legal formalitas. Dalam konteks hak ulayat, tanah kembali dipandang sebagai milik komunitas, bukan sekadar objek ekonomi atau proyek pembangunan. Paradigma ini menekankan bahwa hak-hak minoritas, terutama masyarakat adat, harus diproteksi dengan mekanisme legal yang menghormati sejarah, kulturalitas, dan struktur sosial mereka.
Secara normatif, paradigma ini mensintesiskan empat dimensi hukum. Ius Positivum yakni hukum nasional — UUPA 1960, UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, dan peraturan kehutanan — tetap menjadi landasan operasional. Tetapi kekuatan teori tidak cukup jika kerangka itu tidak diiringi reformasi. Maka hadir dimensi Ius Constitutum–Ius Constituendum: kritik atas regulasi yang ada sekaligus agenda pembaruan struktural. Negara perlu merumuskan ulang mekanisme pengakuan hak ulayat melalui pemetaan partisipatif, registrasi komunal, evaluasi historis-legal, dan larangan penetapan tanah negara tanpa verifikasi adat.
Dimensi Ius Gentium, atau norma internasional, memperkuat legitimasi paradigma ini. Norma seperti Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) serta prinsip non-regression menegaskan bahwa hak adat tidak boleh dihapus melalui kebijakan mundur. Negara yang mengklaim otoritas penuh tanpa menghormati persetujuan komunal melanggar prinsip universal pengakuan masyarakat adat. Selain itu, nilai seperti intergenerational equity dan precautionary principle dari hukum lingkungan global mendesak negara untuk menghormati kelestarian ekologis ketika merencanakan redistribusi atau konversi lahan.
Namun dimensi yang paling khas dalam paradigma ini adalah Ius Communitatis Nusantara. Hukum adat lokal bukan sekadar simbol nilai lama. Ia adalah sistem norma hidup (living law) yang menjadi sumber kearifan agraria komunal. Struktur adat internal — pemimpin adat, mekanisme musyawarah, norma konsensus — harus dihormati sebagai bagian dari proses legal nasional. Dalam banyak komunitas, batas lahan tidak hanya ditentukan oleh peta, tetapi oleh cerita leluhur, batas alam seperti sungai atau batu besar, dan persetujuan generasi. Pengakuan hak ulayat dalam paradigma ini berarti menghormati mekanisme adat dan menjadikannya bagian struktur legal yang sah.
Dua Pilar Praktis: Akses & Fungsi Sosial-Ekologis
Paradigma Ius Integrum Nusantara juga diterjemahkan ke dalam dua pilar praktis yang menyentuh kehidupan sehari-hari: akses (distribution) dan fungsi sosial-ekologis. Pilar akses menyoroti keadilan dalam pembagian tanah: bukan hanya pembagian formal, tetapi pemulihan hak historis masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. Tanah adat yang hilang karena konsesi kolonial atau HGU harus diakui kembali sebagai bagian dari struktur agraria kolektif, bukan hanya diukur sebagai aset statik. Konsep access justice menjamin bahwa komunitas yang kehilangan tanah leluhur mereka mendapat akses nyata — bukan sekadar sertifikat kosong — melalui mekanisme restitusi, redistribusi, dan rekognisi komunal.
Di sisi lain, fungsi sosial-ekologis tanah tidak dapat diabaikan. Dalam paradigma ini, tanah adat bukan diperlakukan sebagai komoditas semata, tetapi sebagai penjaga ekologi dan pemelihara identitas kultural. Praktik lokal seperti leuweung larangan di Jawa Barat, sasi di Maluku, atau rotasi ladang tradisional di Kalimantan, menggambarkan bagaimana masyarakat adat secara alamiah menjaga keberlanjutan lahan mereka jauh sebelum regulasi modern ada. Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan menyinergikan praktik seperti itu dengan regulasi tata ruang nasional. Tak hanya itu, norma internasional melalui intergenerational equity menuntut agar keputusan pembangunan tidak merusak kemampuan alam untuk menopang generasi masa depan.
Perlindungan dan Resolusi Konflik: Jalan Hibrida dan Restoratif
Konflik tanah adat memerlukan solusi yang lebih dari sekadar pembatalan SK atau litigasi di pengadilan. Dalam paradigma ini, penyelesaian harus bersifat hibrida dan restoratif, yaitu:
Pertama, bukti dalam sengketa harus melampaui dokumen administratif. Historical communal evidence — testimonium oral dari tetua, arsip kontrak kolonial, peta tradisional, dan catatan pemanfaatan — diakui sebagai pilihan bukti yang sah. Praktik ini mencerminkan model di mana pengadilan modern belajar dari pengalaman internasional, seperti Aboriginal Title di Kanada di mana Mahkamah Agung menerima bukti lisan dan adat sebagai bukti prima.
Kedua, proses penyelesaian sengketa jangan hanya melalui jalur peradilan formal, tetapi melalui panel adjudikatif hibrida. Panel ini akan menyatukan hakim, ahli adat, antropolog, ahli agraria, dan perwakilan komunitas. Model ini mencerminkan pendekatan lembaga seperti Waitangi Tribunal di Selandia Baru atau Truth and Reconciliation Commission di negara lain, di mana aspek historis dan kultural diangkat bersama dalam upaya rekonsiliasi.
Ketiga, hasil penyelesaian harus bersifat restoratif. Artinya, pemulihan hak tidak hanya berbentuk restitusi tanah, tetapi juga rehabilitasi ekologi, kompensasi untuk hilangnya akses, pemulihan identitas budaya, dan jaminan perlindungan jangka panjang. Restorative remedy ini lebih dari kompensasi finansial — ia adalah wujud keadilan substantif, di mana trauma historis diakui dan diperbaiki dalam perspektif masa depan.
Keempat, syarat Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) wajib dijadikan pintu awal setiap proses perizinan atau pengalihan tanah adat. FPIC bukan sekadar “sosialisasi”, melainkan persetujuan kolektif yang sungguh-sungguh diperoleh sebelum keputusan dibuat. Tanpa FPIC, tindakan administratif negara berisiko menjadi agresi legal yang melanggar hak asasi masyarakat adat.
Belajar dari Dunia: Perspektif Komparatif
Pengalaman internasional memberikan pelajaran kuat bagi Indonesia. Di Brasil, komunitas quilombola memperoleh pengakuan atas tanah historis melalui sertifikat kolektif, tanpa harus membuktikan kepemilikan per individu. Di Kanada, putusan Delgamuukw v. British Columbia memerintahkan negara untuk menghormati Aboriginal Title sebagai hak kolektif yang tak bisa dihapus kecuali melalui pelepasan sah, dan memperkuat doktrin honour of the Crown. Di Afrika Selatan, Communal Land Rights Act menjadi instrumen untuk restitusi tanah pasca-apartheid dan memberikan ruang bagi redistribusi komunal. Di Selandia Baru, Treaty of Waitangi dan lembaga Waitangi Tribunal memberikan mekanisme ijazah rekonsiliasi hak tanah suku Māori dengan negara melalui proses investigatif jangka panjang. Model-model semacam ini menunjukkan bahwa pengakuan tanah adat bukan hanya isu lokal, tetapi bagian dari gelombang keadilan agraria global — dan Indonesia bisa merumuskan adaptasi yang sesuai dengan konteks sosial-kulturalnya.
Menuju Reformasi Kelembagaan: Menegakkan Paradigma Integratif
Paradigma Ius Integrum Nusantara menuntut reformasi kelembagaan agar gagasan normatif dapat menjadi praktik nyata. Birokrasi pertanahan — khususnya ATR/BPN — harus diubah dari lembaga administratif menjadi lembaga trustee publik yang menghormati hak-hak komunal. Harus ada unit khusus untuk hak ulayat, peta adat diintegrasikan dalam sistem kadas nasional, dan verifikasi adat menjadi prasyarat sebelum SK tanah negara dikeluarkan. Komunitas adat pun perlu diakui sebagai co-regulator dengan kewenangan menilai investasi, menetapkan tata ruang lokal, dan menegakkan norma adat.
Lebih jauh, dibutuhkan lembaga permanen yang menangani sengketa agraria dengan pendekatan historis dan restitutif. Tribunal agraria independen atau komisi kebenaran agraria dapat menjadi arena dialog hukum, investigasi, dan pemulihan hak. Lembaga semacam ini akan menjadi simbol nyata bahwa negara serius membangun sistem agraria yang inklusif dan adil.
Paradigma Teoretik Baru: Memperbarui Fondasi Hukum Agraria
Secara teoretik, paradigma ini membuka ruang diskusi baru. Ia menantang dualisme lama antara hukum positif dan hukum adat, menempatkan hukum adat sebagai sumber norma (source of norms) yang sejajar dengan peraturan tertulis. Paradigma ini menyintesiskan lima prinsip keadilan: legalitas administratif, legitimasi budaya, keadilan ekologis, keadilan inter-generasi, dan keadilan historis — menciptakan sebuah transformative law yang tidak hanya mengatur, tetapi merekonstruksi relasi kuasa atas tanah.
Secara konstitusional, paradigma ini menghidupkan kembali semangat pluralisme hukum. Konstitusi Indonesia memang mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi tanpa mekanisme operasional yang kuat, pengakuan itu hanya wacana. Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa pluralisme itu nyata dan perlu diwujudkan melalui kebijakan, registrasi komunal, dan lembaga penyelesaian sengketa yang menghormati adat.
Refleksi dan Harapan
Kilasan masalah agraria Indonesia — dari konflik HGU hingga pengabaian hak ulayat — menunjukkan bahwa reforma pertanahan bukan sekadar urusan teknis, tetapi ujian nilai. Negara harus memilih: apakah akan terus beroperasi sebagai birokrasi yang mengelola tanah, atau sebagai pengelola amanah yang menghormati sejarah dan komunitas lokal. Ius Integrum Nusantara memberikan jalur teoretik sekaligus operasional: rekognisi hak, redistribusi keadilan, pemeliharaan ekologi, dan perlindungan komunitas adat sebagai satu kesatuan paradigma.
Jika diterima dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, paradigma ini bisa menjadi fondasi sistem agraria modern yang lebih adil, manusiawi, dan berakar. Tanah tidak lagi menjadi obyek konflik semata, tetapi simbol rekonsiliasi antara sejarah dan masa depan, antara negara dan masyarakat adat, antara pembangunan dan identitas budaya. Inilah momen bagi Indonesia untuk menegaskan kembali: keadilan agraria bukan mimpi kosong, tetapi panggilan konstitusional dan kemanusiaan.
Menutup Babak, Membuka Jalan Reformasi Agraria
Menutup telaah panjang mengenai Ius Integrum Nusantara, kita diingatkan bahwa perjuangan hukum agraria Indonesia bukan sekadar soal sertifikat, batas peta, atau kepemilikan formal. Ini adalah upaya memulihkan keseimbangan antara negara, komunitas adat, dan ekologi yang menopang kehidupan kolektif. Dari konflik tanah bekas HGU hingga sengketa wilayah adat, terlihat jelas bahwa prosedur administratif tanpa pengakuan historis dan budaya hanya menciptakan legitimasi semu—legalitas yang tampak sah di atas kertas, tetapi kehilangan akar keadilan substantif.
Paradigma justice-based governance yang diusung oleh Ius Integrum Nusantara menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadi pemilik tunggal yang mendikte, melainkan pengelola amanah (public trustee) yang melindungi hak-hak komunal, keberlanjutan ekologis, dan identitas budaya. Rekognisi hak ulayat, redistribusi keadilan, pemeliharaan fungsi sosial-ekologis tanah, serta mekanisme resolusi konflik restoratif menjadi pilar utama yang menjembatani gap antara hukum formal, norma internasional, dan hukum adat.
Pengalaman komparatif dari Kanada, Brasil, Afrika Selatan, hingga Selandia Baru menegaskan satu hal: hukum yang menghormati masyarakat adat bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan konstitusional. Bukti lisan, arsip historis, peta tradisional, dan konsensus komunitas menjadi bagian dari bukti sah, dan FPIC bukan ritual formal, tetapi hak kolektif yang tidak bisa dinegosiasikan.
Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa Ius Integrum Nusantara bukan sekadar konsep akademik, tetapi kerangka operasional menuju reformasi agraria yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada identitas hukum Nusantara. Dengan mekanisme hibrida yang menggabungkan negara dan adat, dengan restorasi hak historis dan ekologis, serta dengan lembaga permanen yang independen, Indonesia berpotensi membangun sistem pertanahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, manusiawi, dan demokratis.
Dari hasil kajian ini, tersimpan pesan penting: keadilan agraria adalah perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, keberanian, dan integritas. Tanah bukan sekadar aset; ia adalah tumpuan kehidupan, memori kolektif, dan identitas yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Dengan Ius Integrum Nusantara, reformasi agraria dapat menjadi jembatan antara sejarah, hukum, dan keadilan, membuka jalan bagi masa depan di mana hukum tidak hanya mengatur, tetapi benar-benar menegakkan keadilan.
Membangun Paradigma Agraria Baru demi Keberlanjutan dan Keadilan
Di balik gemerincing mesin ekspansi perkebunan dan pembangunan kawasan strategis nasional, ada suara lantang yang kerap tenggelam: suara tanah yang bukan objek biasa, melainkan warisan hidup. Di banyak kampung adat, ketika pohon ditebang dan ladang diubah fungsi, masyarakat bukan kehilangan sekadar lahan—mereka kehilangan identitas, memori leluhur, dan jaminan masa depan. Konflik tanah adat yang terus muncul bukan sekadar perseteruan administratif, tetapi pertarungan nilai: antara negara sebagai otoritas birokrasi dan komunitas adat yang menganggap tanah sebagai bagian dari dirinya.
Dalam kerangka pertanahan nasional, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebenarnya menawarkan pijakan awal yang mengakui dualisme kepemilikan: tanah negara dan tanah adat. Namun praktik berulang menunjukkan bahwa interpretasi semata legalitas belum cukup. Negara sering bertindak seperti pemilik absolut, mengabaikan sejarah dan relasi kultural masyarakat adat yang telah lama menginduk pada customary tenure. Logika demikian menciptakan administrative absolutism, di mana tanah lebih mudah ditetapkan sebagai milik negara daripada diakui sebagai hak komunal.
Ketegangan ini menjadi nyata, misalnya, di bekas konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang melewati masa izin. Di Sumatra Timur, wilayah bekas HGU PTPN di eks-Deli menyimpan cerita lama: tanah yang dahulu dikelola oleh perusahaan, sejatinya berasal dari wilayah adat yang diserahkan melalui contractus concessionarium, bukan sebidang “tanah kosong negara”. Setelah konsesi berakhir, negara menempatkan kembali tanah tersebut sebagai “tanah negara” melalui keputusan administratif tanpa menguji eksistensi hak ulayat yang secara historis tak pernah sirna. Proses ini memperlihatkan wajah lawful dispossession—perampasan yang tampak sah secara prosedur, tetapi tidak adil secara historis.
Selanjutnya, dalam konteks inilah gagasan Ius Integrum Nusantara muncul: sebuah paradigma hukum agraria yang tidak sekadar normatif, tetapi juga historis, ekologis, dan konstitusional. Paradigma ini menyatukan empat dimensi hukum—ius positivum (hukum nasional), ius constitutum–ius constituendum (reformasi regulasi), ius gentium (norma internasional), dan ius communitatis Nusantara (hukum adat dan nilai lokal)—ke dalam satu sistem konseptual yang mampu menjembatani fragmentasi kelembagaan dan pluralitas norma.
Dengan Ius Integrum Nusantara, negara tidak lagi dipandang sebagai penguasa tunggal yang memutuskan status tanah secara sepihak, melainkan sebagai public trustee—pemegang amanah yang berkewajiban menjaga tanah sebagai sumber kehidupan bersama. Konsep ini sejalan dengan interpretasi konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan penguasaan negara dalam kerangka amanah, bukan kepemilikan mutlak (dominium). Negara tetap memiliki kewenangan, tetapi diikat oleh empat batasan utama: identitas sejarah komunitas adat (historical embeddedness), keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan hak asasi manusia.
Selain itu, sejarah agraria Indonesia menunjukkan urgensi rekontekstualisasi seperti ini. Pada masa kolonial, Belanda memberi konsesi besar melalui kontrak jangka panjang, namun tidak pernah menghapus hak asal-usul masyarakat adat. Setelah kemerdekaan, nasionalisasi konsesi tidak diikuti dengan rekognisi penuh terhadap hak ulayat, dan ketika masa HGU selesai, banyak tanah kembali menetapkan sebagai tanah negara tanpa kajian sosial-historis. Ketidakadilan struktural ini dibenarkan oleh kerangka administratif semata, sementara suara adat dan komunitas lokal nyaris tak terdengar dalam pengambilan keputusan.
Krisis legitimasi ini tidak hanya bersifat lokal: ia disertai dengan kerugian sosial dan ekologis yang dalam. Komunitas adat menghadapi putusnya akses terhadap ladang warisan, hilangnya kontrol atas sistem pangan tradisional, dan erosi daya hidup kolektif. Kebijakan pertanahan yang mengabaikan nilai komunal ini memperparah jurang ketimpangan agraria dan mengancam kedaulatan pangan di wilayah adat, di mana keanekaragaman pertanian dan pengetahuan lokal selama ini menjadi basis ketahanan masyarakat.
Ius Integrum Nusantara mengajukan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat hibrida, yaitu: Pertama, dalam hal pembuktian hak adat, paradigma ini mengakui historical communal evidence: proses litigasi harus membuka ruang bagi testimonium orale tetua adat, arsip kolonial, peta tradisional, dan bukti antropologis pemanfaatan tanah. Model semacam ini mirip dengan praktik Kanada atau Australia, di mana pengadilan adat atau tribunal memiliki kapasitas menerima bukti non-dokumen sebagai bagian dari verifikasi hak.
Kedua, mekanisme adjudikatif perlu ditata ulang: panel hibrida yang melibatkan hakim, ahli adat, antropolog, ahli agraria, serta perwakilan komunitas adat dapat menjadi lembaga permanen yang menilai sengketa tidak hanya dari sudut teknis legal, tetapi juga dari sudut sosial dan budaya. Model ini mencontoh lembaga semacam Waitangi Tribunal di Selandia Baru atau Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan.
Ketiga, paradigma integratif menegaskan perlunya restorative legal remedy. Putusan pengadilan tidak cukup jika hanya menyatakan batal SK atau administrasi, tetapi harus menyertakan pemulihan hak ulayat: pengembalian tanah, pemulihan ekosistem, kompensasi bagi komunitas yang kehilangan akses, dan mekanisme jangka panjang untuk melindungi legitimasi komunitas adat.
Keempat, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menjadi syarat mutlak dalam setiap perencanaan investasi atau pengalihan tanah adat. FPIC lebih dari sekadar konsultasi simbolis; ia adalah hak veto kolektif komunitas adat agar keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka benar-benar sah dan adil. Tanpa FPIC yang menghormati nilai lokal, keputusan administratif hanya akan memperdalam alienasi dan konflik.
Reformasi kelembagaan pertanahan menjadi bagian integral dari penerapan paradigma ini, maka Kementerian ATR/BPN harus bertransformasi dari lembaga administrasi pertanahan menjadi institusi public trustee yang lebih peka terhadap hak adat. Unit kerja khusus untuk hak ulayat, integrasi peta adat ke dalam sistem Kadas terpusat, serta larangan menetapkan tanah negara tanpa verifikasi adat adalah langkah awal yang krusial. Selain itu, penguatan peran lembaga adat sebagai co-regulator menjadi esensial: komunitas adat harus bisa menilai rencana investasi, menetapkan tata ruang lokal, memberi persetujuan atau menolak proposal proyek, serta menetapkan sanksi adat jika terjadi pelanggaran.
Pendirian tribunal agraria independen juga menjadi keniscayaan, dan tribunal semacam Tribunal Agraria Nasional, atau Komisi Kebenaran Agraria, harus dirancang sebagai lembaga permanen yang berfungsi sebagai forum investigatif dan peradilan restorative, bukan peradilan administratif biasa. Dalam lembaga ini, pengakuan historis dan rekonsiliasi harus menjadi bagian dari proses adjudikatif.
Secara teoretik, paradigma Ius Integrum Nusantara membawa transformasi besar dalam pemikiran hukum agraria. Ia merevisi pemisahan tajam antara hukum positif dan hukum adat dengan menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar tradisi yang dipertahankan, melainkan source of norms yang sah. Dalam kerangka ini, lima prinsip keadilan digabung dalam satu paradigma: legalitas administratif, legitimasi budaya, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, dan keadilan historis. Semua unsur ini menjalin sebuah transformative law, hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi merestrukturisasi relasi kuasa atas tanah.
Paradigma ini juga memperkokoh konstitusionalisme multikultural Indonesia. Konstitusi 1945 sudah membuka ruang untuk pluralisme hukum; Ius Integrum Nusantara memperjelas operasionalisasi pluralisme tersebut melalui mekanisme konkret. Hak ulayat tidak lagi dipandang sebagai keanekaragaman sisi pinggiran, tetapi sebagai pilar keadilan agraria yang setara dengan hak atas tanah negara. Dalam kerangka ini, konsep communal sovereignty dihidupkan kembali: masyarakat adat bukan subjek subordinat, tetapi pemegang kedaulatan atas tanah komunalnya.
Implementasi paradigma ini tentu tidak mudah. Butuh keberanian politik, reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas masyarakat adat, serta kesediaan negara untuk membiayai pemetaan adat dan restitusi historis. Tapi tantangan tersebut bukan alasan menunda perubahan, melainkan urgensi. Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan jaminan keberlanjutan budaya, pangan, dan identitas bangsa. Jika tidak diubah, status quo legal-administratif hanya akan memperbesar jurang ketimpangan agraria dan menegakkan dominasi formal yang mengabaikan makna tanah yang lebih dalam.
Selanjutnya dengan Ius Integrum Nusantara, maka diharapkan Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem agraria yang adil dan berakar. Sebuah sistem di mana negara bukan penafsir mutlak, tetapi pelindung amanah generasi, dan masyarakat adat bukan objek kebijakan, tetapi mitra pengelola tanah. Dengan paradigma ini, konflik agraria dapat dijawab bukan hanya dengan putusan pengadilan, melainkan dengan pemulihan struktural: pengakuan historis, keadilan sosial, dan rasa hormat atas keberagaman kultural Nusantara. Jika negara sungguh menaruh keadilan sebagai dasar pembangunan, maka sudah waktunya menggabungkan norma, nilai, dan identitas dalam satu visi agraria baru—visi yang menghormati akar masa lalu sekaligus membuka jalan bagi masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menutup Siklus Agraria dengan Paradigma Integratif
Setelah menelusuri perjalanan panjang hukum agraria Indonesia—dari kontrak kolonial concessionarium, konsesi perusahaan, hingga peraturan negara pascakemerdekaan—satu hal menjadi jelas: tanah bukan sekadar objek administratif, tetapi entitas hidup yang memuat sejarah, identitas, dan relasi sosial-ekologis. Konflik yang muncul di bekas Hak Guna Usaha, sengketa batas wilayah adat, hingga kriminalisasi komunitas lokal bukan kegagalan individu atau institusi semata; ia adalah gejala sistemik dari kerangka hukum yang memisahkan legalitas formal dari legitimasi historis dan budaya.
Di sinilah relevansi Ius Integrum Nusantara menjadi krusial. Paradigma ini menutup celah antara norma hukum, praktik administratif, dan hak komunal, menempatkan negara bukan sebagai penguasa absolut, tetapi public trustee yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pembangunan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Dalam epilog ini, kita menyadari bahwa transformasi agraria bukan soal mengganti regulasi, tetapi mengubah cara pandang terhadap tanah dan masyarakat yang hidup di atasnya.
Kasus-kasus historis menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat bukan sekadar formalitas, melainkan pemulihan communal sovereignty yang telah lama terabaikan. Pengembalian tanah bekas HGU kepada komunitas adat, penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent, serta pembuktian berbasis sejarah dan budaya (historical communal evidence) adalah langkah konkret untuk menegakkan keadilan substantif. Lembaga permanen, seperti tribunal agraria independen, berpotensi menjadi mekanisme restoratif yang menyeimbangkan kepentingan negara, investor, dan komunitas lokal, seraya melestarikan nilai-nilai budaya dan ekologis.
Secara teoretik, paradigma ini juga memperkaya kajian hukum agraria. Integrasi ius positivum, ius constitutum–ius constituendum, ius gentium, dan ius communitatis Nusantara tidak hanya menawarkan kerangka analisis konseptual, tetapi juga instrumen operasional bagi kebijakan dan praktik hukum. Ia merevisi pemahaman dualistik antara hukum adat dan hukum nasional, menempatkan hak ulayat sebagai pilar setara dalam sistem hukum, sekaligus menegaskan prinsip multikulturalisme konstitusional Indonesia.
Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi agraria Indonesia bergantung pada keberanian politik dan kelembagaan untuk menerapkan paradigma integratif. Jika negara mampu menegakkan transformative law yang mengakui sejarah, menghormati komunitas adat, dan menjamin keberlanjutan ekologis, tanah tidak hanya menjadi basis ekonomi atau alat birokrasi, tetapi fondasi keadilan, identitas, dan kedaulatan masyarakat Nusantara.
Dengan demikian, hasil kajian ini bukan sekadar penutup narasi, tetapi seruan reflektif: membangun sistem agraria yang adil adalah tanggung jawab kolektif—antara negara, masyarakat adat, akademisi, dan publik—agar tanah di Indonesia kembali menjadi ruang kehidupan yang manusiawi, berkelanjutan, dan berakar pada identitas hukum Nusantara.
Menafsir Ulang Tanah dan Keadilan
Di banyak pelosok Nusantara, tanah masih diperlakukan sebagai tubuh sejarah. Ia bukan sekadar bidang yang digambar di peta, atau deretan koordinat dalam sertifikat, tetapi ruang hidup yang menyimpan ingatan, identitas, dan masa depan. Dalam setiap tapak ulayat, tersimpan narasi yang lebih tua daripada republik ini sendiri. Ketika negara atau korporasi menancapkan palu keputusan atas wilayah yang telah dijaga leluhur berabad-abad lamanya, yang dipertaruhkan bukan hanya akses, melainkan keberlanjutan suatu peradaban. Di titik inilah ketegangan agraria Indonesia terus muncul—antara hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang dibakukan negara, antara customary tenure yang diwariskan generasi dan bureaucratic formalism yang sering kali tak memahami lanskap sosial yang dilampauinya.
Dalam pusaran inilah muncul kebutuhan untuk membangun cara pandang baru terhadap hukum pertanahan. Selama puluhan tahun, diskursus agraria cenderung dipisahkan dalam kotak-kotak yang kaku: hukum positif di satu sisi, antropologi hukum di sisi lain, dan analisis ekonomi tanah di ruang berbeda. Pemisahan epistemik ini membuat banyak kebijakan agraria kehilangan akar dan kepekaan sosial, sehingga konflik atas tanah ulayat terus berulang.
Pendekatan hukum yang hanya bertumpu pada Ius Positivum tidak pernah benar-benar memadai untuk menjawab kompleksitas relasi tanah dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Di sinilah gagasan Ius Integrum Nusantara mengambil peran, menawarkan kerangka yang lebih utuh untuk memahami tanah, kuasa negara, dan hak masyarakat adat dalam satu tarikan napas yang komprehensif.
Paradigma ini tidak hanya menyatukan empat tatanan hukum—Ius Positivum, Ius Constitutum–Ius Constituendum, Ius Gentium, dan Ius Communitatis Nusantara—melainkan juga memulihkan kembali dimensi historis, ekologis, dan komunal yang kerap hilang akibat pendekatan hukum yang terlalu administratif. Melalui kerangka ini, tanah tidak lagi dipandang sebagai unit registrasi, melainkan entitas multidimensi yang tak dapat dipisahkan dari ingatan kolektif dan kedaulatan budaya komunitas adat. Dengan perspektif semacam ini, frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 justru tidak memusatkan kekuasaan pada negara sebagai pemilik dominium, tetapi menempatkan negara sebagai public trustee, pemegang amanah yang harus menghormati batas konstitusional berupa hak-hak masyarakat adat dan fungsi sosial-ekologis tanah.
Peralihan cara pandang ini penting karena sejarah agraria Indonesia sarat dengan reduksi makna tanah. Kolonialisme memulai itu melalui politik domeinverklaring, yang mengklaim hampir seluruh tanah tak bertuan sebagai milik negara jajahan. Setelah kemerdekaan, logika yang mirip sering berlanjut dalam cara aparatur negara menafsirkan tanah yang habis masa HGU-nya sebagai otomatis menjadi tanah negara. Padahal banyak HGU awalnya diterbitkan di atas tanah adat yang diberikan secara contractus concessionarium, bukan tanah negara. Di sinilah delegitimasi hak ulayat berulang tanpa pernah benar-benar dipertanyakan secara historis dan normatif. Padahal, hak ulayat—dengan karakter komunal, kesinambungan antar generasi, dan basis kosmologisnya—tidak pernah terputus oleh perubahan rezim hukum, sebagaimana berkali-kali ditegaskan dalam literatur hukum adat maupun putusan Mahkamah Konstitusi.
Rekontekstualisasi hak ulayat menjadi kunci untuk memulihkan keadilan agraria. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, tanah ulayat menduduki posisi yang kuat bukan hanya secara moral, tetapi secara hukum. Pengakuan hak ulayat tidak mensyaratkan surat keputusan pemerintah; kehadirannya ex lege, melekat dalam komunitas adat itu sendiri. Negara justru berkewajiban membuktikan ketiadaan hak ulayat sebelum menyatakan suatu hamparan sebagai tanah negara, mengikuti asas presumption of indigenous rights yang berlaku luas dalam Ius Gentium. Prinsip free, prior, and informed consent pun menjadi batu ujian legitimasi setiap kebijakan yang menyentuh tanah adat, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang sekadar diberi tahu, tetapi pengambil keputusan utama atas wilayahnya.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sengketa tanah adat selama empat dekade terakhir memperlihatkan pola yang konsisten: negara lebih percaya pada dokumen administratif dibanding sejarah komunitas. Administrasi pertanahan sering kali beroperasi dalam logika administrativisme, seolah ketiadaan sertifikat adalah bukti ketiadaan hak. Negara pun secara sepihak memonopoli tafsir atas istilah “tanah negara”, padahal dalam teori public trusteeship, negara tidak memiliki tanah; ia hanya mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, masyarakat adat mudah sekali dikriminalisasi atas praktik pengelolaan tanah yang mereka jalankan secara turun-temurun. Konflik yang seharusnya dilihat sebagai persoalan struktural justru dibingkai sebagai pelanggaran hukum oleh warga yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
Kerangka Ius Integrum Nusantara tidak hanya mengkritik kondisi ini, tetapi menawarkan jalan keluar. Pendekatan justice-based menggantikan rule-based formalism, sehingga penyelesaian sengketa tidak berhenti pada legalitas administratif, melainkan bergerak menuju pemulihan struktur agraria. Tanah dipahami sebagai relasi sosial-ekologis yang menghubungkan identitas komunitas, sistem pangan, ruang hidup, dan kedaulatan budaya. Negara tidak lagi ditempatkan sebagai penafsir tunggal, melainkan sebagai pelindung yang wajib memastikan setiap tindakan administratifnya menghormati hak-hak adat dan nilai konstitusional. Karena itu, sistem agraria modern harus berbasis pluralisme hukum: hukum adat, hukum nasional, dan norma internasional berjalan saling mengisi, bukan saling meniadakan.
Dari sinilah reformasi agraria yang sejati dapat dibayangkan. Tanpa pengakuan menyeluruh terhadap masyarakat adat, tanpa reformasi birokrasi pertanahan, dan tanpa mekanisme adjudikasi agraria yang independen, keadilan hanya akan menjadi jargon administratif. Negara perlu membangun institusi yang mampu memahami sejarah lokal, menilai bukti komunal secara proporsional, dan memastikan bahwa prinsip FPIC tidak sekadar menjadi hiasan peraturan, tetapi benar-benar hidup dalam proses perizinan. Tribunal agraria nasional menjadi kebutuhan mendesak agar sengketa yang menyangkut tanah adat tidak lagi diadili oleh lembaga yang tidak dibentuk untuk memahami kompleksitas historis dan komunal tersebut. Restitusi tanah bekas HGU pun harus menjadi agenda penyembuhan struktural yang menghadirkan kembali keadilan, bukan sekadar penutupan konflik.
Dengan demikian, dari seluruh hasil pembahasan ini bermuara pada satu gagasan besar: masa depan agraria Indonesia ditentukan oleh keberanian untuk mengakui pluralitas hukum yang telah ada sejak sebelum republik ini berdiri. Tanah tidak bisa ditundukkan sepenuhnya pada logika administratif. Ia menuntut penghormatan, pengetahuan sejarah, dan keadilan yang berakar pada pengalaman konkret masyarakat. Ius Integrum Nusantara menawarkan kerangka itu—sebuah paradigma yang menjembatani hukum positif, kearifan lokal, dan norma global, sehingga tanah dapat kembali diperlakukan sebagai ruang kehidupan yang adil bagi semua warga. Jika negara ingin mengakhiri lingkaran panjang konflik agraria, maka langkah pertama adalah menempatkan tanah bukan di bawah kekuasaan negara, melainkan dalam amanah konstitusional yang mewajibkan perlindungan terhadap mereka yang telah menjaganya jauh sebelum hukum nasional dibuat. Tanah, dalam pengertian itulah, menjadi sumber bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga keadilan, keberlanjutan, dan martabat bangsa.
Masa Depan Agraria Indonesia
Pada akhirnya, seluruh perdebatan tentang tanah—baik yang menyangkut hak ulayat, kewenangan negara, maupun kepastian hukum—bermuara pada satu pertanyaan mendasar: kepada siapa masa depan agraria Indonesia harus berpihak? Jika tanah terus diperlakukan sebagai objek administratif yang netral, maka ketidakadilan akan berulang, karena struktur historis yang timpang tidak pernah dinetralkan oleh prosedur. Namun bila tanah dipahami sebagai ruang kehidupan yang lahir dari sejarah, kebudayaan, dan relasi ekologis, maka hukum dapat kembali menemukan alasan keberadaannya: melindungi yang rapuh, menyeimbangkan kekuasaan, dan memastikan masa depan yang layak bagi generasi berikutnya.
Ius Integrum Nusantara menawarkan pijakan untuk keluar dari kebuntuan normatif ini. Dengan menyatukan ius positivum yang memberi kerangka legal, ius gentium yang menghadirkan standar global, ius communitatis yang menghidupkan hukum adat, dan ius constituendum yang menuntun arah pembaruan, paradigma ini menempatkan hukum agraria bukan sebagai alat administratif, melainkan sebagai sarana penyembuhan struktur sosial. Ia mengembalikan negara pada peran trustee yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebagai pemilik tunggal sumber daya.
Kajian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan hukum agraria tidak ditentukan oleh kemampuan negara menambah aturan, tetapi oleh keberanian untuk merombak cara pandang. Selama negara terus bergantung pada legalitas yang terpisah dari kenyataan sosial, konflik agraria akan tetap menjadi luka terbuka di tubuh republik. Tetapi jika negara bersedia menegakkan keadilan yang bertumpu pada sejarah, ekologi, dan martabat masyarakat adat, maka tanah dapat kembali menjadi ruang hidup yang menyatukan—bukan memisahkan—anak bangsa.
Di persimpangan inilah Indonesia berdiri hari ini. Pilihan yang diambil negara akan menentukan apakah tanah tetap menjadi sumber konflik, atau justru berubah menjadi fondasi keadilan sosial yang selama ini hanya dijanjikan oleh konstitusi.
Paradigma Ius Integrum Nusantara bukan jawaban akhir, tetapi tawaran jalan pulang menuju tata agraria yang tidak lagi menempatkan warga sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, sejarah, dan masa depan. Dan selama negara mengingat bahwa tugasnya adalah menjaga amanah itu, harapan untuk keadilan agraria tidak akan pernah sepenuhnya padam.
Rekonstruksi Legitimasi Hak Ulayat Deli dalam Paradigma Hukum Agraria Multidimensi
Sejarah dan Dimensi Tanah Adat Deli
Sengketa tanah adat Deli bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan bagaimana hukum agraria Indonesia masih bergumul dengan warisan kolonial dan reduksi makna tanah. Sejak abad ke-19, wilayah antara Sungai Wampu hingga Sungai Ular tercatat dalam peta resmi 1869 dan 1924 sebagai kawasan politik dan kebudayaan masyarakat Deli. Struktur pemerintahan internal, sistem produksi, dan relasi sosial yang tumbuh di atas tanah ini menegaskan bahwa hak ulayat—hak komunal atas tanah—tidak hanya bersifat sosial, tetapi melekat sebagai institusi hukum tradisional, terjaga secara turun-temurun jauh sebelum Republik Indonesia hadir.
Dokumen kolonial seperti peta dan izin konsesi perusahaan Belanda bukan sekadar arsip administratif. Konsesi Deli Maatschappij, misalnya, bersifat izin penggunaan (concession), bukan pemindahan kepemilikan (ius abusus). Prinsip ius consentum menegaskan bahwa persetujuan pihak lain tidak menghapus hak asal-usul (ius integrum) masyarakat adat. Saat nasionalisasi perusahaan pada 1958, yang dinasionalisasi hanyalah modal perusahaan, bukan tanah konsesi; hak ulayat tetap berada dalam kerangka hukum adat, karena tidak ada tindakan hukum sah yang memindahkannya.
Hak Guna Usaha dan Interpretasi Tanah Negara
Era Orde Baru membawa dinamika baru melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTPN II. HGU hanya memberi hak pakai jangka waktu tertentu, bukan menghapus hak ulayat. Saat HGU habis atau dicabut, tanah kembali dalam penguasaan negara sebagai kapasitas publik, tetapi tidak otomatis menjadi “tanah negara” bebas klaim hak ulayat. Masalah muncul ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan tanah bekas HGU sebagai tanah negara tanpa proses identifikasi, verifikasi, dan konsultasi dengan masyarakat adat Deli. Langkah ini melanggar prosedur formal, mengabaikan sejarah, hukum adat, dan ketentuan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan ini bersifat self-executing, tidak bergantung pada dokumen administratif.
Secara prosedural, Permen ATR/BPN No. 18/2019 mewajibkan identifikasi masyarakat adat, verifikasi hak ulayat, dan pemetaan partisipatif sebelum penetapan tanah. Tidak ada bukti prosedur ini dilakukan; Lembaga Adat Deli tidak dilibatkan, berita acara konsultasi tidak ada, dan musyawarah adat diabaikan. Ini jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas keterbukaan, kecermatan, partisipasi, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Secara substantif, SK BPN bertentangan dengan Pasal 18B(2) dan 28I(3) UUD 1945, serta Pasal 3, 5, dan 26 UUPA 1960. Pernyataan bahwa tanah bekas HGU otomatis menjadi tanah negara adalah penyederhanaan hukum yang keliru. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan negara bersifat perlindungan, bukan titel kepemilikan yang menghapus hak masyarakat.
Nilai Sosial, Kultural, dan Ekonomi Tanah Adat
Kawasan adat Deli kaya nilai sosial, kultural, dan ekonomi. Tanah ini bukan hanya ruang produksi, tetapi juga simbol identitas kolektif dan sarana penghidupan. Hilangnya tanah adat berarti runtuhnya garis sejarah dan terganggunya kedaulatan budaya. Tindakan administratif yang mengabaikan hak ulayat berdampak langsung pada keberlangsungan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang diakui konstitusi.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi jalur strategis dalam penyelesaian sengketa. Objek gugatan—SK Penetapan Tanah Negara Bekas HGU—adalah keputusan administratif yang konkret, final, dan individual. PTUN menilai legalitas keputusan administratif tanpa memerlukan bukti kepemilikan absolut, berbeda dengan Pengadilan Negeri. Jika SK dibatalkan, status tanah kembali mempertimbangkan hak ulayat melalui verifikasi ulang. Lembaga Adat Deli memiliki rechtstreekse belang, mewakili kepentingan historis, kultural, dan yuridis masyarakat. Struktur pengurusnya—Ketua Adat, Sekretaris Adat, dan para pemangku urung/kuta—memenuhi syarat sebagai pihak berkepentingan langsung. Legal standing ini menegaskan posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum aktif.
Paradigma Hukum Agraria Multidimensi
Pembatalan SK BPN lebih dari sekadar koreksi administratif; ia merupakan rekonstruksi paradigma hukum agraria Indonesia. Paradigma ini menyatukan empat tatanan hukum: Ius Positivum, kerangka hukum positif nasional; Ius Constitutum–Ius Constituendum, prinsip konstitusional dan arah pembaruan; Ius Gentium, standar global; dan Ius Communitatis Nusantara, hukum adat sebagai fondasi. Pendekatan ini memulihkan dimensi historis, ekologis, dan komunal yang kerap hilang akibat dominasi perspektif administratif. Dalam kerangka ini, tanah bukan sekadar unit registrasi, tetapi entitas multidimensi yang melekat pada ingatan kolektif dan kedaulatan budaya komunitas adat. Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memusatkan kekuasaan pada negara sebagai pemilik dominium, tetapi menempatkan negara sebagai public trustee, pemegang amanah yang menghormati hak masyarakat adat dan fungsi sosial-ekologis tanah.
Sejarah agraria Indonesia sarat dengan reduksi makna tanah. Kolonialisme melalui politik domeinverklaring mengklaim hampir seluruh tanah tak bertuan sebagai milik negara jajahan. Setelah kemerdekaan, logika serupa muncul ketika aparatur negara menafsirkan tanah bekas HGU sebagai otomatis menjadi tanah negara, padahal banyak HGU diterbitkan di atas tanah adat melalui contractus concessionarium, bukan tanah negara. Delegitimasi hak ulayat berulang tanpa diuji secara historis maupun normatif. Hak ulayat, dengan karakter komunal, kesinambungan antar generasi, dan basis kosmologisnya, tidak pernah terputus, sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum adat dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Rekontekstualisasi Hak Ulayat sebagai Kunci Keadilan
Rekontekstualisasi hak ulayat menjadi kunci untuk memulihkan keadilan agraria. Dalam kerangka Ius Integrum Nusantara, tanah ulayat menempati posisi kuat secara moral dan hukum. Pengakuan hak ulayat tidak mensyaratkan SK pemerintah; keberadaannya ex lege, melekat pada komunitas adat itu sendiri. Negara justru wajib membuktikan ketiadaan hak ulayat sebelum menyatakan suatu hamparan sebagai tanah negara, sesuai asas presumption of indigenous rights dalam Ius Gentium. Prinsip free, prior, and informed consent menjadi ujian legitimasi setiap kebijakan yang menyentuh tanah adat, menjadikan masyarakat pemegang keputusan utama atas wilayahnya.
Ius Integrum Nusantara menawarkan pijakan normatif untuk keluar dari kebuntuan hukum. Dengan menyatukan ius positivum yang memberi kerangka legal, ius gentium yang menghadirkan standar global, ius communitatis yang menghidupkan hukum adat, dan ius constituendum yang menuntun arah pembaruan, paradigma ini menempatkan hukum agraria sebagai sarana pemulihan struktur sosial, bukan sekadar alat administratif. Negara kembali pada peran sebagai trustee, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sebagai pemilik tunggal sumber daya.
Pemulihan Legitimasi dan Fungsi Trustee Negara
Tanah adat Deli adalah perpanjangan identitas komunitas, ruang kosmologis, dan sarana produksi. Hak ulayat diperkuat prinsip ius integrum, hak asal-usul yang tidak terputus, dan ius consentum, persetujuan penggunaan pihak lain. Penetapan tanah sebagai “tanah negara” tanpa verifikasi hak ulayat melanggar hierarki hukum, mengabaikan prinsip trusteeship, dan menghapus hak yang dilindungi konstitusi.
Rekonstruksi legitimasi hak ulayat Deli bukan tindakan belas kasihan, melainkan kewajiban hukum, sejarah, dan keadilan. Kemenangan hukum masyarakat Deli akan menjadi preseden penting: hukum agraria Indonesia harus berpihak pada mereka yang secara historis, hukum, dan kultural memiliki hak atas tanah, bukan pada dominasi administratif semata. Dengan paradigma hukum multidimensi ini, negara menempatkan diri sebagai pelindung hak rakyat dan penjamin fungsi sosial-ekologis tanah, sehingga keadilan agraria dapat ditegakkan tanpa mengorbankan identitas, sejarah, dan kesejahteraan masyarakat adat.
Rekonstruksi Hak Ulayat Mandailing dalam Paradigma Agraria Modern Terpadu
Sejak dahulu, tanah ulayat Mandailing bukan sekadar aset fisik, melainkan fondasi ruang hidup, identitas kolektif, dan penopang struktur sosial. Masyarakat Mandailing, sebagaimana komunitas adat lain di Nusantara, menempatkan tanah, sungai, hutan, dan sumber daya alam sebagai bagian integral dari sistem sosialnya. Hak ulayat bukan hak individu, melainkan recht van bestuur—hak komunal yang menuntut keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Proses normatif seperti customary conversion memungkinkan individu mengelola tanah tertentu dengan persetujuan kepala adat, tetapi hak kolektif tetap menjadi prinsip utama.
Struktur sosial Mandailing menegaskan prinsip itu. Raja adat, Raja Panusunan dan lembaga kekerabatan membentuk hierarki yang egaliter, menjaga keseimbangan pengelolaan tanah, hak, dan tanggung jawab antar-marga. Namun, sejarah agraria Indonesia menunjukkan bahwa hak ulayat kerap direduksi menjadi pelengkap administratif. Keberadaannya sering bergantung pada pengakuan negara, bukan sebagai sumber legitimasi primer pengelolaan ruang hidup.
UUPA 1960 mengakui hak ulayat sepanjang masih ada, menegaskan bahwa hukum agraria nasional harus bertumpu pada hukum adat—the living law. Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum adat menjadi dasar agraria nasional, sedangkan Pasal 1 ayat (2) menyatakan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa berada di bawah penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat, bukan kepemilikan absolut (dominium). Sayangnya, pengakuan formal jarang disertai mekanisme implementatif yang konsisten, sehingga negara cenderung bertindak sebagai superior landlord yang memegang right of disposal.
Sejarah Ulayat dan Tata Ruang Mandailing
Sejak masa kolonial, tanah adat Mandailing dikelola melalui prinsip dalihan na tolu, menegaskan relasi sosial atas ruang hidup, bukan transaksi ekonomi semata. Wilayah ulayat merupakan jaringan makna yang meliputi situs leluhur, hutan larangan, sawah, sungai, dan ruang sakral. Kebijakan kolonial Belanda melalui domeinverklaring dan konsesi jangka panjang (concession contracts) tidak pernah menghapus hak asal-usul masyarakat, meskipun mengatur penggunaan tanah untuk produksi komersial.
Setelah kemerdekaan, nasionalisasi konsesi tidak diikuti rekognisi penuh terhadap hak ulayat. Ketika masa HGU berakhir, banyak tanah kembali ditetapkan sebagai tanah negara tanpa kajian sosial-historis. Aparatur negara sering beroperasi dalam logika administratif semata, sehingga suara komunitas lokal nyaris tidak terdengar. Delegitimasi hak ulayat ini bukan hanya administrasi yang cacat prosedur, tetapi ketidakadilan struktural yang mengabaikan dimensi historis, ekologis, dan kultural tanah.
Dalam konteks komparatif, negara-negara dengan sejarah hukum adat kuat, seperti Filipina, Kanada, dan Selandia Baru, memberikan pelajaran penting. Filipina melalui Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA) mengakui native title tanpa pembuktian ulang, Kanada mengatur Aboriginal title yang setara dengan hukum nasional, sedangkan Selandia Baru menguatkan hak Maori melalui Treaty of Waitangi. Model ini menegaskan bahwa pengakuan hak adat sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek administratif, dapat menjadi fondasi politik agraria yang stabil.
Konflik dan Ketegangan Administratif
Pola sengketa ulayat Mandailing cenderung seragam: batas wilayah sering bersinggungan dengan perusahaan perkebunan atau tambang, sementara negara memberikan konsesi tanpa menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yang diakui sebagai customary international law. FPIC memastikan bahwa keputusan yang menyentuh wilayah adat dilakukan dengan persetujuan masyarakat, bebas tekanan, dan informasi lengkap. Tanpa FPIC, penerbitan HGU atau penetapan tanah negara menjadi ultra vires, melampaui kewenangan pejabat, sekaligus melanggar prinsip keadilan substantif.
Lembaga adat Mandailing berperan sebagai mediator, tetapi kapasitas lokal tidak cukup menghadapi logika birokrasi yang menafsirkan tanah adat sebagai terra nullius modern. Rekam jejak Mandailing dari arsip kolonial hingga dokumen lokal menunjukkan pengaturan tanah adat yang relatif konsisten. Pasca kemerdekaan, desentralisasi dan liberalisasi ekonomi tanah memperburuk posisi ulayat; pejabat pertanahan sering memproses permohonan konsesi tanpa verifikasi sejarah wilayah ulayat.
Konstitusi 1945 melalui Pasal 18B, 28I, dan 33 menegaskan perlindungan masyarakat adat dan penguasaan negara atas bumi sebagai public trusteeship. Namun ketika negara menafsirkan dirinya sebagai pemilik mutlak, lahirlah kebijakan yang mengabaikan hak asal-usul, mengganggu fungsi ekologis, dan merusak situs leluhur.
Paradigma Ius Integrum Nusantara
Di sinilah paradigma Ius Integrum Nusantara menjadi krusial. Paradigma ini merevisi pemisahan tajam antara hukum positif (ius positivum) dan hukum adat, menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar tradisi, melainkan source of norms yang sah. Lima prinsip keadilan digabungkan: legalitas administratif, legitimasi budaya, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, dan keadilan historis. Semua unsur ini membentuk transformative law, hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi merestrukturisasi relasi kuasa atas tanah.
Paradigma ini memulihkan dimensi historis, ekologis, dan komunal yang kerap hilang akibat pendekatan hukum administratif. Tanah tidak lagi dipandang sekadar unit registrasi, tetapi entitas multidimensi yang melekat pada memori kolektif, identitas budaya, dan kedaulatan masyarakat adat. Konsep communal sovereignty dihidupkan kembali: masyarakat adat bukan subjek subordinat, tetapi pemegang kedaulatan atas tanah komunalnya.
Secara konstitusional, paradigma ini memperkokoh pluralisme hukum Indonesia. Konstitusi 1945 sudah membuka ruang bagi keberagaman hukum; Ius Integrum Nusantara menjabarkan mekanisme operasionalnya. Hak ulayat tidak lagi dianggap keanekaragaman pinggiran, tetapi pilar keadilan agraria yang setara dengan hak atas tanah negara. Prinsip trusteeship negara sesuai Pasal 33 ayat (3) menempatkan negara sebagai pemegang amanah (public trustee), bukan pemilik absolut.
Ulayat dan Administrasi Modern: Paradoks Formalisasi
Paradigma administrasi yang menilai hak ulayat melalui peta dan dokumen formal menimbulkan paradoks. Prosedur formal menjadi syarat utama pengakuan, sehingga hak adat berabad-abad baru dianggap eksis setelah disahkan pejabat. Keputusan pejabat pertanahan yang menetapkan tanah negara di atas ulayat tanpa verifikasi sejarah atau konsultasi adat melanggar prosedur administratif sekaligus mandat konstitusi, termasuk asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti keterbukaan, partisipasi, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam perspektif Ius Integrum Nusantara, pengakuan hak ulayat bersifat deklaratif, ex lege, tanpa perlu legalisasi administratif. Negara justru berkewajiban membuktikan ketiadaan hak ulayat sebelum menetapkan tanah sebagai tanah negara, mengikuti asas presumption of indigenous rights yang berlaku dalam Ius Gentium.
Tumbaga Holing: Paradigma Integratif
Penguatan hak ulayat Mandailing memerlukan paradigma Tumbaga Holing, filosofi hukum Nusantara yang memadukan kesinambungan adat, rasionalitas modern, dan visi jangka panjang tata ruang hidup. Dalam kerangka ini, hukum adalah living normative order, prediktor sosial yang menjamin keadilan dan memberdayakan masyarakat sebagai subjek hukum.
Sistem adat Mandailing berlapis, hierarkis, tetapi egaliter. Raja adat, Raja Panusunan, dan Dalihan Natolu bertindak sebagai normative authority, menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan norma, mengadili konflik, dan memberi putusan dengan legitimasi turun-temurun. Dalihan Natolu menegaskan shared sovereignty: setiap marga memiliki hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan. Hierarki tidak menciptakan dominasi, tetapi distribusi peran yang seimbang.
Hukum adat Mandailing bersifat restoratif. Tujuannya memulihkan keseimbangan sosial, bukan menghukum. Mekanisme musyawarah, pengakuan kesalahan, dan pemulihan relasi menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekologis, stabilitas sosial, dan keadilan antar generasi. Substansi hukum ini dapat dirumuskan dalam tiga inti: struktur adat sebagai perangkat legitim, Dalihan Natolu sebagai normative matrix, dan keberlanjutan hukum adat bergantung pada keseimbangan antar-marga.
Hukum Adat Mandailing sebagai Instrumen Futuristik
Hukum adat Mandailing bukan sekadar warisan, tetapi sumber inspirasi untuk agraria inklusif. Prinsip komunalitas ulayat dan dalihan na tolu mampu menyesuaikan diri dengan tekanan pasar tanah, urbanisasi, dan perubahan iklim. Mekanisme musyawarah adat dan restorative justice memastikan keberlanjutan ekologis dan keadilan antar generasi.
Integrasi hukum adat ke sistem agraria nasional harus menjamin rekognisi substantif, pembagian kewenangan antara lembaga adat dan negara, serta penilaian dampak sosial-adat (adat impact assessment). Prinsip FPIC, yang diakui UNDRIP 2007 dan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 35/2012), mencegah pelanggaran substantif dan prosedural.
Pengalaman global menunjukkan keserupaan dengan indigenous jurisprudence modern di Kanada, Selandia Baru, dan Filipina, di mana hukum adat diperlakukan sebagai sumber legitimasi negara, bukan residu historis. Di Indonesia, Tumbaga Holing memungkinkan hukum adat Mandailing menjadi instrumen epistemologis membangun sistem agraria adaptif dan korelatif. Negara berperan sebagai public trustee, menjamin rekognisi substantif, pengawasan ruang hidup adat, dan keseimbangan kewenangan lembaga adat dan negara.
Pilar Keadilan Agraria
Hak ulayat Mandailing adalah refleksi pluralisme hukum dan keadilan agraria. Integrasi hukum adat dan hukum nasional melalui paradigma Tumbaga Holing membuka jalan transformasi agraria yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pembangunan yang berkeadilan menuntut pengakuan bahwa tanah bukan sekadar komoditas, tetapi ruang pengetahuan, memori kolektif, dan identitas budaya. Mandailing menawarkan model integrasi hukum adat yang menjadi tolok ukur stabilitas politik agraria Indonesia. Dengan pendekatan ini, negara tidak lagi menjadi superior landlord, tetapi public trustee yang menjaga keberlanjutan ruang hidup adat bagi generasi mendatang.
Dalam kerangka ini, tanah ulayat Mandailing bukan hanya soal penguasaan fisik, tetapi pengakuan atas sejarah, identitas, dan hubungan ekologis masyarakat dengan lingkungannya. Negara, sebagai pengelola dan pengawas (trustee), harus menempatkan hukum adat sebagai fondasi hukum agraria nasional, menghormati prinsip keadilan, dan memastikan kesinambungan hak ulayat antar generasi.
Rekonstruksi Hak Ulayat Mandailing dalam Hukum Nasional
Di Mandailing, tanah bukan sekadar aset ekonomi atau ruang administratif. Ia adalah nadi kehidupan masyarakat, sumber identitas, dan fondasi relasi sosial. Hak ulayat Mandailing mengatur penguasaan komunal (communal ownership), di mana seluruh anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, dijalankan melalui musyawarah adat (deliberative governance). Raja adat, Raja Panusunan, dan lembaga kekerabatan Dalihan Natolu berperan sebagai custos normarum, menjaga keseimbangan otoritas dan keadilan sosial.
Hak ulayat bukan semata harta, tetapi medium pengetahuan, memori kolektif, dan mekanisme tata kelola sosial. Sungai, hutan, sawah, dan situs leluhur bukan hanya objek, tetapi bagian dari jaringan norma hidup (living law) yang diakui oleh masyarakat dan dijaga turun-temurun. Di sinilah terlihat bahwa tanah Mandailing adalah space of meaning, bukan hanya space of ownership.
Dalam konteks hukum nasional, hak ulayat diakui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Pasal 3, yang menegaskan hukum adat tetap menjadi sumber hak atas tanah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketertiban umum. Konstitusi 1945 melalui Pasal 18B dan Pasal 28I memberikan perlindungan konstitusional bagi masyarakat hukum adat, sementara Pasal 33 menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial.
Sejarah dan Ketahanan Hukum Ulayat
Sejarah menunjukkan daya tahan luar biasa hak ulayat Mandailing. Pada era kolonial, Belanda mencoba mengubah tanah adat menjadi konsesi perkebunan atau Hak Guna Usaha (HGU). Dokumen kolonial 1869–1924 mencatat bahwa meskipun administrasi kolonial berusaha mengubah status tanah, batas wilayah ulayat tetap diakui oleh masyarakat lokal. Fakta ini menegaskan konsep living law Eugen Ehrlich: hukum bukan sekadar teks, tetapi praktik sosial yang dipatuhi masyarakat.
Pasca kemerdekaan, nasionalisasi konsesi tidak diikuti rekognisi penuh terhadap hak ulayat. Banyak tanah yang berakhir sebagai tanah negara setelah HGU selesai, tanpa verifikasi historis maupun konsultasi adat. Aparatur negara kerap bekerja dalam logika administratif semata, sehingga suara komunitas lokal nyaris tak terdengar. Delegitimasi hak ulayat ini menciptakan ketidakadilan struktural, yang mengabaikan dimensi historis, ekologis, dan kultural tanah.
Ius Integrum Nusantara: Paradigma Hukum Hybrid
Dalam konteks itulah gagasan Ius Integrum Nusantara muncul: paradigma hukum agraria yang menyintesiskan empat dimensi hukum—ius positivum, ius constitutum–ius constituendum, ius gentium, dan ius communitatis Nusantara—ke dalam satu sistem konseptual. Paradigma ini tidak sekadar normatif, tetapi juga historis, ekologis, dan konstitusional, mampu menjembatani fragmentasi kelembagaan dan pluralitas norma.
Ius positivum tetap menjadi landasan operasional. Hukum nasional—UUPA 1960, UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, serta peraturan kehutanan—memberikan legalitas formal yang diperlukan agar hak ulayat dapat diakui dalam sistem hukum nasional. Tetapi hukum positif tidak cukup bila tidak diiringi reformasi struktural.
Di sinilah ius constitutum–ius constituendum hadir: kritik terhadap regulasi yang ada sekaligus agenda pembaruan hukum. Negara harus merumuskan mekanisme rekognisi hak ulayat melalui pemetaan partisipatif, registrasi komunal, evaluasi historis-legal, dan larangan menetapkan tanah negara tanpa verifikasi adat. Paradigma ini mendorong reformasi prosedural sekaligus substantif.
Ius gentium, atau norma internasional, memperkuat legitimasi paradigma ini. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), prinsip non-regression, serta nilai intergenerational equity dan precautionary principle dalam hukum lingkungan global menegaskan bahwa hak adat tidak boleh dihapus melalui kebijakan mundur. Negara yang mengklaim otoritas penuh tanpa persetujuan komunal melanggar prinsip universal pengakuan masyarakat adat.
Dimensi paling khas adalah ius communitatis Nusantara. Hukum adat lokal bukan sekadar simbol nilai lama, melainkan sistem norma hidup yang menjadi sumber kearifan agraria komunal. Struktur internal—pemimpin adat, musyawarah, konsensus—harus dihormati sebagai bagian dari proses legal nasional. Dalam banyak komunitas, batas lahan ditentukan bukan oleh peta semata, tetapi oleh cerita leluhur, batas alam, dan persetujuan generasi. Pengakuan hak ulayat berarti menghormati mekanisme adat dan menjadikannya bagian dari struktur legal yang sah.
Paradigma Justice-Based Governance
Ius Integrum Nusantara mengusung paradigma justice-based governance. Negara tidak dipandang sebagai pemilik tunggal yang mendikte, tetapi sebagai pengelola amanah (public trustee) yang melindungi hak-hak komunal, keberlanjutan ekologis, dan identitas budaya. Rekognisi hak ulayat, redistribusi keadilan, pemeliharaan fungsi sosial-ekologis tanah, serta mekanisme resolusi konflik restoratif menjadi pilar utama yang menjembatani kesenjangan antara hukum formal, norma internasional, dan hukum adat.
Dalam paradigma ini, negara tetap memiliki kewenangan, tetapi diikat oleh empat batasan utama: identitas sejarah komunitas adat (historical embeddedness), keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini sejalan dengan interpretasi konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan penguasaan negara dalam kerangka amanah, bukan kepemilikan mutlak (dominium).
Rekonstruksi Hukum dan Mekanisme Operasional
Dalam praktiknya, rekonstruksi hak ulayat Mandailing melalui Ius Integrum Nusantara memerlukan integrasi empat dimensi hukum ke dalam mekanisme operasional. Pemetaan partisipatif (participatory mapping) mengidentifikasi batas ulayat berdasarkan tradisi, situs leluhur, dan persetujuan generasi. Registrasi komunal (Customary Land Registry) mengakui hak kolektif secara formal tanpa mereduksi karakter adat. Evaluasi historis-legal memastikan bahwa setiap penetapan tanah negara mempertimbangkan kontinuitas hak ulayat.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dilakukan melalui co-governance antara lembaga adat dan pemerintah. Masyarakat memiliki kewenangan mengatur perizinan adat (customary licensing), membagi manfaat (benefit-sharing), dan berpartisipasi dalam perencanaan tata ruang (RTRW). Konversi hak ulayat menjadi hak milik individu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kepala adat dan tetap berada di bawah pengawasan komunal.
Sengketa diselesaikan melalui mekanisme hybrid (adat + negara), memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Putusan adat memiliki legitimasi hukum, sementara konflik dengan pihak luar diselesaikan dengan mempertimbangkan prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent). Integrasi norma adat ke dalam peraturan daerah dan putusan pengadilan menegaskan legal pluralism konstruktif, di mana norma adat dan norma negara saling memperkuat.
Perspektif Komparatif
Secara internasional, paradigma ini memiliki kesamaan dengan pengakuan native title di Australia dan FPIC dalam konteks Inter-American Court of Human Rights. Dalam Mabo v. Queensland (1992), Mahkamah Australia menegaskan penguasaan tanah oleh masyarakat adat memiliki legitimasi hukum. Perbedaannya, Ius Integrum Nusantara menekankan integrasi yang mempertahankan konteks historis, sosial, dan budaya lokal, menghasilkan hukum hybrid yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional.
Di Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 342 K/Sip/1995 menegaskan pengembalian tanah kepada masyarakat adat ketika diklaim negara atau pihak ketiga. Studi kasus di Desa Rambah Tengah Hulu menunjukkan peran tokoh adat sebagai mediator dalam sengketa perkebunan, menegaskan prinsip subsidiaritas dan legal pluralism. Norma adat dan norma negara dioperasikan secara paralel untuk menguatkan legitimasi sosial dan kepastian hukum.
Integrasi Sosial dan Ekologis
Hak ulayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya, resolusi konflik, dan pengambilan keputusan ekonomi lokal. Pendekatan Ius Integrum Nusantara menjamin bahwa kebijakan publik menghormati hak kolektif dan nilai budaya. Modernitas hukum dan kearifan lokal dapat harmonis melalui prinsip subsidiaritas, di mana komunitas lokal menjadi pemegang kewenangan tertinggi.
Pengakuan hak ulayat juga berdampak pada keberlanjutan ekologis. Prinsip precautionary principle menuntut perlindungan hutan, sungai, dan situs leluhur saat redistribusi atau konversi lahan dilakukan. Dengan pengawasan komunal dan mekanisme musyawarah, pengelolaan tanah Mandailing tetap berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologis dan sosial antar generasi.
Fondasi Hukum Pertanahan Inklusif
Integrasi hak ulayat Mandailing melalui Ius Integrum Nusantara menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar simbol tradisi, tetapi bagian integral dari sistem hukum nasional yang responsif, pluralistik, dan transformatif. Sistem ini menyatukan legitimasi sosial dan legalitas formal, melindungi hak kolektif, mengurangi konflik, dan memastikan pembangunan wilayah dilakukan adil dan berkelanjutan.
Dengan mekanisme identifikasi masyarakat adat, verifikasi lapangan, registrasi formal, dan musyawarah sah, paradigma ini melestarikan nilai tradisional Nusantara sekaligus membentuk fondasi hukum pertanahan Indonesia yang adil, berkeadaban, dan komprehensif. Negara diposisikan bukan sebagai superior landlord, tetapi sebagai public trustee yang menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat, memastikan bahwa tanah tetap menjadi sumber kehidupan, identitas, dan keadilan bagi generasi mendatang.
Tanah, Identitas, dan Kearifan Komunal
Di Mandailing, seperti di banyak komunitas adat Nusantara, tanah bukan sekadar aset ekonomi atau objek administratif. Ia adalah simbol identitas, pengikat sosial, dan medium spiritual yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta lingkungan alam. Hak ulayat, tanah marga, petuanan, leuweung larangan, hingga sasi, semuanya mencerminkan norma yang melekat dalam komunitas—living law—yang menegaskan bahwa pengelolaan tanah adalah tanggung jawab kolektif, bukan hak individual semata.
Keputusan tentang penggunaan tanah di komunitas adat Mandailing bukan diambil melalui pendaftaran formal semata. Musyawarah adat, persetujuan kolektif, dan peran pemimpin adat (custos normarum) menjadi instrumen utama. Di sinilah logika komunal berbeda secara fundamental dari rezim hukum modern yang cenderung individualistis: tanah bukan komoditas yang dipindahtangankan secara permanen, tetapi ruang keberlanjutan eksistensi kolektif dan spiritual.
Kegagalan Hukum Positif dan Fragmentasi Agraria
Sejak lahirnya UUPA 1960, hukum agraria nasional menegaskan prinsip penguasaan tanah oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, praktik implementatif seringkali gagal menjembatani realitas sosial-komunal. Pendaftaran tanah, sertifikasi, dan izin konsesi kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan hak historis masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik, marginalisasi komunitas, dan degradasi lingkungan. Fragmentasi hukum dan birokrasi menyebabkan tanah adat seolah menjadi “zona abu-abu” antara legitimasi formal negara dan eksistensi historis masyarakat.
Kritik terhadap kerangka hukum nasional ini bukan penolakan terhadap hukum, tetapi seruan agar hukum dapat menyatu dengan nilai-nilai lokal dan standar internasional. Tanah tidak lagi sekadar objek kepemilikan atau sumber ekonomi; ia adalah bagian dari jaring sosial-ekologis yang mengikat manusia, alam, dan sejarah.
Paradigma Ius Integrum Nusantara: Empat Dimensi Hukum
Dalam konteks itulah muncul paradigma Ius Integrum Nusantara, kerangka konseptual yang mengintegrasikan empat dimensi hukum:
1. Ius Positivum: Landasan Hukum Nasional
Hukum nasional tetap menjadi pondasi operasional. UUPA 1960, undang-undang kehutanan, peraturan pertanahan, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi membentuk instrumen legal formal yang memungkinkan negara menata tanah secara administratif. Tanpa ius positivum, integrasi norma adat dan internasional akan kehilangan payung legal, sehingga legitimasinya diragukan.
Namun, ius positivum saja tidak cukup. Regulasi formal seringkali mengabaikan konteks lokal, misalnya menetapkan tanah negara tanpa memverifikasi klaim adat. Kekosongan implementatif ini membuka ruang konflik, baik antara masyarakat adat dan negara, maupun antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekologis.
2. Ius Constitutum–Ius Constituendum: Agenda Reformasi Hukum
Paradigma ini menegaskan bahwa hukum nasional yang ada (constitutum) memiliki kekurangan implementatif dan menuntut reformasi (constituendum). Agenda reformasi ini mencakup mekanisme pendaftaran komunal, verifikasi historis-legal, konsultasi adat, dan larangan penetapan tanah negara tanpa persetujuan komunitas.
Reformasi ini bukan sekadar teknis administratif. Ia menuntut perubahan cara berpikir birokrasi pertanahan: dari sekadar pemilik tanah menjadi public trustee—pengelola amanah yang memahami nilai sosial, ekologis, dan historis tanah. Negara, dengan demikian, diikat oleh empat batas utama: identitas sejarah komunitas adat (historical embeddedness), keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Ius Gentium: Norma Internasional sebagai Standar Legitimasi
Norma internasional menambah bobot moral dan legal. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang diakui dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), menegaskan bahwa pengakuan hak-hak adat tidak boleh dikurangi atau diabaikan. Doktrin non-regression memastikan bahwa pengakuan hak tidak mundur di tengah perubahan kebijakan.
Putusan pengadilan internasional, seperti Awas Tingni v. Nicaragua oleh Inter-American Court of Human Rights, menunjukkan bahwa negara yang menetapkan kawasan tanpa persetujuan komunitas adat dapat melanggar hak asasi. Norma internasional ini bukan aspiratif semata; ia menjadi tolok ukur bagi legitimasi tindakan negara terhadap tanah adat, memberikan preseden hukum dan standar perlindungan global yang dapat diadopsi dalam konteks lokal.
4. Ius Communitatis Nusantara: Hukum Adat sebagai Living Law
Yang paling khas adalah dimensi hukum adat. Tanah ulayat, hutan suci, dan wilayah larangan di komunitas Mandailing tidak hanya simbol identitas, tetapi aturan hidup (living law) yang mengikat sosial dan ekologis. Struktur internal—raja adat, musyawarah marga, dan mekanisme konsensus—adalah bagian integral dari tata kelola hukum.
Dalam praktiknya, hak ulayat bukan sekadar tercatat di registri, tetapi dihidupkan melalui musyawarah, persetujuan kolektif, dan peran pemimpin adat, dan dalam hal paradigma Tumbaga Holing memperoleh legitimasi sebagai hukum yang hidup dalam jiwa rakyatnya. Ini adalah logika komunal dengan abstraksi hukum yang dipatuhi dan dihormati serta belaku secara imperatif, dan sangat jauh berbeda dengan hukum modern yang individualistik dan formalistik. Keputusan pengelolaan tanah mengikuti norma sosial dan spiritual, memastikan kesinambungan ekologis dan kelangsungan identitas komunitas yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh dalam simpul hukum Tumbaga Holing.
Integrasi Norma: Menuju Public Trustee
Paradigma Ius Integrum Nusantara menekankan bahwa negara tidak boleh bertindak sebagai pemilik tunggal (dominium), melainkan sebagai public trustee. Konsep ini menekankan pengelolaan amanah: melindungi hak komunal, menjaga kesejahteraan kolektif, dan memastikan kelestarian lingkungan.
Integrasi keempat dimensi hukum ini menghasilkan prinsip co-governance: hukum adat menjadi sumber legitimasi (legitimacy), hukum nasional memberikan legalitas (legality), norma internasional menetapkan standar, dan agenda reformasi memastikan implementasi yang partisipatif. Mekanisme ini melampaui litigasi dan pembatalan administratif; ia menekankan restorasi hak dan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan.
Kelembagaan dan Operasionalisasi
Integrasi hukum memerlukan lembaga konkret. Lembaga adat—raja adat, musyawarah marga, dan lembaga adat formal—diakui sebagai entitas hukum dengan kewenangan pengelolaan ulayat, penyelesaian sengketa, dan musyawarah kolektif. Sementara itu, lembaga negara seperti ATR/BPN, pemerintah daerah, dan pengadilan memberikan payung legal formal.
Forum customary-state arbitration board dapat menjadi mekanisme hybrid untuk menyelesaikan sengketa. Registri tanah adat (Customary Land Registry) merekam peta wilayah adat, catatan pewarisan ulayat, dan dokumen musyawarah. Dengan demikian, hak ulayat hidup sebagai entitas hukum hybrid: formal di mata negara, sah secara adat, dan diakui secara internasional.
Normatif dan Positif: Pengakuan Formal
Kerangka normatif memastikan hak ulayat diakui secara hukum. UUD 1945 memberikan dasar konstitusional, sedangkan UUPA 1960 memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak adat. Peraturan pemerintah dan daerah harus mengkodifikasi norma adat—musyawarah, larangan, dan peta ulayat—tanpa menghilangkan karakter tradisional.
Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 menjadi contoh awal pengaturan identifikasi, verifikasi, dan pemetaan masyarakat adat. Ke depan, sistem ini perlu diperkuat agar inklusif, transparan, dan menghormati hak historis komunitas. Pengakuan formal sekaligus praktis ini menjadikan hak ulayat Mandailing sebagai entitas hukum hybrid yang nyata di lapangan.
Hukum yang Hidup
Lapisan paling mendasar adalah praktik sosial. Hak ulayat hanya berarti jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari: pertanian, pemanfaatan hutan, penggunaan air, dan pewarisan tanah. Kepatuhan terhadap aturan adat dan prosedur formal menjadi tolok ukur keberhasilan. Interaksi masyarakat, adat, pemerintah, dan korporasi menjadi indikator apakah ius integrum Nusantara bukan sekadar doktrin, tetapi hukum yang hidup.
Perspektif Historis dan Komparatif
Sejarah Mandailing menunjukkan ketahanan hak ulayat terhadap tekanan kolonial maupun modern. Selama era kolonial, batas wilayah ulayat tetap dihormati meski administrasi Belanda mencoba mengubah status tanah. Setelah kemerdekaan, konsesi dan HGU yang tidak memverifikasi hak adat menimbulkan konflik, menegaskan perlunya paradigma hukum hybrid.
Secara komparatif, Ius Integrum Nusantara mirip dengan native title di Australia (Mabo v. Queensland, 1992) yang mengakui hak kolektif masyarakat adat. Perbedaannya, di Indonesia, hukum adat tidak sepenuhnya menyesuaikan diri dengan hukum negara; sebaliknya, negara menghormati adat sebagai bagian dari konstitusi dan kosmologi Nusantara. Praktik co-management di Amerika Latin juga diadaptasi, menjadikan kearifan lokal sebagai pilar tata kelola modern.
Tantangan dan Strategi Implementasi
Resistensi birokrasi, keterbatasan data historis, dan konflik kepentingan korporasi menjadi tantangan utama. Risiko pendaftaran adat sekadar formalitas atau penyalahgunaan musyawarah adat nyata, tetapi risiko terbesar adalah membiarkan status quo berlanjut: tanah adat terambil tanpa rekognisi, identitas komunitas hilang, dan konflik agraria menjadi bom waktu sosial-politik.
Strategi implementasi meliputi: pemetaan partisipatif, izin ganda (adat dan negara), co-management sumber daya alam, pembentukan forum arbitrase hybrid, serta pendidikan dan pelatihan kapasitas lembaga adat dan komunitas. Pendekatan ini memperkuat subjek hukum adat menjadi partisipan aktif, bukan sekadar objek regulasi.
Menuju Hukum Pertanahan yang Beradab dan Berkelanjutan
Paaradigma Ius Integrum Nusantara menawarkan fondasi untuk hukum pertanahan yang plural, adil, dan berkelanjutan. Model ini futuristik karena mengantisipasi urbanisasi, ekspansi perkebunan, dan perubahan iklim; deterministik karena memberi kepastian hukum melalui prosedur dan registri; dan responsif karena menghormati realitas sosial-budaya masyarakat adat.
Tanah adat dalam perspektif Pancasila adalah warisan leluhur sekaligus ruang masa depan. Ius Integrum Nusantara menghormatinya sebagai keduanya: warisan yang harus dijaga dan proyek kolektif menuju keadilan agraria sejati. Negara, sebagai public trustee, berkewajiban melindungi hak komunal, keberlanjutan ekologis, dan identitas budaya, sehingga hukum pertanahan Indonesia dapat menjadi instrumen inklusif, beradab, dan substantif.
Kesimpulan: Integrasi Filosofi, Hukum, dan Praktik
Paradigma Ius Integrum Nusantara merumuskan ulang hukum agraria dengan cara menyatukan empat lapisan:
Filosofi dan Nilai: Pancasila, kosmologi adat, dan tanggung jawab sosial-ekologis.
Reformasi dan Legalitas: Hukum nasional, agenda reformasi, registri komunal, dan prosedur partisipatif.
Norma Internasional: FPIC, UNDRIP, non-regression, dan preseden internasional.
Hukum Adat dan Praksis Sosial: Musyawarah adat, co-governance, dan implementasi harian yang memastikan hukum hidup.
Keempat dimensi ini membentuk sistem yang sah secara legal, berkeadilan substantif, dan mampu menjaga keberlanjutan ekologis sekaligus warisan kultural. Dengan Ius Integrum Nusantara, negara tidak lagi sekadar mengelola tanah, tetapi menata kembali identitas agraria Indonesia melalui prinsip keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap warisan komunal.
Referensi
Colchester, M. (2021). Indigenous peoples and the law: Global perspectives on customary rights. Routledge.
Ehrlich, E. (1913). Fundamental principles of the sociology of law. Transaction Publishers.
Kartini, A. (2022). Hak ulayat Mandailing: Historis, normatif, dan strategi perlindungan hukum. Pustaka Hukum Nusantara.
Mahkamah Agung. (1995). Putusan No. 342 K/Sip/1995.
Mahkamah Konstitusi. (2012). Putusan No. 35/PUU-X/2012.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat.
PTUN Medan. (2012). Putusan No. 20/G/2012/PTUN-MDN.
Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B, 28I, 33.
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
Note: Mabo v. Queensland [1992] HCA 23.
Penulis adalah Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia.