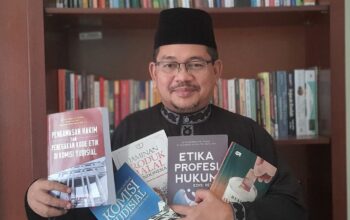Oleh: Dr. H.Ikhsan Lubis, S.H., SpN., M.Kn.
Reformasi Kenotariatan Menuju Ius Integrum Nusantara 2045
Indonesia telah mengalami evolusi panjang dalam sistem hukum kenotariatan sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Sistem yang pada awalnya diwarisi dari rezim hukum kolonial (Staatsblad 1860 No. 3) perlahan mengalami transformasi menuju sistem hukum nasional yang lebih inklusif, modern, dan berkeadilan. Namun, proses ini tidak berlangsung linear, melainkan dipengaruhi oleh perubahan politik, dinamika sosial, dan tekanan global yang membentuk karakter hukum di setiap periodenya. Pada periode awal pascakemerdekaan, sistem kenotariatan bersifat hibrida, menggabungkan formalisme kolonial dengan hukum adat dan Islam yang hidup di masyarakat. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, birokratisasi dan legalisme mulai menguat, meski masih belum sepenuhnya menyentuh aspek keadilan substantif. Tonggak besar terjadi pada Reformasi 1998, yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) dan diperbarui dalam UU No. 2 Tahun 2014, yang membawa notaris ke dalam kerangka hukum nasional sebagai pejabat umum yang berintegritas dan bertanggung jawab secara profesional.
Tantangan baru muncul dalam era digital pasca-2014.
Perkembangan teknologi informasi menuntut penyesuaian mendalam dalam praktik kenotariatan, mulai dari pengesahan akta elektronik, penggunaan tanda tangan digital, hingga perlindungan data pribadi. Namun, regulasi masih belum sepenuhnya menjawab dinamika ini. Di sisi lain, kesenjangan akses terhadap layanan notariat di wilayah marjinal masih menjadi masalah struktural yang menghambat prinsip equality before the law. Selanjutnya, dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045, sistem hukum kenotariatan diharapkan menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional yang tidak hanya mengedepankan formalitas dan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif, keterjangkauan layanan, dan responsivitas terhadap pluralitas budaya hukum. Kenotariatan Indonesia perlu menjadi instrumentum iuris yang menyatukan aspek hukum positif, legitimasi sosial, dan keberlanjutan teknologi demi menciptakan sistem hukum yang integral dan berakar pada jati diri bangsa.
Reformasi kenotariatan bukan hanya soal revisi undang-undang, tetapi menuntut pembaruan paradigma kelembagaan dan penguatan sistem hukum nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi berbasis ius integrum menjadi langkah strategis untuk membangun sistem kenotariatan yang inklusif, adaptif, dan transformatif menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pendahuluan
Transformasi sistem hukum kenotariatan di Indonesia merupakan refleksi dinamis dari perubahan sosial, politik, dan budaya yang melanda negeri ini sejak era kolonial hingga masa kini. Evolusi ini tidak hanya memperlihatkan adaptasi prosedural dan formalistik, tetapi juga pergeseran mendasar dalam paradigma hukum yang mengakomodasi tuntutan keadilan sosial, akuntabilitas, serta kebutuhan akan transparansi di tengah kompleksitas masyarakat modern. Dalam konteks sejarahnya, sistem kenotariatan Indonesia berangkat dari sebuah legal transplant dari hukum kolonial Belanda yang sangat kaku dan formalistis, kemudian berkembang melalui berbagai periode dengan karakter dan orientasi yang berbeda-beda. Sejak masa pascakemerdekaan, yang ditandai oleh periode peralihan hukum, hingga era reformasi dan digitalisasi, kenotariatan berusaha menjadi pilar utama penjamin kepastian hukum sekaligus pelayan publik yang responsif dan inklusif.
Sistem kenotariatan pada awalnya berfungsi terbatas bagi kalangan tertentu, terutama mereka yang berstatus Eropa dan kelompok yang disamakan, sementara mayoritas masyarakat adat dan Muslim tetap berpegang pada hukum informal dan tradisional. Realitas ini menimbulkan dilema klasik dalam pembangunan hukum nasional: bagaimana menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat formal dan universal, tetapi juga mampu menghormati dan mengintegrasikan pluralitas budaya hukum yang melekat dalam masyarakat. Periode Orde Lama dan Orde Baru menegaskan pentingnya birokratisasi dan kodifikasi hukum, namun masih mempertahankan jarak dengan keadilan sosial yang lebih luas. Baru pada era reformasi melalui UU No. 30 Tahun 2004 dan revisinya pada 2014, sistem kenotariatan mendapat kerangka hukum yang lebih kokoh, mengukuhkan posisi notaris sebagai pejabat publik dengan tanggung jawab profesional yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat.
Selain itu, di era modern ini kemapuan negara Indonesia sedang diuji dalam menghadapi tantangan baru berupa digitalisasi, globalisasi, dan pluralitas budaya hukum yang semakin kompleks. Kenotariatan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang efisien dan transparan, namun tetap menjaga keotentikan, legalitas, dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah. Di sinilah konsep ius integrum menjadi sangat relevan: sebuah paradigma hukum yang tidak hanya mengedepankan aturan formal, tetapi juga menyeimbangkan aspek keadilan substantif dan keberpihakan kepada kepentingan umum.
Paradigma Hukum Nasional Pasca-Kolonial Dikaitkan dengan Ius Integrum Nusantara 2045
Keangka konseptual Ius Integrum Nusantara 2045 menawarkan visi hukum nasional yang mengintegrasikan unsur formalitas, keadilan sosial, serta kearifan lokal dan modernitas teknologi dalam satu kesatuan yang harmonis. Dalam konteks sistem kenotariatan, paradigma ini menuntut penyesuaian mendalam terhadap prinsip-prinsip lama yang bersifat eksklusif dan birokratis menjadi suatu sistem yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Ius Integrum menekankan pentingnya legal certainty yang berpadu dengan social justice, yaitu kepastian hukum yang tidak mengabaikan keadilan substantif dan hak asasi manusia. Hal ini sangat relevan dalam konteks kenotariatan Indonesia, di mana notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta formal, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik dan pelindung kepentingan semua pihak, termasuk kelompok marjinal dan rentan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, non-diskriminasi, equality before the law, dan kepentingan umum yang telah diperkuat melalui revisi UUJN, merupakan manifestasi konkret dari paradigma ius integrum dalam praktik.
Kemudian, dalam menghadapi digitalisasi, paradigma ius integrum juga mengharuskan penyusunan regulasi yang tidak hanya mengakomodasi penggunaan teknologi, seperti akta elektronik dan tanda tangan digital, tetapi juga menjamin perlindungan data pribadi dan hak akses masyarakat secara merata. Regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi harus mampu menjaga integritas hukum dan memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan profesi notaris. Dengan demikian, kenotariatan dapat berfungsi sebagai penjaga legalitas sosial-teknologis yang menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan keadilan sosial.
Selain itu, ius integrum menuntut integrasi yang lebih baik antara hukum nasional dengan sistem hukum adat dan Islam, yang selama ini masih berjalan secara paralel dan kurang terintegrasi dalam praktik kenotariatan formal. Pengakuan terhadap keberagaman budaya hukum ini menjadi landasan bagi sistem kenotariatan yang inklusif, mampu menjembatani ketegangan antara modernitas dan tradisi, serta menyediakan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya, dari perspektif pembangunan hukum nasional menuju 2045 perlu adanya suatu sistem kenotariatan yang ideal sebagai suatu sistem yang mampu menjawab kompleksitas sosial-budaya dan teknologi secara simultan. Sebagai pejabat publik, notaris harus diperlengkapi dengan kapasitas profesional yang terus berkembang, mekanisme pengawasan yang kuat, serta akses teknologi yang memadai. Pendekatan holistik ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan, tetapi juga memperkuat fondasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pengembangan konsep Ius Integrum Nusantara 2045 menawarkan kerangka normatif dan konseptual yang sangat relevan bagi evolusi kenotariatan Indonesia. Paradigma ini mengimbangi antara tuntutan formalitas hukum dan kebutuhan akan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan dinamika zaman. Sistem kenotariatan yang berlandaskan paradigma ini tidak hanya akan menjadi instrumen penting dalam sistem hukum nasional, tetapi juga pilar bagi tata kelola hukum yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial di era digital.
Periode I: Masa Peralihan Pasca-Kemerdekaan (±1945–1959)
Periode pertama pascakemerdekaan merupakan masa transisi yang penuh dinamika dalam sistem kenotariatan Indonesia. Karakter hukum pada periode ini masih sangat dipengaruhi oleh legacy kolonial Belanda, terutama Staatsblad 1860 No. 3 yang tetap menjadi rujukan utama dalam praktik kenotariatan. Namun, kondisi sosial-politik yang baru mengharuskan sistem hukum menyesuaikan diri dengan konteks nasional yang sedang dibangun. Notaris pada masa ini masih berfungsi terbatas untuk kalangan Eropa dan golongan yang disamakan, sementara mayoritas masyarakat yang mengacu pada hukum adat dan Islam tidak terlayani secara formal. Dengan demikian, sistem kenotariatan masih bersifat hibrida dan transisional, di mana unsur kolonial dan lokal saling berinteraksi namun belum sepenuhnya melebur.
Parameter hukum pada masa ini sangat menekankan legalitas formal dan otentisitas dokumen sebagai tolok ukur utama dalam memastikan keabsahan akta. Hukum kenotariatan masih dipandang sebagai alat administratif yang berorientasi pada kejelasan bukti hukum, tetapi belum mengakomodasi kebutuhan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, prinsip keadilan lokal dan legitimasi sosial tetap menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan dalam konteks sosial yang majemuk. Hal ini mencerminkan situasi hukum yang belum seragam, di mana norma hukum negara formal belum sepenuhnya diterima atau diimplementasikan secara luas, terutama di luar kawasan kota-kota besar.
Kerangka hukum pada periode ini bersifat fragmentaris dan belum berbentuk sistem yang koheren. Pengaruh hukum kolonial masih dominan, tetapi sudah mulai muncul kesadaran akan pentingnya pembangunan hukum nasional yang mandiri dan relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Transisi konstitusional dari RIS ke UUDS 1950 dan kemudian kembali ke UUD 1945 menandai perubahan landasan konstitusional yang turut mempengaruhi pembangunan sistem kenotariatan. Namun, belum ada undang-undang khusus yang mengatur jabatan notaris secara nasional sehingga posisi dan peran notaris masih lemah dan belum terintegrasi secara sistematis dalam sistem hukum nasional yang sedang berkembang.
Rujukan hukum yang digunakan dalam praktik kenotariatan masih merujuk pada hukum kolonial, terutama Staatsblad 1860 No. 3, yang menetapkan peraturan tentang jabatan notaris dan tata cara pembuatan akta. Dalam ranah konstitusional, perpindahan sistem politik dan hukum dari negara federal ke negara kesatuan juga mempengaruhi status hukum kenotariatan secara tidak langsung, karena menuntut penyesuaian terhadap norma-norma baru yang bersifat nasional. Namun, keberadaan hukum adat dan hukum Islam sebagai sumber hukum utama bagi mayoritas masyarakat menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk mengembangkan sistem kenotariatan yang inklusif, walaupun pada periode ini belum tercapai harmonisasi yang memadai.
Selanjutnya, dapat dipahami dalam periode pascakemerdekaan ini merupakan fase awal pembentukan sistem kenotariatan yang masih sangat bergantung pada legal transplant kolonial, namun mulai menyerap semangat pembaruan hukum nasional. Sistem kenotariatan belum berperan secara universal dan lebih banyak berfungsi sebagai alat administrasi formal bagi kalangan terbatas. Kerangka hukum dan rujukan yang ada masih memerlukan reformasi dan harmonisasi yang signifikan agar dapat melayani kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang beragam dan kompleks. Masa ini membuka ruang bagi transformasi yang lebih mendalam dalam periode berikutnya, menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan profesional.
Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem kenotariatan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial Belanda, khususnya Staatsblad 1860 No. 3 yang mengatur jabatan notaris secara formalistis. Pada masa ini, belum terjadi kodifikasi hukum kenotariatan nasional yang independen; sistem hukum yang berlaku masih bersifat hybrid dengan dominasi hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam yang saling berdampingan secara tidak simetris. Notaris pada periode ini cenderung melayani golongan Eropa dan masyarakat kelas atas yang tunduk pada hukum Barat, sehingga akses layanan kenotariatan belum bersifat universal dan inklusif. Hukum yang berlaku berorientasi pada legalitas formal dan otentisitas dokumen yang kaku, sementara keadilan lokal dan legitimasi sosial cenderung didasarkan pada hukum adat dan norma komunitas setempat.
Kesadaran akan pentingnya pembentukan hukum nasional yang mandiri mulai tumbuh, namun proses transisi masih lambat dan menghadapi tantangan integrasi antara hukum lama dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Pada periode ini, posisi notaris belum menjadi pejabat umum yang melayani seluruh lapisan masyarakat, sehingga kenotariatan belum berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung prinsip keadilan substantif (substantive justice) dan akses keadilan (access to justice) secara luas1.
Periode II: Orde Lama (±1959–1966)
Periode Orde Lama ditandai oleh kondisi hukum nasional yang masih dalam tahap konsolidasi dan pencarian identitas hukum yang kokoh setelah masa revolusi dan masa transisi sebelumnya. Karakter hukum pada periode ini ditandai dengan ketidakpastian dan fragmentasi, karena belum ada regulasi kenotariatan yang mengikat secara nasional. Sistem kenotariatan masih belum menjadi kebutuhan universal dalam masyarakat, dan fungsi notaris belum sepenuhnya diakui sebagai institusi hukum formal. Peran pejabat adat dan agama masih sangat dominan dalam mengurus urusan dokumentasi dan pembuktian, terutama di luar pusat-pusat pemerintahan, sehingga mencerminkan situasi hukum pluralistik yang berlapis.
Kemudian, tinjauan dalam aspek parameter hukum, prinsip keadilan substantif mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, terutama dalam konteks hukum yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas dan beragam. Hukum informal dan instrumen lokal seperti hukum adat dan hukum Islam masih menjadi sumber utama penyelesaian sengketa dan legitimasi dokumen, sementara pengakuan terhadap hukum formal negara masih sangat terbatas. Aksesibilitas terhadap pelayanan hukum formal, termasuk jasa notaris, menjadi masalah karena belum adanya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur. Prinsip kesetaraan hukum mulai dikembangkan, meskipun pelaksanaannya masih belum konsisten dan belum merata di seluruh wilayah.
Kerangka hukum pada periode ini tetap belum terintegrasi secara sistematis dalam konteks nasional. Tidak adanya undang-undang jabatan notaris menyebabkan status dan kewenangan notaris masih ambigu dan bergantung pada peraturan lokal maupun kebiasaan. Posisi notaris lebih sebagai pelengkap administrasi ketimbang pejabat publik yang berfungsi dalam rangka pelayanan hukum secara profesional dan nasional. Peran institusi pemerintahan dan peradilan mulai terasa, namun masih terbatas pada fungsi administratif dan pengesahan dokumen, tanpa ada sistem pengawasan terpadu yang mengatur praktik kenotariatan secara menyeluruh. Keadaan ini mencerminkan kondisi hukum yang belum matang dan menuntut reformasi substantif.
Rujukan hukum yang digunakan dalam praktik kenotariatan di masa ini masih bersifat tumpang tindih antara norma hukum formal yang diadopsi dari masa kolonial dan hukum adat serta hukum Islam yang hidup secara faktual di masyarakat. Ketiadaan regulasi nasional mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan jaminan kepastian dalam pembuatan akta dan dokumen hukum lainnya. Peran notaris yang belum diperkuat secara hukum membuka ruang bagi variasi praktik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan administratif. Secara konstitusional, masa Orde Lama masih mengedepankan pembangunan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial, namun masih dalam kerangka yang sangat terbatas dan belum terwujud secara konkret dalam bidang kenotariatan.
Selanjutnya dapat disimpulkan, periode Orde Lama merupakan masa pembentukan yang masih lemah bagi sistem kenotariatan Indonesia. Karakter hukum yang masih terfragmentasi dan dominasi hukum informal menjadi ciri utama, sementara parameter hukum yang mulai menuntut keadilan substantif belum dapat diwujudkan secara sistematis dalam kerangka hukum nasional. Rujukan hukum masih bersifat pluralistis dan belum terintegrasi, yang menimbulkan ketidakpastian dan disparitas layanan kenotariatan. Periode ini menunjukkan perlunya pembentukan regulasi nasional yang kokoh dan pembinaan sistem kenotariatan yang profesional, sebagai fondasi penting untuk kemajuan sistem hukum Indonesia yang lebih modern dan berkeadilan.
Masa Orde Lama ditandai oleh ketidakpastian hukum nasional yang masih belum utuh, di mana belum ada undang-undang khusus yang mengatur jabatan notaris secara nasional. Regulasi kenotariatan masih menggunakan instrumen hukum lokal dan hukum adat yang beroperasi secara informal dan kontekstual di berbagai daerah. Notaris belum menjadi satu-satunya otoritas yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, karena peran pejabat adat dan agama masih dominan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa dan pengakuan hak.
Karakteristik hukum pada masa ini mulai mengarah pada prinsip aksesibilitas hukum, dengan upaya memperluas kesetaraan hukum bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Namun, pembentukan sistem kenotariatan yang terstruktur dan profesional belum tercapai, sehingga fungsi notaris masih parsial dan belum memenuhi prinsip equality before the law secara optimal2. Periode ini menandai tahap awal proses nasionalisasi sistem hukum kenotariatan yang masih harus banyak diperbaiki dari segi regulasi dan mekanisme pengawasan.
Periode III: Orde Baru (1966–1998)
Periode Orde Baru ditandai dengan dominasi sistem hukum birokratis yang formalistik, di mana legalitas dan kepastian hukum menjadi fokus utama dalam pembentukan dan pengelolaan sistem kenotariatan. Karakter hukum pada masa ini berkembang menuju pembakuan peran notaris sebagai pejabat administratif negara yang mengeluarkan akta otentik dengan pengakuan hukum yang lebih luas. Sistem kenotariatan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dengan penekanan pada formalitas hukum yang ketat, menjadikan akta notaris sebagai bukti yang kuat dalam sistem peradilan. Hal ini juga ditandai dengan peran yang lebih jelas dari lembaga peradilan dan Departemen Kehakiman sebagai pengawas dan regulator kegiatan notaris.
Parameter hukum yang berkembang dalam periode ini adalah legal certainty (kepastian hukum), authenticity (keaslian), dan public faith (kepercayaan publik). Notaris diharapkan mampu memberikan jaminan legalitas dan kepastian atas dokumen yang dibuatnya sehingga akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Di samping itu, sistem pengawasan mulai diarahkan pada pembinaan dan pengendalian administratif terhadap praktik notaris untuk mengurangi potensi penyimpangan. Namun, meskipun ada kemajuan dalam formalitas dan legalitas, sistem ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses layanan dan akuntabilitas publik yang terbatas.
Keerangka hukum yang berlaku pada periode Orde Baru didasarkan pada instruksi dan regulasi administratif dari Departemen Kehakiman, meskipun belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur jabatan notaris secara komprehensif. Notaris diatur melalui peraturan pemerintah dan surat edaran yang menegaskan kedudukan mereka sebagai pejabat negara dalam aspek tertentu, terutama dalam hal pembuatan akta otentik dan pengesahan dokumen. Peradilan berperan penting dalam mengesahkan dan memvalidasi dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan jabatan notaris. Sistem hukum ini memberikan fondasi yang lebih kokoh, meskipun belum mencapai tingkat kodifikasi yang memadai.
Rujukan hukum pada masa ini masih bercampur antara hukum kolonial yang diwarisi seperti KUHPerdata dan KUHAP, dengan instruksi administratif yang lebih mengutamakan fungsi birokrasi dalam pengelolaan kenotariatan.
Pendekatan hukum yang bersifat hierarkis dan birokratis ini mengutamakan stabilitas dan ketertiban administrasi negara. Namun, kendala muncul dari kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif dan inklusivitas hukum, sehingga layanan kenotariatan lebih sering terpusat di wilayah perkotaan dan terbatas bagi kalangan tertentu. Hal ini mencerminkan masih adanya jurang kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan hukum di tingkat nasional.
Selain itu, dapat diketahui pada masa Periode Orde Baru merupakan fase konsolidasi sistem kenotariatan yang lebih formal dan terorganisasi, dengan fokus pada legal formalitas dan kepastian hukum. Meskipun demikian, karakter hukum yang sangat birokratis dan terbatas pada aspek administratif menghambat perkembangan profesionalisme dan akses layanan yang merata. Kerangka hukum yang digunakan lebih menekankan pengaturan teknis dan administratif, sementara kebutuhan akan reformasi substantif dan perlindungan hak-hak masyarakat masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Periode ini menjadi titik penting dalam evolusi sistem kenotariatan yang menyiapkan landasan untuk kodifikasi dan reformasi hukum berikutnya.
Periode Orde Baru memperlihatkan peningkatan formalitas dan birokratisasi dalam sistem kenotariatan, yang dipengaruhi oleh regulasi administratif dari Departemen Kehakiman. Dalam masa ini, pengesahan akta notaris mulai diakui secara resmi sebagai bukti hukum yang kuat (public faith), meskipun dasar hukum utamanya masih berupa peraturan administratif dan belum ada kodifikasi secara menyeluruh. Notaris mulai diinstitusionalisasi dan posisinya menjadi bagian penting dari sistem administrasi hukum negara, walaupun RKUHP dan KUHPerdata masih mengadopsi konsep hukum kolonial Belanda yang formalistik.
Prinsip hukum yang berkembang berpusat pada legal certainty, authenticity, dan public faith, yang berkontribusi pada peningkatan kredibilitas akta notaris sebagai instrumen hukum. Namun, kontrol dan pengawasan profesi notaris masih lemah, dan akses keadilan bagi masyarakat luas masih terbatas oleh birokrasi dan sistem hukum yang kaku3. Notaris masih dianggap sebagai aparat negara yang bertugas melayani golongan tertentu, belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelayan hukum publik yang inklusif.
Periode IV: Awal Reformasi & Kodifikasi Pertama (1998–2004)
Periode reformasi pasca-Orde Baru menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem kenotariatan Indonesia, di mana terjadi transformasi mendasar dalam karakter hukum dan pengakuan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan formal yang jelas. Karakter hukum pada masa ini beralih dari birokrasi administratif menuju sistem hukum yang lebih terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kelahiran Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menandai kodifikasi pertama yang secara eksplisit mengatur kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab notaris secara nasional, menggantikan warisan regulasi kolonial dan aturan parsial sebelumnya.
Parameter hukum dalam periode ini berkembang signifikan, menekankan asas kepastian hukum, legalitas, dan profesionalitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan tugas notaris. UUJN memperjelas bahwa notaris tidak hanya sebagai pejabat administratif, tetapi pejabat umum yang memiliki kewenangan atribusi yang terukur dan bertanggung jawab penuh terhadap pembuatan akta otentik. Selain itu, prinsip keadilan substantif mulai ditekankan sebagai upaya untuk mewujudkan layanan kenotariatan yang tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sebagai bagian dari reformasi sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Kerangka hukum yang terbentuk pada periode ini adalah pengkodifikasian normatif pertama yang menyeluruh terkait jabatan notaris, mencakup kewenangan, larangan, kode etik, hingga mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi notaris. UUJN menjadi instrumen hukum nasional yang mengintegrasikan aspek formalitas hukum dengan prinsip pelayanan publik, mempertegas bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian otentik yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan regulasi ini juga merupakan respons atas kebutuhan modernisasi sistem hukum nasional yang mendukung keterbukaan dan transparansi, sejalan dengan semangat reformasi politik dan hukum pasca-1998.
Rujukan hukum utama pada masa ini adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang menggantikan berbagai aturan residual dari masa kolonial dan aturan sektoral yang tersebar. UUJN juga memasukkan unsur prinsip-prinsip hukum yang modern seperti asas integritas, asas akses keadilan, dan asas equality before the law yang sebelumnya kurang mendapat perhatian memadai. Regulasi ini sekaligus memperkuat kedudukan notaris dalam hierarki sistem hukum nasional, memperjelas tanggung jawab hukum, dan memberikan dasar bagi pengembangan organisasi profesi notaris serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif.
Periode IV menandai perubahan paradigmatik dalam sistem kenotariatan Indonesia, dari era administratif menuju era kodifikasi hukum yang modern dan menyeluruh. UUJN tidak hanya memperkuat posisi notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga mengukuhkan prinsip hukum yang lebih berorientasi pada pelayanan, keadilan, dan profesionalisme. Periode ini merupakan fondasi utama yang membuka jalan bagi pengembangan sistem kenotariatan yang lebih terstruktur dan berdaya saing, sekaligus menempatkan profesi notaris pada posisi strategis dalam sistem hukum nasional yang demokratis dan terbuka.
Era reformasi membawa angin perubahan signifikan dalam sistem kenotariatan Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UU ini menjadi tonggak sejarah kodifikasi pertama jabatan notaris yang secara tegas menetapkan notaris sebagai pejabat umum (public official) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kode etik yang diatur secara nasional. Regulasi ini menghapus banyak sisa hukum kolonial yang tidak relevan dan memberikan landasan hukum yang modern dan menyeluruh bagi profesi notaris.
Karakteristik periode ini adalah penguatan aspek legalitas, kepastian hukum, profesionalitas, dan keadilan substantif. UUJN menegaskan notaris harus melayani publik secara non-diskriminatif, dan akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian formal (authentieke akte). Selain itu, UUJN menanamkan prinsip keterbukaan (transparency), integritas, dan akses keadilan sebagai fondasi utama regulasi kenotariatan4. Transformasi ini menandai perubahan paradigma dari notaris sebagai pelaku hukum privat menjadi pelayan hukum publik yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan sistem hukum nasional.
Periode V: UUJN Perubahan & Penguatan Profesi (2004–2014)
Periode pasca pengesahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditandai dengan dinamika perkembangan sistem kenotariatan yang semakin matang dan profesional.
Pada periode ini, revisi besar melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum kenotariatan, dengan memperkuat mekanisme pengawasan, tanggung jawab, dan kode etik profesi. Karakter hukum periode ini bertransformasi menjadi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat akan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan yang inklusif, sejalan dengan semangat reformasi hukum yang berkelanjutan.
Parameter hukum yang diatur dalam UUJN Perubahan mengedepankan asas akuntabilitas dan non-diskriminasi, sekaligus mempertegas kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Notaris semakin diposisikan sebagai pelayan publik yang harus menjunjung tinggi integritas dan keadilan substantif dalam memberikan layanan kenotariatan. Penguatan aspek kode etik dan pengawasan oleh Majelis Kehormatan Notaris, yang diperkuat melalui pasal-pasal khusus dalam UUJN P, menjadikan profesi ini lebih terstruktur dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Kerangka hukum pada masa ini mengalami pengembangan normatif yang signifikan, dengan memperkuat legitimasi organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah resmi yang mewadahi dan membina para notaris di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan dimensi kolektif dan institusional yang penting bagi pengembangan profesi, sekaligus mempertegas fungsi pengawasan internal dan pembinaan profesional yang berkesinambungan. Regulasi yang lebih komprehensif ini menjadi landasan penting bagi profesionalisme dan kredibilitas jabatan notaris.
Rujukan hukum utama pada periode ini selain UU No. 2 Tahun 2014 adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kedudukan organisasi profesi dan mekanisme pengawasan jabatan notaris. Pendekatan hukum yang dipilih pada masa ini lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan integrasi digital dalam praktik kenotariatan, meskipun penerapan digitalisasi masih dalam tahap awal. Dengan demikian, periode ini menjadi tahap krusial dalam penguatan sistem kenotariatan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Dengan demikian, dapat diketahui dalam periode ini merupakan masa konsolidasi dan penguatan sistem kenotariatan Indonesia, di mana legislasi semakin memperkokoh status notaris sebagai pejabat umum yang profesional dan bertanggung jawab. UUJN Perubahan menjadi fondasi hukum yang menyelaraskan kepentingan publik dan profesionalisme, sekaligus membuka ruang bagi perkembangan teknologi serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Transformasi ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kenotariatan modern menuju era digital dan globalisasi.
Periode ini ditandai dengan revisi UUJN melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, yang menguatkan kewenangan, tanggung jawab, serta pengawasan profesi notaris. UUJN Perubahan menambahkan aspek pengawasan profesional melalui organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagai mekanisme kontrol etika dan disiplin. Ini menjadi titik penting bagi peningkatan akuntabilitas dan integritas profesi kenotariatan.
Selain itu, UUJN P mempertegas prinsip non-diskriminasi, keadilan substantif, dan kepentingan umum sebagai nilai fundamental dalam pelaksanaan tugas notaris. Regulasi ini juga mulai membuka peluang adaptasi teknologi dalam praktik kenotariatan, meskipun implementasi digitalisasi masih terbatas. Posisi INI sebagai organisasi tunggal semakin diperkuat dengan pengakuan hukum dan dukungan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan pentingnya organisasi profesi sebagai mitra negara dalam pengawasan dan pembinaan profesi5. Periode ini menjadi tonggak profesionalisasi notaris yang semakin mandiri dan bertanggung jawab secara sosial.
Periode VI: Era Digital & Kenotariatan Modern (2014–Sekarang)
Periode VI menandai babak baru dalam evolusi kenotariatan Indonesia dengan hadirnya tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial-budaya yang semakin meluas. Era modern ini ditandai oleh perlunya adaptasi sistem kenotariatan terhadap perkembangan teknologi informasi serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kerangka hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 beserta revisinya (UU No. 2 Tahun 2014), dikombinasikan dengan regulasi pelaksana dan kode etik profesi yang terus diperbarui untuk menjawab kebutuhan zaman.
Karakter hukum periode ini bersifat hybrid antara formalitas tradisional dengan kebutuhan modernisasi digital. Kenotariatan dihadapkan pada permasalahan validitas akta elektronik, tanda tangan digital, serta perlindungan data pribadi yang menuntut sinergi antara hukum substansial dan teknologi. Penguatan prinsip hukum di masa ini mencakup asas legalitas, profesionalitas, akses keadilan secara digital, dan perlindungan hak-hak pihak lemah dalam masyarakat, sehingga kenotariatan tidak hanya menjadi pelayanan administratif, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang responsif terhadap perubahan zaman.
Parameter hukum yang dibangun pada masa ini mengedepankan efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pelayanan publik, seiring dengan upaya integrasi sistem kenotariatan dengan teknologi informasi. Regulasi pendukung seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi kerangka normatif tambahan yang menuntut penyesuaian operasional kenotariatan secara menyeluruh. Aspek perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada klien, tetapi juga pada legitimasi jabatan notaris dalam menghadapi dinamika digital.
Kerangka hukum masa kini juga mulai mempertimbangkan pluralitas budaya hukum di Indonesia, termasuk integrasi prinsip-prinsip hukum adat dan Islam ke dalam praktik kenotariatan formal. Hal ini menjadi upaya penting untuk menjaga keberlanjutan legitimasi sosial kenotariatan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Regulasi dan pengawasan profesi notaris semakin diarahkan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme yang berkelanjutan, sehingga profesi ini dapat berperan strategis dalam pembangunan hukum nasional.
Tidak dapat dipungkiri, dan merupakan suatu keniscayaan pada masa periode VI menggambarkan transformasi mendalam dalam sistem kenotariatan Indonesia yang harus menyeimbangkan antara tradisi hukum formal dengan inovasi teknologi dan tuntutan keadilan sosial. Masa kini menuntut revisi regulasi yang adaptif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem digital yang efektif agar kenotariatan dapat berperan optimal sebagai penjaga legalitas dan kepercayaan publik di era 4.0 dan seterusnya. Periode ini merupakan titik kritis bagi pembaruan hukum nasional dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045 yang mengedepankan harmonisasi dan integrasi sistem hukum modern dan kearifan lokal.
Memasuki era digital, kenotariatan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menghadapi Oglobalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan plural. Sistem kenotariatan modern dituntut mampu mengakomodasi digitalisasi proses pembuatan akta, pengakuan tanda tangan elektronik, dan perlindungan data pribadi, sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi pelaksana serta kode etik profesi yang dikeluarkan Ikatan Notaris Indonesia menjadi landasan penting dalam menghadapi revolusi digital ini.
Prinsip hukum pada masa ini menekankan efisiensi, akses keadilan digital, legalitas modern, serta perlindungan hak asasi manusia dan kelompok marjinal. Namun, integrasi teknologi dalam kenotariatan masih menghadapi hambatan regulasi dan infrastruktur, sehingga layanan kenotariatan digital belum merata dan optimal. Prospek ke depan menuntut revisi mendalam UUJN dan regulasi pendukung agar sistem kenotariatan dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif, responsif, dan inklusif dalam era digital governance
Periode VI diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menjadi landasan hukum utama kenotariatan modern Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memperkuat pengaturan kewenangan dan tanggung jawab notaris, tetapi juga mengakomodasi dinamika sosial dan teknologi yang berkembang pesat. Regulasi pelaksana dan kode etik profesi terus diperbaharui, mempertegas peran notaris sebagai pejabat umum yang wajib menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas di tengah kompleksitas tuntutan masyarakat.
Selain itu, kerangka hukum digital menjadi sorotan utama pada masa ini, dengan pengakuan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuatan dan pengesahan akta notaris. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen normatif yang memperluas cakupan hukum kenotariatan, terutama terkait validitas akta elektronik dan perlindungan data klien. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta perlunya revisi mendalam atas aturan teknis agar sesuai dengan karakteristik teknologi mutakhir. Karakter hukum pada masa ini tidak hanya didominasi oleh aspek formalitas legal, tetapi juga menuntut prinsip-prinsip keadilan substantif yang lebih luas. Asas akses keadilan digital menjadi perhatian, mengingat adanya disparitas kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kenotariatan dituntut untuk menyediakan layanan yang inklusif dan tidak diskriminatif, sekaligus menjaga perlindungan hak-hak pihak-pihak yang rentan atau marjinal. Hal ini menuntut penguatan fungsi pengawasan dan kode etik profesi untuk memastikan pelayanan notaris tetap berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.
Paradigma modern kenotariatan juga mulai memasukkan nilai-nilai pluralisme hukum, dengan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hukum Islam yang selama ini menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia. Integrasi ini memerlukan pendekatan normatif yang sensitif dan adaptif, agar praktik kenotariatan dapat mengakomodasi keanekaragaman hukum tanpa mengorbankan prinsip universal legalitas dan kepastian hukum. Dalam konteks Ius Integrum Nusantara 2045, hal ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum yang harmonis dan berkelanjutan, menggabungkan kearifan lokal dan modernitas.
Secara prospektif, tantangan terbesar di Periode VI adalah mempercepat transformasi digital kenotariatan secara menyeluruh, termasuk pengembangan sistem e-notaris yang aman dan terstandarisasi secara nasional. Perlu pula sinergi antara pemerintah, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan sektor teknologi untuk menciptakan ekosistem kenotariatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Dengan demikian, kenotariatan Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan legitimasi sosial dan legalitasnya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum nasional yang inklusif, modern, dan berkeadilan.
Era Digital dan Kenotariatan Modern
Periode VI, sebagai masa transformasi digital dan modernisasi sistem kenotariatan, dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar yang bersifat struktural dan teknis.
Pertama, transformasi digital kenotariatan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem teknologi informasi nasional yang memadai. Infrastruktur digital yang tidak merata dan disparitas kemampuan teknologi di berbagai daerah menimbulkan kesenjangan layanan, sehingga akses ke akta elektronik belum universal. Hal ini berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum dan pemerataan keadilan dalam penyelenggaraan jasa kenotariatan.
Kedua, pengaturan legal mengenai akta elektronik dan tanda tangan digital masih perlu diperkuat dan diselaraskan dengan regulasi lain, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Ketiadaan standar teknis yang jelas mengenai validitas dan keamanan dokumen elektronik dalam praktik kenotariatan berpotensi menimbulkan keraguan hukum dan risiko penyalahgunaan data. Hal ini mengharuskan pembaruan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk menjamin perlindungan hukum dan integritas dokumen.
Ketiga, tantangan sosial budaya turut memengaruhi implementasi modernisasi kenotariatan. Masyarakat Indonesia yang pluralistik dengan tingkat literasi hukum dan teknologi yang beragam membutuhkan pendekatan inklusif agar layanan kenotariatan tidak menjadi eksklusif bagi kalangan tertentu saja. Tantangan ini mengharuskan notaris dan lembaga pengawas profesi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan publik, memperkuat pendidikan dan sosialisasi, serta mengoptimalkan peran organisasi profesi sebagai mediator dan pembina profesionalitas.
Keempat, dari sisi prospek keberadaan digitalisasi kenotariatan membuka peluang besar untuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Penerapan sistem e-notaris yang terintegrasi dengan database hukum nasional memungkinkan pengurangan birokrasi, pengamanan data yang lebih baik, dan percepatan proses legalisasi dokumen. Potensi ini selaras dengan cita-cita Ius Integrum Nusantara 2045 yang menekankan integrasi sistem hukum nasional yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan keadilan sosial.
Kelima, penguatan sinergi antara pemerintah, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia, dan sektor teknologi informasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Pembentukan regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kenotariatan, akan memantapkan peran notaris sebagai penjaga legalitas dokumen dalam era digital. Dengan pendekatan strategis ini, kenotariatan Indonesia diperkirakan mampu bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang adaptif dan berkeadilan.
Keenam dan terakhir, dari hasil kajian ini kita memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif tentang perjalanan sistem kenotariatan Indonesia dari masa ke masa, sekaligus menyiapkan landasan analisis tantangan dan prospek masa depan dalam konteks Ius Integrum Nusantara 2045 yang mengedepankan integrasi hukum nasional dengan kearifan lokal dan kemajuan teknologi.
Kenotariatan dalam Gerak Transformasi Hukum Nasional menuju Ius Integrum Nusantara 2045
Evolusi hukum kenotariatan Indonesia merupakan refleksi langsung dari dinamika pembentukan sistem hukum nasional pasca-kolonial yang kompleks. Dari warisan Staatsblad hingga kodifikasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, transformasi ini memperlihatkan proses panjang penggalian identitas hukum Indonesia. Tidak sekadar mengikuti jalur legal transplant, sistem kenotariatan Indonesia telah bertransformasi menjadi legal construction—yakni suatu bentuk pemahaman hukum yang tidak hanya meniru bentuk, tetapi membangun sistem yang relevan, partisipatif, dan mencerminkan realitas sosial-politik yang berkembang di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap fase sejarahnya, dari masa transisional pasca kemerdekaan hingga era digital saat ini, sistem kenotariatan mengalami penyesuaian terhadap perubahan paradigma hukum dan kebutuhan masyarakat. Awalnya, notaris adalah representasi kekuasaan kolonial yang hanya melayani kelas sosial tertentu dalam struktur masyarakat dualistik. Namun, secara bertahap, notaris menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional, melayani seluruh warga negara dengan prinsip equality before the law. Kodifikasi melalui UUJN dan perubahannya pada 2014 tidak hanya memperkuat posisi notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga menandai upaya serius negara dalam membentuk sistem pembinaan, pengawasan, dan profesionalisme yang terukur dan berintegritas.
Selain itu, dalam konteks hukum sosial adanya perubahan ini tidak berdiri sendiri. Ia bergerak seiring dengan perubahan struktur masyarakat, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi, dan perkembangan teknologi. Tantangan yang muncul bukan hanya pada aspek formalisme hukum, melainkan juga pada kemampuan hukum untuk merespons nilai-nilai lokal, pluralitas hukum, serta penetrasi teknologi digital yang mengubah cara publik mengakses dan mempercayai dokumen hukum. Notaris dihadapkan pada realitas bahwa kekuatan otentik akta tidak hanya terletak pada materiel dan legalitas, tetapi juga pada legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sistem kenotariatan harus dilihat bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai pranata hukum yang berperan strategis dalam menjamin keadilan substantif.
Dengan demikian, dalam kerangka Ius Integrum Nusantara 2045—yakni suatu visi besar integrasi sistem hukum Indonesia yang utuh, berakar pada tradisi hukum nasional, tetapi terbuka terhadap perkembangan global dan digital—kenotariatan memiliki posisi penting sebagai trustee keadilan dan legalitas dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Transformasi digital tidak dapat dihindari, dan justru menjadi kesempatan emas untuk menjadikan notaris sebagai garda depan dalam reformasi hukum berbasis teknologi. Akta elektronik, tanda tangan digital, dan layanan e-notariat merupakan ekspresi dari evolusi hukum ke arah legal tech yang tetap menjunjung tinggi prinsip formalitas, keabsahan, dan perlindungan hukum.
Namun, peluang ini hanya akan optimal bila dibarengi dengan pendekatan kebijakan hukum yang integratif, adaptif, dan berbasis data. Reformulasi UUJN untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kearifan lokal, peningkatan kapasitas organisasi profesi, dan sistem pengawasan yang independen, adalah syarat mutlak menuju sistem kenotariatan yang kuat. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital dan literasi hukum masyarakat harus menjadi agenda prioritas agar sistem kenotariatan dapat hadir sebagai pelayan hukum yang inklusif, transparan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat.
Kemudian dari hasil kajian ini kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi sistem kenotariatan tidak dapat dipisahkan dari visi besar pembangunan hukum nasional Indonesia yang berpijak pada nilai keindonesiaan dan cita hukum sosial. Dalam semangat Ius Integrum Nusantara 2045, sistem kenotariatan diharapkan menjadi jangkar kepastian hukum yang tidak hanya administratif, tetapi juga etis dan transformatif. Ia harus mampu menjembatani dunia hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang berubah cepat—dan karena itu, menjadi pilar utama dalam membangun masa depan hukum Indonesia yang berkeadilan, berintegritas, dan berdaya saing global.
“Hukum bukan sekadar teks dalam pasal, melainkan cermin peradaban; dan notaris bukan sekadar penjaga legalitas, tetapi penenun kepercayaan publik dalam tenun kebangsaan. Dalam terang Ius Integrum Nusantara 2045, kenotariatan tidak hanya bertugas mengesahkan dokumen, tetapi mewariskan keadilan yang hidup, berakar pada kearifan lokal, dan menjangkau masa depan bangsa yang majemuk dan bermartabat.”
Penulis adalah Ketua Pengwil Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia
Catatan Kaki (Body Notes):
Staatsblad 1860 No. 3 dan pengaruh hukum kolonial Belanda terhadap kenotariatan, lihat Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Hukum Kenotariatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 25-35.
Lihat analisis hukum adat dan informalitas hukum di Indonesia, Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 112-125.
Studi mengenai birokratisasi hukum Orde Baru dan dampaknya pada notariat, Bambang Waluyo, Administrasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 78-89.
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan implikasinya pada sistem hukum nasional, Kompilasi UU dan Analisis, Kemenkumham RI, (Jakarta, 2004).
UU No. 2 Tahun 2014 dan penguatan pengawasan profesi melalui Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Laporan Tahunan, (Jakarta, 2015).
Studi transformasi digital dan kenotariatan modern, Triyono, Kenotariatan dan Teknologi Informasi, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 45-58.
Perbandingan regulasi kenotariatan digital di negara ASEAN, Arief Hidayat, Digital Notary Law: Comparative Study, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 112-130
Laporan evaluasi pengawasan profesi notaris di Indonesia, INI, Laporan Tahunan 2023, hlm. 40-55
Analisis integrasi hukum adat dan Islam dalam sistem hukum nasional, Siti Aminah, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 15 No. 1 (2021), hlm. 67-82.
Studi pengembangan kompetensi digital di profesi hukum, Ahmad Fauzi, Legal Tech Indonesia, (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 88-104
Kebijakan akses keadilan digital dan inklusivitas, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Strategi Nasional Reformasi Hukum 2020–2025, hlm. 73-89.
Program edukasi hukum publik dan literasi digital, Kementerian Hukum dan HAM RI, Buku Pedoman Literasi Hukum, (Jakarta, 2022), hlm. 25-40.