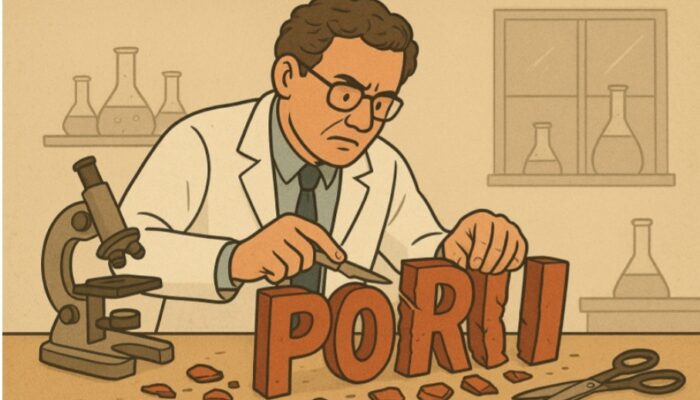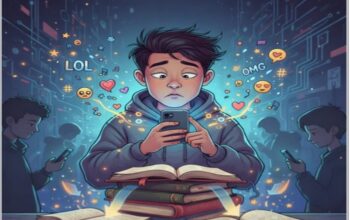Oleh: Yanhar Jamaluddin1) dan Syafrial Pasha2)
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto menempatkan “reformasi birokrasi” sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu lembaga yang paling banyak mendapat sorotan.
Narasi tentang Reformasi Polri digemakan sebagai ikhtiar untuk membentuk aparat yang profesional, berjiwa humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, sebagaimana yang kerap terjadi pada rezim-rezim setelah Reformasi 1998, semangat reformasi seringkali menjelma menjadi sekadar slogan tanpa jiwa.
Di tengah derasnya wacana efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan kinerja, muncul pertanyaan mendasar: apakah yang disebut reformasi itu sungguh mengubah struktur kekuasaan dan kesadaran birokrasi, atau sekadar memperindah wajah lama dengan sentuhan teknologi baru ?
Dalam praktiknya, reformasi birokrasi di Indonesia kerap berhenti pada tataran administratif—penyusunan standar operasional, perbaikan struktur organisasi, atau penetapan indikator kinerja—tanpa menyentuh inti persoalan yang paling mendasar: cara berpikir dan logika kekuasaan di dalamnya. Foucault (1980) pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar netral; ia bersembunyi dalam bahasa, institusi, dan prosedur yang tampak rasional di permukaan.
Dengan demikian, yang disebut reformasi acap kali tidak meruntuhkan kekuasaan lama, melainkan hanya memperhalus cara kekuasaan itu dijalankan.
Reformasi sebagai Wacana yang Membeku
Lebih dari dua puluh tahun reformasi birokrasi dijalankan di Indonesia, namun hasilnya justru menunjukkan paradoks.
Kita memiliki beragam mekanisme pengawasan, tetapi kejujuran tak bertambah; berbagai standar kinerja disusun, tetapi keberanian moral tetap langka. Reformasi berubah menjadi semacam ritual administratif—seremoni legitimasi kekuasaan—di mana pemerintah terus berbicara tentang perubahan, sementara birokrasi tetap mempertahankan hierarkinya yang tak tersentuh kritik.
Foucault dalam Power/Knowledge (1980) menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi menindas, melainkan juga menciptakan “rezim kebenaran”.
Dengan kata lain, setiap kebijakan reformasi membawa serta logika berpikir yang menormalkan perilaku dan menentukan batas antara benar dan salah.
Dalam kerangka ini, istilah seperti good governance, pelayanan publik, dan efisiensi tidak lagi netral, melainkan menjadi wacana ideologis yang membentuk cara kita memahami hakikat perubahan.
Tanpa kesadaran reflektif, reformasi birokrasi akhirnya menjelma menjadi mitos rasionalitas: kita meyakini bahwa birokrasi akan bersih jika strukturnya dibenahi, padahal yang seharusnya dikaji adalah kesadaran kekuasaan yang tersembunyi di balik struktur itu sendiri.
Dekonstruksi Birokrasi: Dari Struktur ke Makna
Pada titik inilah, gagasan dekonstruksi yang diperkenalkan Jacques Derrida (1976) menemukan relevansinya. Dekonstruksi bukanlah tindakan meruntuhkan, melainkan cara membaca kembali teks, struktur, dan makna yang selama ini dianggap mapan dan tak tergugat. Ia mengundang kita untuk bertanya: apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata indah seperti “melayani”, “tertib”, atau “efisien” ?
Birokrasi, sejatinya, adalah sebuah teks yang hidup—ia menulis, menafsirkan, dan menata ulang hubungan antara negara dan warganya. Mengikuti pemikiran Derrida bahwa “tidak ada sesuatu di luar teks” (there is nothing outside the text), maka birokrasi bukan sekadar tumpukan aturan, melainkan bahasa kekuasaan yang membentuk realitas sosial itu sendiri.
Pendekatan dekonstruktif mengajarkan bahwa setiap sistem makna selalu memuat ketegangan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Reformasi, misalnya, di permukaan tampil sebagai gerakan pembaruan, namun di baliknya sering bersembunyi nalar kontrol—kehendak negara untuk menata warga dalam bentuk-bentuk kepatuhan baru.
Mendekonstruksi birokrasi berarti membuka ruang bagi kesadaran kritis: bahwa pelayanan publik tidak seharusnya direduksi menjadi sekadar urusan efisiensi, melainkan dipahami sebagai relasi etis antara negara dan manusia. Sebab, perubahan yang sejati tidak lahir dari penyempurnaan prosedur, melainkan dari keberanian untuk menggugat dan menafsirkan ulang makna kekuasaan itu sendiri.
Reformasi Polri di Era Prabowo: Antara Efisiensi dan Sentralisasi
Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, agenda “Reformasi Polri” ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional. Berbagai langkah seperti restrukturisasi jabatan, peningkatan kesejahteraan personel, serta digitalisasi layanan publik—mulai dari SPKT Online hingga SIM Online—dikampanyekan sebagai simbol modernisasi institusional.
Namun di balik retorika efisiensi dan modernisasi tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah reformasi ini benar-benar mendorong akuntabilitas publik, atau justru memperkokoh sentralisasi kekuasaan negara?
Foucault dalam Discipline and Punish (1977) menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja lewat represi yang kasatmata, melainkan melalui mekanisme pengawasan dan normalisasi. Dalam kerangka ini, reformasi yang mengandalkan digitalisasi dan sistem pengukuran kinerja berpotensi memperluas jangkauan kontrol negara, bukan memperbesar ruang partisipasi masyarakat. Polri yang semakin efisien bisa saja bertransformasi menjadi Polri yang semakin menyeluruh dalam memantau warganya.
Terlebih lagi, dalam situasi politik kontemporer, agenda reformasi sering dijalankan seiring dengan penguatan visi strong state—negara yang kokoh, terpusat, dan menomorsatukan stabilitas dibandingkan demokrasi deliberatif. Dengan demikian, “reformasi Polri” dapat terbaca sebagai simulakra reformasi: tampak seperti pembaruan, namun sesungguhnya mengukuhkan pola lama kekuasaan yang dibungkus dengan bahasa dan teknologi baru.
Birokrasi sebagai Teks Kekuasaan
Max Weber (1978) pernah menggambarkan birokrasi sebagai puncak rasionalitas modern, namun sekaligus sebagai “sangkar besi” (iron cage)—sebuah ruang di mana manusia terperangkap dalam sistem aturan yang mereka bangun sendiri. Dalam konteks Indonesia, sangkar besi itu tidak hanya hadir dalam bentuk prosedur administratif, tetapi juga dalam budaya hierarki, loyalitas personal, dan patronase yang menutup ruang bagi meritokrasi sejati.
Birokrasi—termasuk di dalamnya Polri—berfungsi sebagai teks kekuasaan yang terus menulis ulang dan menghapus batas antara negara dan rakyat. Ia memiliki narasi, simbol, serta ritual yang menanamkan makna kepatuhan dan reproduksi kekuasaan. Karena itu, melakukan dekonstruksi terhadap birokrasi berarti menggugat narasi-narasi tersebut: mempertanyakan klaim netralitas birokrasi yang sejatinya merupakan arena politik penuh kepentingan.
Mengikuti pemikiran Derrida, dekonstruksi membuka kemungkinan bagi munculnya yang tertunda—yakni makna-makna yang selama ini diabaikan atau disisihkan. Dalam konteks birokrasi, yang tertunda itu adalah suara publik, pengalaman warga, dan dimensi etika kemanusiaan yang tidak pernah tercermin dalam dokumen-dokumen reformasi yang formal dan teknokratis.
Dari Reformasi ke Kesadaran Dekonstruktif
Reformasi yang sejati tidak berhenti pada penataan sistem, melainkan menata kesadaran manusia di dalamnya. Ia menuntut keberanian untuk mempertanyakan hakikat kekuasaan, bukan sekadar mengubah bentuk dan strukturnya. Pada titik inilah muncul kebutuhan untuk bergerak dari sekadar reformasi birokrasi menuju dekonstruksi birokrasi—yakni dari perubahan yang bersifat struktural menuju pembacaan ulang atas makna-makna dasar yang membangun logika birokrasi itu sendiri.
Reformasi Polri dan birokrasi nasional hanya akan memiliki makna apabila disertai dengan perubahan etika kekuasaan: bergeser dari logika pengawasan menuju logika pelayanan, dari hierarki menuju partisipasi, dari ketertiban yang semu menuju keadilan yang reflektif.
Yang dibutuhkan bukanlah semakin banyak prosedur, melainkan semakin banyak kesadaran. Tidak cukup hanya menciptakan birokrasi yang bersih, tetapi birokrasi yang mampu jujur terhadap makna kekuasaannya sendiri.
Dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan birokrasi, tetapi untuk membebaskannya dari mitos rasionalitas yang mengekang ruang kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang tidak pernah direfleksikan akan selalu menemukan cara baru untuk mempertahankan dirinya—bahkan melalui sesuatu yang disebut “reformasi”.
Epilog: Dari Teks ke Kesadaran Publik
Reformasi birokrasi di era Prabowo sebenarnya dapat menjadi momentum penting, asalkan dipahami melalui kesadaran dekonstruktif—yakni kesadaran bahwa perubahan sejati tidak lahir dari meja rapat atau deretan dokumen kebijakan, melainkan dari tumbuhnya kesadaran publik yang kritis terhadap makna dan cara kerja kekuasaan.
Selama reformasi terus dimaknai sebatas efisiensi administratif dan bukan sebagai praksis etika, birokrasi akan tetap menjadi teks yang menuliskan kepatuhan, bukan kebebasan.
Mungkin di sinilah tanggung jawab kaum intelektual publik: untuk terus membaca ulang teks birokrasi dengan pandangan yang jernih dan keberanian yang jujur. Sebab, setiap upaya reformasi yang tidak disertai dengan dekonstruksi pada dasarnya hanya akan melahirkan bentuk kekuasaan baru—lebih lembut, lebih canggih, namun tetap menundukkan. (1) Ketua Pusat Kajian MAP-UMA dan Sekjen PB. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, 2) Etnografer Sumatera Utara)