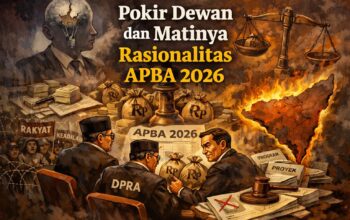Oleh: Farid Wajdi
Di ujung Sumatera, bumi menangis. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diterjang hujan deras tanpa henti. Sungai-sungai yang biasanya tenang kini berubah menjadi monster yang menelan kampung, rumah, jembatan, dan ladang.
Banjir dan longsor menelan ratusan nyawa, memaksa jutaan orang mengungsi, dan merampas harapan ribuan keluarga. Anak-anak berjalan di genangan, ibu-ibu menatap langit tanpa tahu kapan air akan surut, sementara lansia terjebak di rumah mereka yang retak dan terancam roboh.
Di tengah kepedihan ini, pemerintah pusat menolak menaikkan status bencana menjadi Bencana Nasional, seolah angka korban dan luas wilayah yang terdampak belum cukup untuk membuka pintu solidaritas dan bantuan maksimal (Detik.com, 2025).
Keputusan ini bukan sekadar istilah administratif. Ia menyingkap pilihan nilai bangsa: antara empati dan birokrasi, antara tanggung jawab konstitusional dan rasa takut pejabat akan tanggung jawab fiskal. Ia mempertanyakan kembali: apakah nyawa dan masa depan rakyat dianggap lebih rendah daripada prosedur dan kepentingan politik?
Hukum, Empati, dan Solidaritas yang Tertunda
Kerangka hukum Indonesia telah menyiapkan instrumen untuk menghadapi bencana berskala nasional. Undang-Undang Penanggulangan Bencana menetapkan lima kriteria utama: jumlah korban, kerugian materi, kerusakan infrastruktur, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial-ekonomi yang signifikan (Tempo.co, 2025).
Banjir dan longsor di Sumatera jelas melewati semua kriteria itu. Rumah-rumah hancur, jalan dan jembatan putus, ribuan orang kehilangan mata pencaharian, dan layanan dasar terganggu. Kerusakan melintasi kabupaten dan provinsi, bukan hanya di satu wilayah administratif.
Namun pimpinan lembaga mitigasi bencana menyatakan peristiwa ini tidak dikategorikan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah dianggap masih mampu menangani situasi (Detik.com, 2025).
Artinya, instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi rakyat tidak dijalankan secara konsisten. Status nasional, yang seharusnya menjadi jaminan perlindungan rakyat, menjadi subjek pertimbangan politik: apakah cukup parah untuk diakui secara resmi atau tidak.
Status nasional bukan soal angka atau pasal undang-undang. Ia soal kemanusiaan: ketika krisis melampaui kapasitas lokal, negara harus hadir penuh, tanpa kompromi. Status nasional membuka akses anggaran darurat, koordinasi logistik terpusat, pengerahan tenaga dan alat besar-besaran, serta prioritas pemulihan layanan dasar. Ia adalah bukti nyata bahwa rakyat yang terkena bencana tidak dibiarkan sendirian (Tribun Aceh, 2025).
Bupati Aceh Utara bahkan menitikkan air mata saat mengaku angkat tangan karena banjir tak kunjung surut dan bantuan pusat lambat datang (Tribun Aceh, 2025). Pernyataan itu bukan retorika, tetapi cermin kegagalan struktural: warga bertahan di tengah genangan sementara keputusan yang bisa menyelamatkan nyawa ditunda.
Seorang akademisi hukum menekankan bahwa banyak praktisi hukum tidak memahami prinsip keadaan darurat, padahal instrumen hukum sudah tersedia. Keengganan negara menggunakan hukum darurat menunjukkan jurang antara aturan di atas kertas dan realitas di lapangan.
Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal empati yang tertunda. Status Bencana Nasional adalah tanda bahwa negara mendengar tangisan rakyatnya, memberikan prioritas, dan memastikan korban tidak merasa ditinggalkan sendirian. Ketika status itu ditahan, solidaritas resmi dan akses dana darurat tertunda, memperpanjang penderitaan yang seharusnya bisa diminimalkan.
Politik, Birokrasi, dan Pilihan Moral
Penundaan status nasional mencerminkan ketakutan pemerintah: risiko fiskal, tanggung jawab hukum, dan pengawasan publik.
Status nasional membuka akses anggaran darurat dan audit publik ketat, yang dianggap berisiko oleh pejabat birokrasi. Namun moralitas negara bukan soal kompromi anggaran atau reputasi pejabat.
Ketika warga menghadapi banjir dan longsor, anak-anak kehilangan sekolah, warga kekurangan pangan dan air bersih, negara harus hadir tanpa menunda. Penolakan status nasional juga menandai kegagalan struktural: mitigasi risiko lemah, tata ruang dan pengelolaan lingkungan buruk, serta izin tambang dan perkebunan yang memperparah bencana. Kerusakan ekologis ini adalah tanggung jawab negara, bukan semata warga atau pemerintah daerah (CNN Indonesia, 2025).
Di negara tetangga, respons cepat menjadi bukti bahwa keputusan status nasional bukan sekadar formalitas. Thailand mengalokasikan miliaran rupiah untuk korban banjir bandang, sementara Sri Lanka menetapkan status bencana nasional ketika bencana besar terjadi (Detik.com, 2025).
Indonesia tertinggal dalam memanfaatkan kapasitas hukum dan negara untuk bencana berskala besar.
Menunda status nasional bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah pertaruhan legitimasi moral. Ketika negara menahan instrumen hukum saat rakyat paling rentan, janji perlindungan publik terasa hampa.
Publik bertanya: apakah keselamatan warga atau stabilitas birokrasi yang lebih diprioritaskan? Jika pola ini terus berulang, instrumen hukum darurat dan status nasional akan menjadi formalitas kosong.
Status Bencana Nasional adalah jembatan antara hukum, kemanusiaan, dan solidaritas. Penolakan menaikkan status bencana meskipun bukti nyata ada menunjukkan bahwa birokrasi dan kalkulasi anggaran lebih diutamakan daripada nyawa warga.
Jika negara sungguh peduli, langkahnya jelas: tetapkan status Bencana Nasional sekarang juga, tanpa menunggu prosedur atau pertimbangan politik. Korban membutuhkan lebih dari janji; mereka membutuhkan tindakan nyata.
Menunda keputusan dalam bencana berskala besar bukan netral. Itu adalah pilihan dan pilihan itu berbicara keras tentang prioritas negara: manusia atau formalitas, empati atau kalkulasi politik.
Setiap detik yang terbuang adalah waktu yang hilang bagi penyelamatan, rehabilitasi, dan keadilan. Bagi keluarga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, penundaan itu bisa menjadi perbedaan antara harapan dan keterlantaran. Keberanian moral harus mengalahkan perhitungan administratif. Dalam bencana sebesar ini, kecepatan, komitmen, dan empati bukan pilihan; itu adalah kewajiban negara.
Ini bukan sekadar opini. Ini seruan agar bangsa ini membuktikan bahwa prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak kosong, bahwa nilai kemanusiaan, solidaritas, dan empati bukan retorika semata.
Status Bencana Nasional harus segera ditetapkan, bukan karena hukum menuntut, tetapi karena hati nurani menuntut.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU