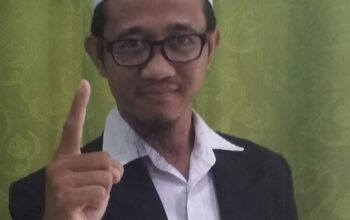Oleh Yanhar Jamaluddin 1), Syafrial Pasha2)
KETERBUKAAN informasi seharusnya bukan sekadar penyediaan data, tetapi proses yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tanpa partisipasi aktif dan akses yang setara, keterbukaan hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Artikel ini menawarkan pembacaan dekonstruktif terhadap peristiwa besar dalam praktik suap aparat penegak hukum dalam perkara korupsi. Dengan menggunakan pendekatan Dekonstruksi Jacques Derrida, adalah pendekatan kritis yang bertujuan untuk membongkar struktur makna yang mapan dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan untuk mencari makna baru dan tidak terduga dari sebuah teks atau fenomena.
Karena itu artikel ini menunjukkan bahwa teks-teks hukum tidak netral, melainkan menjadi alat representasi kekuasaan yang menyingkirkan rakyat sebagai subjek utama.
Peristiwa ini tidak hanya memuat pasal-pasal hukum, tetapi juga menyimpan jejak-jejak kekuasaan peradilan. Sementara itu, ketika teks hukum dijadikan komoditas maka institusi peradilan menjadi simulasi dari keadilan itu sendiri. Artikel ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus dibaca sebagai pertarungan wacana antara rakyat dan penguasa.
Dalam era pasca-kebenaran (post-truth), institusi-institusi formal kehilangan wibawa epistemologisnya. Negara, yang semula dianggap sebagai penjaga keadilan, justru tampak semakin jauh dari rakyatnya.
Praktik suap di ranah hukum memperkuat kecurigaan publik bahwa hukum telah kehilangan integritas moralnya.
Tulisan ini ingin menawarkan pembacaan alternatif: bahwa krisis ini bukan hanya akibat aktor individu, tapi juga akibat struktur teks hukum itu sendiri.
Dengan memakai pendekatan dekonstruksi Derrida, kita diajak membaca hukum bukan sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai teks yang bisa digugat, diretas, dan diungkap makna-makna tersembunyinya.
Membongkar Ilusi Transparansi
Fenomena ini menunjukkan bahwa “keterbukaan” (transparansi) bisa saja dikendalikan oleh kekuasaan supaya keterbukaan itu tampak baik, padahal menyembunyikan hal lain. Ada logika dari pengucilan masyarakat (eksklusi) yang berbunyi “apa yang tidak dikatakan menjadi bagian dari strategi kekuasaan”.
Dekonstruksi tidak membuat sistem keterbukaan informasi menjadi lebih tertib—justru sebaliknya, yakni menggugat ketertiban itu untuk menguak yang tersembunyi dibaliknya, memunculkan “yang absen” dalam diskursus, dan menunjukkan bahwa keterbukaan itu sendiri bisa menjadi bentuk lain dari strategi penutupan.
Yang menjadi pertanyaan apakah keterbukaan informasi publik saat ini benar-benar memberi kuasa pada rakyat, atau hanya memperindah citra kekuasaan.
Kalau dilihat dari lensa teori principal-agent, posisi rakyat sebagai principal (pemberi amanah) justru direduksi hanya menjadi penonton dari informasi yang “dibuka” tapi tidak bisa diakses secara makna maupun dampak.
Sebab itu, informasi publik akhirnya menjadi simulakra jika meminjam istilah dari Baudrillard, yang merupakan salinan atau peniruan yang tidak lagi terhubung dengan objek aslinya, dan dapat menciptakan realitas tersendiri yang mungkin tidak mencerminkan realitas asli. Atau lebih tepatnya dinamakan “simulakra keterbukaan”, bukan hak untuk mengontrol.
Menggunakan pendekatan dekonstruksi Derrida, kita dapat melihat bahwa pertama; transparansi dapat dianggap sebagai “simulakra”, yakni keterbukaan informasi yang ditampilkan hanyalah representasi yang menutupi realitas sebenarnya.
Kedua; bahasa sebagai alat kekuasaan, yakni penggunaan istilah seperti “rahasia negara” atau “kepentingan nasional” dapat menjadi alat untuk menutup akses informasi yang seharusnya publik.
Ketiga; partisipasi publik yang semu, yakni proses yang tampak inklusif namun sebenarnya tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara bermakna.
Kebijakan publik seringkali dibungkus dalam bahasa yang tampak netral, teknokratis, dan penuh jargon. Tapi dekonstruksi mengajarkan bahwa bahasa tidak netral—ia selalu menyimpan relasi kuasa, hasrat, dan penyingkiran.
Tugas dekonstruksi adalah membuka lapisan-lapisan bahasa itu dan menunjukkan kontradiksi di dalamnya. Derrida mengkritik kecenderungan berpikir dikotomis (biner), seperti: publik vs privat, legal vs illegal, rakyat vs elit, dan militer vs sipil. Kebijakan publik sering menggunakan dikotomi ini untuk menyederhanakan realitas dan melegitimasi keputusan.
Dari hasil pembacaan di atas, kita bisa menyarankan agar ilmu administrasi publik mengadopsi sikap yang lebih reflektif dan etis:
• Meninjau ulang narasi keterbukaan: Bukan hanya prosedur, tapi harus menjamin akses publik terhadap proses pembentukan makna kebijakan.
• Membangun forum interpretatif: Rakyat bukan hanya sebagai penerima informasi, tapi sebagai penafsir kebijakan.
• Mengakui yang tak hadir: Setiap kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan siapa yang tidak terwakili dalam forum formal.
Peradilan dan Simulasi Keadilan: Bahasa yang Diperjualbelikan
Kasus suap aparat penegak hukum dalam berbagai perkara akhir-akhir ini, termasuk korupsi CPO, menunjukkan bagaimana hukum telah menjadi simulasi.
Istilah-istilah seperti “proses hukum,” “putusan final,” atau “putusan inkrah” menjadi penanda kosong—signifiers without substance. Mereka tampak menjanjikan keadilan, tapi kenyataannya dikendalikan oleh uang.
Derrida menyebut bahwa makna selalu tertunda dan ditunda (différance), tidak pernah hadir utuh. Maka keadilan dalam ruang hukum formal selalu berjarak dari rakyat.
Apalagi ketika keputusan hukum didasarkan pada transaksi tersembunyi, makna keadilan menjadi hantu yang mengecoh—seperti specter dalam Specters of Marx.
Kita hidup dalam bayang-bayang hukum, bukan dalam kehadirannya yang utuh. Dengan kata lain, keadilan tidak pernah tiba, ia hanya dijanjikan. Maka publik tidak melihat realitas hukum, tetapi hanya tiruannya, yang terus-menerus direproduksi oleh media, institusi, dan aparat hukum.
Praktik suap dalam aparat penegak hukum terkait korupsi menunjukkan bagaimana hukum telah menjadi simulasi dari keadilan itu sendiri. Seperti dalam teori Deliberative Governance yang mengedepankan dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah, proses hukum yang penuh transaksi gelap justru menyingkirkan suara masyarakat yang seharusnya hadir dalam pengambilan keputusan. Simulasi keadilan ini menjauhkan rakyat dari proses hukum yang seharusnya mereka awasi dan kontrol.
Dekonstruksi Derrida mengungkapkan bahwa makna keadilan dalam hukum selalu tertunda, selalu dikelola dan dimanipulasi dalam lingkup kekuasaan. Sehingga, pada akhirnya, kita tidak berhadapan dengan keadilan itu sendiri, tetapi dengan sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh kekuasaan untuk mempertahankan status quo.
Keterbukaan informasi publik yang secara legal dijamin, ternyata secara praktis dikonstruksi ulang oleh kekuasaan dalam bentuk yang manipulatif. Wacana keterbukaan hanya digunakan sebagai pembungkus etis, sementara praktiknya dijalankan secara tertutup dan eksklusif.
Maka terjadi apa yang Derrida sebut sebagai “permainan tanda” (jeu des signes)—di mana makna kebenaran dan transparansi diputar untuk membela kekuasaan, bukan rakyat.
Kasus demi kasus yang tak bisa dikonfirmasi secara terbuka, hingga perkara hukum yang dibeli dengan uang, semuanya menunjukkan satu hal: rakyat tidak lagi menjadi subjek utama hukum, melainkan objek dari permainan bahasa kekuasaan.
Administrasi publik tidak hanya menyangkut implementasi kebijakan, tetapi juga produksi dan pengelolaan simbol-simbol negara (seperti transparansi, akuntabilitas, legalitas).
Derrida mengajarkan bahwa simbol-simbol ini tidak pernah netral. Maka dalam administrasi publik, bahasa birokrasi dan hukum adalah arena kontestasi makna, bukan hanya alat manajemen.
Contoh konkret: Korupsi peradilan yang diputus secara diam-diam bukan hanya masalah prosedural, tetapi memperlihatkan bagaimana simbol “partisipasi publik” atau “keterbukaan” digunakan secara selektif.
Dekonstruksi sebagai Metode Kritik Terhadap New Public Management (NPM)
Pendekatan NPM mengedepankan efisiensi, privatisasi, dan manajemen berbasis pasar.
Tapi dengan pendekatan dekonstruksi, kita bisa bertanya: siapa yang ditinggalkan dari narasi efisiensi itu? Apakah rakyat sebagai principal benar-benar ikut serta, atau hanya menjadi statistik?
Maka dari itu, ketika kebijakan publik dibuat dalam ruang tertutup dan keadilan dijalankan dengan transaksi gelap, NPM tidak cukup. Diperlukan pendekatan dekonstruktif untuk membuka kemungkinan-pengertian baru tentang akuntabilitas—yang tidak direduksi hanya menjadi angka laporan, tetapi pengakuan yang akan disingkirkan.
Administrasi publik sering mengklaim bahwa mereka melayani masyarakat, tapi siapa sebenarnya yang mereka representasikan? Derrida akan bertanya: Apakah “masyarakat” itu satu suara? Ataukah ada suara-suara yang dikorbankan demi kepentingan representasi mayoritas?
Dalam kasus korupsi hakim misalnya, suara korban kejahatan dan masyarakat umum tidak pernah benar-benar hadir dalam sistem peradilan. Yang hadir hanyalah representasi simbolik yang telah direkayasa.
Melalui dekonstruksi Derrida, kita bisa mengkritik administrasi publik yang tidak hanya bertumpu pada prosedur teknis, tetapi juga membuka ruang bagi dialog, inklusivitas, dan pemerataan kuasa.
Dalam hal ini, administrasi publik yang baik bukan hanya tentang menjalankan kebijakan, tetapi tentang memastikan suara rakyat tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap proses pembuatan keputusan.
Kesimpulan
Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik, yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam praktik administrasi publik, sering kali terhambat oleh struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik teks-teks hukum dan kebijakan.
Pendekatan dekonstruksi Derrida memungkinkan kita untuk melihat bahwa kebijakan publik, yang tampak rasional dan objektif, sebenarnya sering kali menyembunyikan makna-makna yang terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan yang ada.
Kasus korupsi dalam peradilan dan ketidaktransparanan dalam penegakan hukum mengilustrasikan praktik administrasi publik di Indonesia, meskipun secara formal mengklaim keterbukaan, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang esensial dalam teori administrasi publik.
Lebih jauh lagi, dalam konteks teori Principal-Agent, kita melihat bahwa rakyat (principal) sering kali teralienasi dalam hubungan dengan negara (agent), yang seharusnya bertugas melayani dan mengawasi kepentingan mereka.
Dekonstruksi dalam ilmu administrasi publik, yang menggabungkan teori Principal-Agent, Deliberative Governance, dan Ethics of Care, mengungkapkan pentingnya membongkar struktur kekuasaan yang ada, untuk membuka ruang yang lebih inklusif dan adil bagi rakyat sebagai principal yang sejati.
Hukum dan kebijakan yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat, justru sering kali dipengaruhi oleh praktik-praktik yang tidak transparan dan penuh transaksi tersembunyi. (Penulis 1) Kepala Pusat Kajian Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan 2) Etnografer Sumatera Utara)