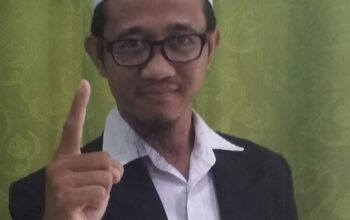Oleh Shohibul Anshor Siregar
Dalam konteks Indonesia, relasi eksploitatif dengan negara kuat seperti Prancis, melalui kerja sama pertahanan dan investasi tanpa alih teknologi, mencerminkan bahaya kolonialisme bentuk baru
Scroll Untuk Lanjut MembacaIKLAN
Artikel ini membahas figur Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traoré, sebagai simbol perlawanan dunia Selatan terhadap dominasi pengetahuan, ekonomi, dan militer global. Dalam konteks perjuangan anti-kolonial baru, Traoré menyoroti pentingnya pendidikan yang membebaskan, pengetahuan lokal yang terpinggirkan, serta kemerdekaan ekonomi dari sistem global yang eksploitatif.
Analisis ini diperdalam melalui gagasan Fadhel Kaboub tentang “kesenjangan abadi” dan usulan penghapusan utang, serta Thomas Piketty tentang ketimpangan struktural akibat warisan kolonialisme. Secara khusus, artikel mengaitkan dinamika ini dengan kondisi Indonesia, termasuk ketergantungan pada Prancis dalam bidang persenjataan tanpa jaminan alih teknologi.
Ditekankan bahwa relasi eksploitatif dapat berulang dalam bentuk baru jika negara-negara berkembang gagal membangun kedaulatan pengetahuan, ekonomi, dan teknologi. Melalui semangat pluriversalitas, artikel ini menyerukan jalan pembebasan yang berangkat dari keberanian berpikir dan bertindak secara mandiri.
Di tengah hiruk-pikuk tatanan dunia yang dikendalikan kekuatan ekonomi dan militer global, muncul suara dari Afrika yang lantang menantang ketimpangan struktural: Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso. Bukan hanya sebagai kepala negara termuda di dunia, tetapi sebagai simbol gerakan baru dari Global Selatan, yang menuntut keadilan ekonomi, kedaulatan epistemik, dan pembebasan dari cengkeraman kolonialisme bentuk baru.
Memulihkan pengetahuan yang dihapuskan dan perlawanan epistemik adalah perjuangan besar. Bayangkan sebuah perpustakaan digital yang megah, penuh situs web dan platform online dengan tampilan menarik darri segi warna-warni. Namun, di balik keindahan visualnya, banyak konten yang justru mencerminkan pengetahuan yang dihapuskan. Situs-situs pendidikan online yang didominasi kurikulum Barat, mengabaikan pengetahuan lokal dan adat. Platform media sosial yang algoritmanya memperkuat bias global, menenggelamkan suara-suara dari komunitas terpinggirkan.
Website berita internasional yang narasinya berpusat pada negara-negara maju, mengabaikan isu-isu penting di Global South. Platform e-commerce yang mempromosikan produk-produk asing, mengancam keberlangsungan ekonomi lokal. Keindahan visual dan teknologi canggih ini menjadi kedok bagi imperatif asing yang menundukkan peradaban baru, menciptakan sebuah paradoks: teknologi yang seharusnya memberdayakan, justru memperkuat ketidaksetaraan dan penghapusan pengetahuan.
Perlawanan epistemik dalam konteks ini adalah perjuangan untuk menciptakan platform digital yang lebih inklusif, yang mempromosikan pengetahuan lokal, memberdayakan komunitas terpinggirkan, dan membangun peradaban baru yang berakar pada nilai-nilai keadilan dan kemandirian.
Traoré mewakili gelombang pemikiran baru yang dengan berani menolak bentuk kekuasaan tersembunyi yang selama ini mengakar kuat: dominasi pengetahuan Barat atas dunia Selatan. Dalam lanskap pendidikan dan informasi global, pengetahuan lokal, yang diwujudkan dalam bahasa ibu, sejarah komunitas, sistem nilai adat, dan cara hidup tradisional, seringkali dipinggirkan, dianggap tidak ilmiah, atau bahkan dihapuskan. Penyingkiran ini bukanlah sekadar kelalaian, melainkan bentuk kekerasan epistemik: sebuah proses sistemik di mana keragaman cara memahami dunia dikikis demi satu standar “rasionalitas” yang dibentuk oleh sejarah kolonial dan logika pasar global.
Dalam pidato-pidatonya yang tegas, Traoré menyerukan revolusi pendidikan di benua Afrika. Bagi dia, pendidikan tidak boleh lagi menjadi alat untuk mencetak buruh murah bagi pasar global yang eksploitatif, melainkan harus menjadi instrumen pembebasan yang menumbuhkan kesadaran historis, memperkuat jati diri budaya, dan membangun solidaritas di antara masyarakat yang selama ini tercerai-berai oleh warisan kolonial. Ia menolak sistem pendidikan warisan penjajah yang hanya melahirkan elite terdidik yang terasing dari realitas sosial bangsanya sendiri, mereka yang lebih fasih mengutip Voltaire daripada mendengar jeritan petani lokal.
Gagasan Traoré mengingatkan pada pemikiran tokoh dekolonial seperti Ngũgĩ wa Thiong’o, Frantz Fanon, hingga Paulo Freire—yang menyatakan bahwa pendidikan sejati adalah proses menyadari penindasan dan kemudian bertindak untuk mengubahnya. Dalam konteks ini, revolusi pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau metode belajar, melainkan upaya menyusun ulang relasi kekuasaan global, dari dominasi ke dialog, dari pemaksaan ke pengakuan akan keberagaman pengetahuan.
Traoré membawa pesan yang lebih luas: bahwa bangsa-bangsa yang ingin merdeka sepenuhnya harus memerdekakan cara berpikir mereka terlebih dahulu. Tanpa pembebasan epistemik, tidak akan ada pembebasan ekonomi, politik, atau budaya yang sejati.
Apa yang disuarakan Traoré bergema dalam analisis para ekonom kritis dari Global Selatan. Fadhel Kaboub, ekonom Tunisia, mengungkap bagaimana negara-negara berkembang terperangkap dalam sistem global yang dirancang agar mereka tetap bergantung. Ia menyebut situasi ini sebagai “kesenjangan abadi” (permanent gap): negara miskin dipaksa mengekspor bahan mentah, mengimpor barang jadi, berutang kepada lembaga internasional, lalu disyaratkan menjalankan kebijakan yang justru mengikis kedaulatan mereka sendiri.
Kaboub mengajukan solusi radikal: penghapusan utang luar negeri, penguatan kapasitas produksi lokal, dan kemandirian fiskal. Baginya, selama negara-negara Selatan masih bergantung pada bantuan dan investasi asing tanpa kontrol, mereka akan tetap menjadi pasar dan ladang eksploitasi.
Sejalan dengan itu, Thomas Piketty, ekonom Prancis, mengingatkan bahwa ketimpangan global adalah warisan historis kolonialisme dan kapitalisme. Dalam Capital and Ideology, ia menegaskan bahwa akumulasi kekayaan di negara-negara kaya tidak lepas dari penjajahan dan eksploitasi panjang atas dunia Selatan. Ia mendorong pajak kekayaan global dan redistribusi internasional sebagai mekanisme korektif.
Indonesia pun tidak imun terhadap jebakan ini. Dalam era modern, bentuk kolonialisme tidak selalu berwujud pendudukan militer, melainkan melalui perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri yang bersyarat. Prancis, yang pernah menjajah Indonesia secara de jure melalui pemerintahan Daendels (1806–1811), kini kembali hadir dalam wujud kerjasama pertahanan dan investasi strategis. Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale dan kapal selam dari perusahaan pertahanan Prancis.
Namun, di balik kemegahan kerja sama militer ini, muncul pertanyaan kritis: apakah ada jaminan alih teknologi? Apakah Indonesia akan terus bergantung pada sistem luar dalam merancang dan memelihara pertahanannya? Ataukah kita hanya sedang mengulang sejarah kolonialisme dalam bentuk baru, negara lemah membeli dari negara kuat, tanpa memperoleh kemandirian jangka panjang?
Jika pembelian persenjataan dilakukan tanpa strategi teknologi dan industrialisasi jangka panjang, maka kita berisiko terjebak dalam hubungan eksploitatif seperti masa lalu. Keberadaan “bantuan modal”, utang pembelian, dan klausul tersembunyi dalam kontrak menjadi perangkat kendali yang tak kalah kuat dari pendudukan militer. Dalam hal ini, Traoré dan Kaboub memberi peringatan: negara tidak boleh mabuk ambisi modernisasi yang dikendalikan dari luar.
Ibrahim Traoré membawa wacana baru ke dalam arena geopolitik: pluriversalitas. Sebuah keyakinan bahwa dunia ini tidak tunggal (universal), tetapi jamak (pluriversal). Bahwa tidak ada satu cara membangun, berpikir, atau menjadi negara maju. Traoré menolak dikte pembangunan dari luar, dan memilih mendengar suara rakyatnya, sejarah bangsanya, dan warisan pengetahuan lokal yang selama ini dipinggirkan.
Dalam hal ini, perjuangan Burkina Faso menjadi cermin bagi Indonesia: bahwa kedaulatan sejati bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang menentukan arah berpikir dan pembangunan kita. Apakah kita percaya pada jalan sendiri, atau tetap mengekor pada pola dan sistem yang selama ini melanggengkan ketimpangan?
Di tengah krisis global (perubahan iklim, konflik, dan ketimpangan) suara-suara dari Selatan dunia seperti Traoré harus diakui sebagai suara masa depan. Ia bukan sekadar pemimpin nasional, tetapi bagian dari gerakan global yang menuntut keadilan historis. Dunia tidak bisa terus berjalan dengan sistem yang hanya menguntungkan segelintir.
Indonesia, dengan sejarah kolonial yang panjang dan posisi strategis di kawasan, punya potensi menjadi bagian dari gerakan ini. Tapi itu hanya mungkin jika kita berani mengoreksi ketergantungan, mengembangkan ekonomi mandiri, dan membangun sistem pengetahuan yang menghargai akar budaya sendiri.
Maka, sebagaimana Traoré menyatakan: “Kita tidak bisa menunggu orang lain membebaskan kita. Pembebasan sejati dimulai dari keberanian berpikir sendiri.” Sebuah pesan sederhana, namun dalam. Sebuah peringatan sekaligus harapan.
Ibrahim Traoré bukan sekadar pemimpin muda dari Afrika Barat; ia mewakili suara yang menolak sistem global yang selama ini menundukkan negara-negara Selatan melalui kekerasan epistemik, ketimpangan ekonomi, dan dominasi militer. Gagasan Fadhel Kaboub dan Thomas Piketty menegaskan bahwa ketimpangan bukan kecelakaan sejarah, melainkan akibat desain sistemik yang mempertahankan ketergantungan.
Dalam konteks Indonesia, relasi eksploitatif dengan negara kuat seperti Prancis, melalui kerjasama pertahanan dan investasi tanpa alih teknologi, mencerminkan bahaya kolonialisme bentuk baru. Indonesia perlu belajar dari peringatan ini: bahwa kemerdekaan sejati menuntut keberanian berpikir mandiri, membangun ekonomi berbasis produksi sendiri, serta merdeka dalam menentukan arah pengetahuan dan pembangunan. Hanya dengan itulah negara-negara Selatan bisa keluar dari bayang-bayang sejarah dan menulis masa depannya sendiri.
Jangan lupa, Prancis adalah salah satu negara yang dominasinya direduksi tajam di Burkina Faso, negara yang dipimpin oleh Traoré, anak desa yang cuma berpangkat kapten itu.
Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).